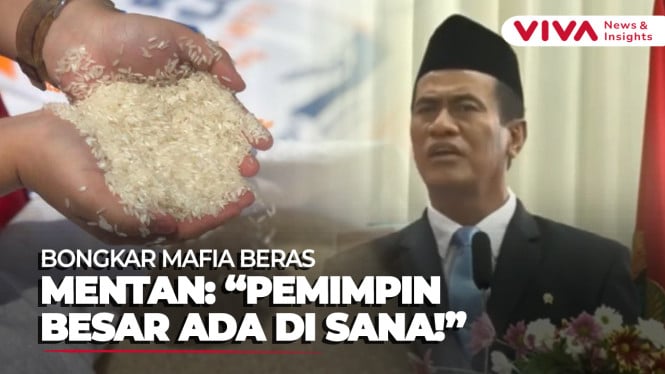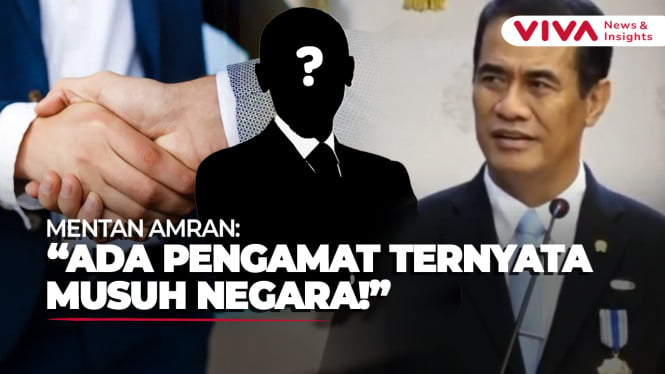Dari Perspektif Freud ke Feed: Memahami Craving Digital dalam Bermedia Sosial
- vstory
VIVA – Sebuah gejala di mana seseorang terus menerus memeriksa Instagram pribadinya hanya untuk melihat siapa saja yang telah menonton (views) story-nya, memberikan likes dan komentar pada unggahan postingannya, mungkin semakin sering kita temui dalam kehidupan bermedia sosial saat ini.
Kebutuhan akan sebuah validasi sosial menjadi hasrat tersendiri di era digital yang saling terhubung di mana media sosial bukan hanya sebagai alat berkomunikasi, tetapi juga telah mampu untuk berevolusi menjadi ruang konsumsi emosional, tempat lahirnya sebuah pencitraan diri dan bisa dianalogikan sebagai arena pertarungan antara kesadaran dan dorongan bawah sadar manusia.
Platform media sosial seperti Instagram misalnya sebagai salah satu contoh, tidak hanya membentuk bagaimana seseorang itu berinteraksi, tetapi juga membuat para penikmatnya menjadi terkontaminasi dengan pola dan cara untuk merasa, berpikir, dan bahkan menilai diri mereka sendiri.
Salah satu fenomena yang paling menonjol dari transformasi digital ini adalah bagaimana perilaku craving digital (kelaparan atau kecanduan) yang lebih luas dapat diartikan sebagai keinginan kuat atau kebutuhan mendesak untuk mendapatkan perhatian terhadap interaksi atau stimulus digital, seperti terus menerus melakukan scrolling, bermain game atau mengecek notifikasi. Terkadang hal ini tidak selalu tentang validasi, tetapi juga tentang ketergantungan akan perangkat digital untuk mendapatkan hiburan atau kepuasan secara instan. Dalam konteks Kebutuhan validasi biasanya hadir berupa likes, komentar, jumlah followers, story views, atau bahkan balasan berbentuk DM (Direct Message) di mana setiap notifikasi yang hadir seakan menjadi stimulus kecil yang dapat meningkatkan dopamine rush (sensasi kebahagiaan), yaitu sebuah kondisi di mana pelepasan zat kimia di otak dapat menciptakan perasaan bahagia sesaat. Meski terlihat sederhana, namun dapat memberi, efek yang luar biasa dan sangat kuat dalam mempengaruhi suasana hati, produktivitas, image bahkan harga diri seseorang.
Dalam perspektif neurologi (sebuah cabang kedokteran yang mempelajari sistem saraf), craving ini memiliki dasar biologis yang nyata. Dopamin (hormon kebahagiaan) sendiri adalah bagian dari sistem penghargaan otak yang memotivasi kita untuk mengulang pengalaman menyenangkan yang kita dapatkan dalam situasi dan kondisi tertentu. Kehadiran media sosial dengan sengaja dirancang untuk memicu mekanisme ini secara konsisten melalui apa yang disebut sebagai intermittent reinforcement yakni sebuah pemberian hadiah sosial secara acak (random) dan tidak terduga. Karena dalam hal ini, pengguna tidak tahu kapan mereka akan menerima validasi (misalnya, unggahan mana yang akan mendapat banyak likes, komentar atau siapa yang akan menanggapi story), mereka cenderung akan terus mengecek aplikasi serta membentuk kebiasaan yang nyaris refleksif atau dapat dikatakan sebagai sebuah sikap yang menunjukkan sesuatu secara otomatis dan spontan.
Craving Validation ini tidak hanya bekerja di level biologis. Jika kita melihatnya dari sudut pandang psikologi klasik, khususnya Teori Psikoanalisis yang dipopulerkan oleh Sigmund Freud, tentu kita dapat memahami dimensi berbeda dalam kacamata yang lebih dalam dan luas. Freud membagi struktur psikis manusia ke dalam tiga elemen utama yaitu: id, ego, dan superego.
Dalam konteks perilaku penikmat media sosial, id berperan sebagai sumber dorongan naluriah dan impulsif yang selalu mencari kesenangan secara instan, seperti saat kita termotivasi untuk terus melakukan scroll, menyimak, atau membagikan konten di feed agar diperhatikan. Dari sisi Ego, para pengguna berusaha untuk mengatur realitas, membatasi waktu dan juga menjaga logika namun mungkin seringkali kalah oleh algoritma digital yang sengaja menciptakan lingkungan yang secara hasrat penuh dengan emosional. Sementara itu, Superego muncul saat kita merasa bersalah setelah terlalu lama menyimak, atau bahkan sudah mulai untuk membandingkan diri dengan kehidupan “sempurna” yang ditampilkan orang lain, salah satu contohnya bagaimana gejala FOMO (Fear Of Missing Out) muncul ketika seseorang merasa ketakutan tidak bisa mengikuti sebuah tren yang sedang terjadi.
Menyimak media sosial secara pasif sebenarnya merupakan aktivitas kompleks yang melibatkan tarik-menarik antara dorongan bawah sadar dan juga kontrol terhadap diri. Dalam kondisi ini, pengguna tidak hanya menjadi konsumen yang dapat melahap sebuah konten, tetapi juga mampu menginternalisasi tekanan sosial, ekspektasi citra diri yang terbentuk serta hadirnya standar kesuksesan yang sering kali tidak realistis. Bagi sebagian orang, craving ini menjadi pelarian dari rasa cemas, kesepian, atau stagnasi (istilah kekinian yang sering terucap dengan statement gini-gini aja tidak ada perubahan) dalam kehidupan nyata. Hal inilah yang kemudian menjadikan pengguna haus akan validasi (craving validation) di media sosial yang bukan sekadar sebagai gejala perilaku digital biasa, melainkan bentuk konsumsi psikis yang bisa berimplikasi serius terhadap keseimbangan mental.
Fenomena yang masif ini semakin relevan jika kita kaitkan dengan data dan laporan tentang krisis kesehatan mental global yang saat ini sudah menjadi pandemi. World Health Organization (WHO) dalam World Mental Health Report 2022 menyebutkan bahwa satu dari delapan orang di dunia saat ini hidup dengan gangguan mental, dan angka tersebut meningkat tajam seiring berlalunya pandemi COVID-19. WHO juga menyoroti bahwa isolasi sosial, munculnya ketidakpastian ekonomi secara global, serta lonjakan pengguna media sosial selama masa pandemi semakin memperluas kondisi ini. Terlebih saat ini banyak remaja dan dewasa muda ,mengalami peningkatan stres, depresi, gangguan tidur, hingga krisis identitas akibat paparan dan konsumsi akan media sosial yang terlalu intens.
Di sinilah kita perlu mempertanyakan, sejauh mana craving ini merupakan bagian dari sifat manusia, dan sejauh mana ia dimanfaatkan oleh sistem digital modern? perusahaan teknologi tentu memahami betul bagaimana emosi manusia bekerja, mereka menggunakan data perilaku pengguna untuk menciptakan pengalaman digital yang semakin dipersonalisasi, tetapi juga semakin manipulatif di era digitalisasi yang dibungkus dengan kapitalisme. Algoritma disusun sedemikian rupa untuk menahan atensi pengguna selama mungkin di dalam aplikasi. Bahkan istilah “ekonomi perhatian (Atttention Economy)” kini menjadi dasar utama model bisnis media sosial di mana waktu dan fokus pengguna menjadi produk yang diperjual belikan kepada pengiklan. Dalam digitalisasi, banyak platform, media sosial dan perusahaan teknologi yang bersaing untuk menarik dan mempertahankan perhatian penggunanya , karena perhatian tersebut dapat dikonversi menjadi keuntungan melalui iklan, data, engagement serta loyalitas pengguna.
Terlebih hal ini diperkuat dengan data laporan digital tahun 2024, yang menyatakan bahwa rata-rata dalam sehari warganet di Indonesia menghabiskan waktunya 3 jam 11 menit untuk bermedia sosial, di mana durasi ini bisa terbilang cukup tinggi mengingat waktu rata-rata global untuk menggunakan media sosial hanya 2 jam 31 menit saja. Artinya kondisi ini menjadi lahan yang sangat subur bagi pelaku industri teknologi dalam menangkap peluang peluang kapitalisme.
Namun menyalahkan teknologi semata tentu bukan sebuah pemikiran yang dewasa,. Sebab yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita semua membangun kesadaran individu terhadap perilaku digitalnya secara personal. Menyimak feed media sosial tentu harus dilihat dari kacamata berbeda , bukan saja sebagai konteks aktivitas yang sifatnya netral, melainkan sebagai bentuk interaksi psikologis yang dapat memperkuat atau bahkan dapat berimplikasi terhadap kondisi mental pengguna, semua ini tergantung bagaimana cara dan persepektif kita dalam menyikapinya.
Menyikapi kondisi ini tentu diperlukan upaya-upaya untuk membangun relasi yang lebih sehat terhadap penggunaan media sosial. Pertama, penting untuk menyadari apa motivasi di balik setiap individu dalam melakukan tindakan digital nya. Sebelum membuka Instagram misalnya, coba tanyakan kepada diri sendiri sekaligus sebagai sebuah refleksi: “Apa yang sedang aku cari?” Jika jawabannya adalah rasa nyaman, pengakuan, atau pengalihan dari stres, maka bisa jadi craving sedang menguasai kita.
Kedua, membatasi waktu konsumsi media sosial dengan melakukan Digital Detox (sebuah kondisi di mana seseorang secara sengaja menjauhkan diri dari perangkat digital untuk meningkatkan produktivitas dan memulihkan fokus nya terhadap kehidupan), atau melalui bantuan fitur fitur seperti screen time control atau deactivate account pada settingan Instagram, yang dapat membantu mengurangi keterlibatan secara impulsif.
Ketiga, mengatur durasi akun yang telah diikuti, dengan mengutamakan konten yang lebih banyak memberi inspirasi, edukasi, atau hiburan yang sehat secara mental serta usahakan untuk menghindari konsumsi akun yang memicu kecemasan dan rasa insecure terhadap diri sendiri.
Implikasi Digital Detox yang dilakukan secara berkala bagi individu tersebut, tentu menjadi strategi yang efektif kerena mampu memulihkan kembali produktivitas secara keseluruhan serta membantu otak melepaskan diri dari pola adiktif, sekaligus memberi ruang bagi terhubungnya koneksi sosial yang lebih nyata, lebih banyak memanfaatkan aktivitas fisik, refleksi bagi pribadi serta dapat berdialog terhadap kehidupan nyata.
Sedangkan bagi sebuah komunitas atau institusi, penting juga untuk meningkatkan bagaimana literasi digital itu dapat bekerja , khususnya pemahaman tentang bagaimana media sosial bekerja, dampaknya terhadap otak dan emosi, serta cara-cara menavigasi dunia digital dengan lebih bijak. Dalam konteks Perusahaan dan brand, memahami craving digital ini seharusnya tidak semata-mata dijadikan sebagai sebuah peluang bisnis, tetapi juga sebagai tanggung jawab etis, karena penting untuk mengingat bahwa membuat konten yang menarik itu memang bagus, tetapi lebih penting lagi bagaimana menciptakan pengalaman digital yang mendukung kesejahteraan psikologis audiens, mengutamakan empati, keaslian, dan nilai yang nantinya bisa menjadi dasar dalam membangun komunikasi yang berkelanjutan dan manusiawi di ruang digital.
Akhirnya, dari perspektif Freud ke feed yang kini kita konsumsi setiap hari, dapat disimpulkan bahwa craving digital adalah realitas baru yang memerlukan kesadaran mendalam. Media sosial dapat menjadi ruang konstruktif yang mampu memperkaya cakrawala pemikiran dan pengetahuan kita dalam berkomunikasi, selama kita tidak dikendalikan oleh dorongan yang tidak kita pahami. Dengan mengenali dinamika bawah sadar, pola craving, dan strategi digital yang dapat mempengaruhi nya, maka kita bisa menjadikan dunia digital bukan hanya sebagai sebuah jebakan dopamine (kebahagiaan) semata, melainkan sebagai ruang yang sehat, bermakna, mampu memberdayakan satu sama lain serta membuka ruang dialog pikiran kita terhadap arti sebuah kehidupan nyata. Salam sehat dan berbahagia