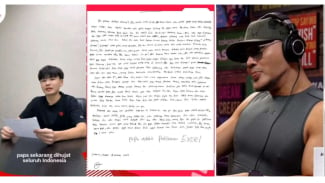Problematika Hukum dalam Pembentukan dan Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor
- VIVA/Edwin Firdaus
VIVA – Setelah reformasi tahun 1998, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda utama di Indonesia. Masa kelam Orde Baru dan maraknya korupsi di rezim otoritarian memberikan pelajaran berharga bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan. Korupsi tidak hanya merusak fondasi negara, tetapi juga menghambat upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis (democratic and clean government).
Menyadari bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, penanganannya juga harus dilakukan dengan langkah-langkah yang luar biasa. Beberapa instrumen khusus dengan kewenangan yang luar biasa pun dibentuk. Mulai dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat beberapa unsur tindak pidana korupsi hingga pembentukan instrumen khusus penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diberikan wewenang lebih besar dibanding lembaga penegak hukum konvensional seperti kepolisian dan kejaksaan.
Selain KPK, pemerintah dan DPR juga mendirikan sebuah pengadilan khusus untuk menangani perkara-perkara korupsi, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Pada awalnya, pengadilan ini dibentuk berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan: “Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutammut diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”
Namun, keberadaan pengadilan ini kemudian dianggap inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pasal tersebut telah menciptakan dualisme dalam penanganan kasus korupsi, yang berdampak pada pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara, terutama para tersangka kasus korupsi.
Putusan MK tersebut menuai banyak kritikan dan kekecewaan dari publik yang menganggapnya sebagai kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, MK tampaknya tidak ingin gegabah dan masih mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: Pertama, dampak hukum dari kekuatan mengikat Pasal 53 UU KPK harus dipertimbangkan dengan matang agar proses pengadilan korupsi yang sedang berjalan tidak terganggu atau terhenti, dan tidak menyebabkan kekacauan hukum.
Kedua, putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi harus memastikan bahwa tidak ada ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu penanganan atau pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi juga harus memastikan tidak ada dampak negatif yang melemahkan semangat pemberantasan korupsi, yang telah menjadi musuh bersama bangsa dan masyarakat Indonesia. Keempat, untuk melakukan perbaikan struktur kelembagaan KPK dan penataan kelembagaan pengadilan khusus yang diperlukan, tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat sehingga membutuhkan waktu yang cukup.
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembuat undang-undang untuk segera menyelaraskan UU KPK dengan UUD 1945 dan membentuk undang-undang khusus untuk pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Mahkamah memberikan batas waktu maksimal satu tahun sejak putusan dibacakan, tetapi pengadilan Tipikor tetap beroperasi dengan kekuatan hukum yang mengikat sampai undang-undang baru diterbitkan.
Akhirnya, DPR mengesahkan RUU Pengadilan Tipikor pada 29 Agustus 2009. Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor disahkan, mengakhiri ketidakpastian masa depan pengadilan khusus tersebut. Namun, seiring waktu, berbagai masalah mulai muncul di pengadilan Tipikor. Kinerja pengadilan ini dinilai menurun. Banyak pihak berpendapat bahwa pengadilan Tipikor kini menjadi titik lemah dalam pemberantasan korupsi.
Hal ini menjadi ironi dibandingkan dengan harapan publik saat pengadilan Tipikor didesentralisasikan ke daerah-daerah. Kinerja pengadilan Tipikor di daerah tidak sebaik ketika masih tersentralisasi di Jakarta. Banyak vonis bebas dan tertangkapnya hakim pengadilan Tipikor karena menerima suap menjadi bukti nyata berbagai masalah yang melilit pengadilan khusus yang masih berusia muda ini.
Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi salah satu masalah yang menyebabkan penurunan kinerja pengadilan Tipikor.
Pengadilan Tipikor/Ilustrasi.
- VIVA.co.id/ Edwin Firdaus
Problem Seleksi Hakim Pengadilan Tipikor
Hakim di pengadilan Tipikor terdiri dari hakim karier dan hakim non karier. Hal ini diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pengadilan Tipikor, yang menyatakan bahwa "Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim Ad hoc."
Baik hakim karier maupun non karier dipilih melalui proses seleksi dengan persyaratan yang berbeda. Namun, yang perlu diingat adalah seleksi hakim pengadilan Tipikor merupakan tahap yang sangat penting dalam pembentukan pengadilan ini. Para hakim ini tidak hanya menjadi tulang punggung pengadilan, tetapi juga bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia secara keseluruhan.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pembentukan pengadilan Tipikor di setiap ibukota kabupaten/kota akan mempengaruhi proses seleksi hakim yang dilakukan. Secara sederhana, jumlah pengadilan yang meningkat akan berdampak pada kualitas hakim yang dipilih.
Jika merujuk pada Pasal 3 UU No. 46 Tahun 2009 yang mengatur pembentukan pengadilan Tipikor di setiap ibukota kabupaten/kota di seluruh Indonesia, kita dapat menghitung kebutuhan jumlah hakim Tipikor. Dengan asumsi setiap kabupaten/kota membutuhkan 5 hakim Tipikor untuk satu majelis, maka dibutuhkan setidaknya 2.570 hakim Tipikor jika semua pengadilan tersebut didirikan.
Tentu sangat menantang untuk menemukan calon hakim yang memiliki kualitas dan integritas tinggi untuk mengisi posisi hakim Tipikor. Jika hal ini dipaksakan, maka Mahkamah Agung mungkin harus menurunkan standar kualitas bagi calon hakim. Kendala dalam proses seleksi hakim ad hoc di pengadilan Tipikor akan dijelaskan sebagai berikut:
Pertama, keengganan Akademisi untuk mendaftar. Salah satu tantangan utamanya adalah minimnya partisipasi akademisi dalam mendaftar sebagai hakim tipikor. Kebanyakan kandidat yang mengikuti seleksi adalah advokat atau pengacara, sementara akademisi sangat sedikit yang turut serta. Meskipun panitia seleksi sudah berusaha mendekati berbagai universitas di Indonesia, hasilnya masih belum memuaskan. Keengganan ini disebabkan oleh ketentuan yang mengharuskan mereka melepaskan jabatan struktural dan fungsional yang mereka pegang, seperti yang diatur dalam Pasal 16 UU Pengadilan Tipikor. Akibatnya, banyak akademisi lebih memilih tetap di kampus daripada menjadi hakim.
Kedua, Seleksi yang Diburu Waktu. Dengan batas waktu dua tahun untuk mengisi posisi di pengadilan tipikor di seluruh ibukota provinsi, MA harus bekerja cepat untuk memenuhi ketentuan undang-undang. Namun, ini menimbulkan tantangan dalam mengajak dan menyeleksi kandidat yang berkualitas untuk menjadi hakim ad hoc. Banyak akademisi dan praktisi berkualitas enggan mengikuti seleksi ini karena berbagai alasan. Hal ini memaksa MA menerima kandidat yang ada demi memenuhi target undang-undang.
Ketiga, Kekurangan Anggaran. Anggaran selalu menjadi kendala klasik dalam setiap proses seleksi, termasuk untuk jabatan hakim. Sistem penganggaran yang buruk sering kali menyebabkan masalah, seperti keterlambatan pembayaran gaji para hakim di pengadilan tipikor daerah. Kekurangan dana ini menghambat kelancaran proses seleksi.
Keempat, Proses Rekam Jejak yang Tidak Optimal. Dalam kondisi waktu yang terbatas dan anggaran yang minim, MA menghadapi risiko terpilihnya hakim yang bermasalah. Proses verifikasi rekam jejak tidak dilakukan secara maksimal, sehingga latar belakang kandidat tidak sepenuhnya diketahui. MA pernah bekerja sama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MAPPI-FHUI) pada seleksi pertama, namun tidak melanjutkan kerja sama tersebut di seleksi berikutnya. Masukan masyarakat yang diterima pun tidak optimal karena minimnya data penunjang. Akibatnya, hakim dengan rekam jejak buruk, seperti Ramlan Comel yang pernah menjadi tersangka kasus korupsi, bisa terpilih.
Kelima, Kurangnya Kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). MA sebenarnya bisa memanfaatkan PPATK untuk menelusuri transaksi keuangan para calon hakim tipikor. Kerjasama ini akan membantu mengetahui kekayaan dan transaksi keuangan calon hakim dengan lebih akurat. Namun, sampai saat ini MA belum melakukannya dan hanya mengandalkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang seringkali diisi dengan manipulasi dan tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya.
(Nazhif Ali Murtadho, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya)