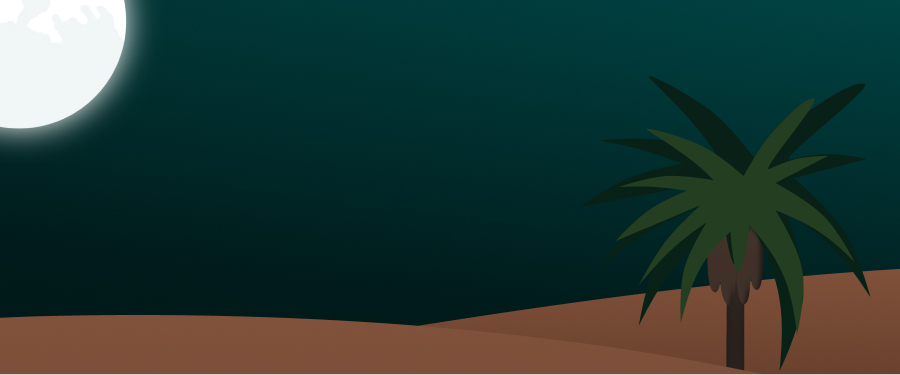Probelematika Penegakan Hukum Pidana Pajak Terhadap Wajib Pajak
- vstory
VIVA – Ketentuan Pidana Materil di Dalam Undang-Undang Perpajakan. Tulisan ini fokus pada ketentuan pidana pajak terhadap wajib pajak. Ketentuan pidana terhadap wajib pajak diatur di dalam Pasal 38 Klaster Perpajakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU CIPTAKER) dan Pasal 39, 39A Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007). Oleh karena itu, apabila wajib pajak disangkakan melakukan tindak pidana pajak, maka di antara tiga (3) Pasal inilah yang akan menjadi dasar kriminalisasi.
Adapun ancaman pidana di dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 39A adalah pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun, paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) sampai 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.
Apabila ketiga rumusan Pasal tersebut dilihat dari kacamata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), didapati bahwa Pasal 38 dirumuskan sebagai tindak pidana “pelanggaran” sedangkan Pasal 39 dan Pasal 39A dirumuskan sebagai tindak pidana “kejahatan.” Hal ni teridentifikasi dari ancaman pidana yang melekat pada masing-masing Pasal a quo, termasuk ancaman pidana terhadap percobaan melakukan tindak pidana (poging) serta penegasannya dalam Pasal 42 UU No. 6 Tahun 1983.
Apresiasi terhadap rezim UU No. 28 Tahun 2007 adalah menambahkan satu syarat terhadap penerapan Pasal 38 UU a quo. Syarat tersebut adalah bahwa “perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A.” Artinya, ancaman pidananya “diperlunak," sehingga perbuatan Si pelanggar baru dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila perbuatan demikian itu adalah perbuatan yang kesekian kali (pengulangan).
Kritikan penulis terhadap Pasal 38 UU a quo adalah tidak dirumuskan secara jelas, tegas dan pasti mengenai kriteria seseorang dapat dikriminalisasi berdasarkan Pasal 38 a quo. Tentu saja rumusan pasal yang demikian gelap dan kabur tersebut bertentang dengan kandungan asas legalitas yaitu lex stricta, lex certa. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam operasionalisasinya. Implikasi lebih lanjut, Pasal a quo berpotensi disulap menjadi lahan transaksional bagi operator hukum yang bersangkutan.
Alih-alih memperjelas dan mempertegas rumusan pasal a quo, rezim UU CIPTAKER justru meniadakan syarat tersebut sehingga kembali pada kondisi norma Pasal 38 UU 6 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Pasal 38 UU No. 9 Tahun 1994, diubah dengan Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2000 yang sebetulnya jelas dan terang kontradiksi dengan legal karakter UU a quo.
Berikutnya, dalam rangka mencapai ambisi penguasa, rezim UU No. 28 Tahun 2007 memproduksi Pasal 39A sebagai legitimasi mengkriminalisasi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Ironisnya, penambahan pasal tersebut tidak diikuti dengan merevisi Pasal 42 UU No. 6 Tahun 1983, sehingga menimbulkan persoalan baru yaitu apakah tindak pidana dalam Pasal 39A merupakan kejahatan atau pelanggaran.
Jika memotret melalui penafsiran sistematis (logis) dari Pasal 39 sampai 39A, Pasal 39A tergolong sebagai kejahatan. Namun berbeda jika berangkat secara a contrario dari Pasal 42 UU No. 6 Tahun 1983.
Sampai di sini, penulis menuduh rezim UU CIPTAKER bahwa hakikat negara hukum telah diplesetkan menjadi negara penghukuman, dan bahkan lebih ekstrem lagi sebagai negara penghakiman.
Akibat Hukum Jika Terpidana Pajak Tidak Melakukan Pembayaran Pidana Denda Secara Sukarela
Telah disampaikan bahwa bentuk pidana terhadap wajib pajak dapat berupa denda, penjara atau kumulasi keduanya. Berdasarkan Pasal 43C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) bahwa Pidana denda dalam Pasal 39 dan 39A UU No. 28 Tahun 2007 tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan. Dalam pada itu, narapidana pajak yang tidak melakukan pembayaran pidana denda dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka jaksa melakukan upaya paksa yaitu menyita harta kekayaan terpidana untuk dilelang dan hasil lelang tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda.
Setelah jaksa melakukan penelusuran dan penyitaan harta kekayaan terpidana, jika harta kekayaan tidak mencukupi untuk membayar pidana denda, si terpidana dipidana dengan pidana penjara.
Tentu saja hal ini sangat problematis secara asas maupun secara norma. Misalnya, berangkat melalui pertanyaan, bagaimana proses penelusuran harta kekayaan terpidana dan siapa yang menentukan nilai harta kekayaan terpidana?
Dalam hal ini, harta kekayaan terpidana berpotensi disita seluruhnya dan dilelang untuk membayar pidana denda. Sebetulnya perbuatan yang demikian bertentang dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yakni:
"Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah."
Pertanyaan lebih lanjut, bagaimana proses penjatuhan pidana penjara? Berdasarkan prinsip do process of law, harus melalui mekanisme pemeriksaan pengadilan yang outputnya adalah putusan hakim dengan amar putusan pemidanaan. Namun demikian, proses ini pun melanggar asas hukum umum “ne bis in idem” yang berarti tidak seorang pun dapat dituntut atau diadili dua (2) kali atas perbuatan yang sebelumnya telah diputus oleh hakim.
Selain itu, melanggar pula Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara tegas menyatakan bahwa:
“Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya.”
Ketentuan Acara Pidana di Dalam Undang-Undang Perpajakan
Penegakan ketentuan pidana pajak terlebih diawali dengan tindakan atau kegiatan “pemeriksaan bukti permulaan" (BUKPER) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan (1a) UU HPP dan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 239/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan (PMK Nomor 239/PMK.03/2014).
Menurut Pasal 1 angka (9) PMK Nomor 239/PMK.03/2014 bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan bukti permulaan adalah “pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan Bukti Permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.”
Lalu, menurut penjelasan resmi Pasal 43A UU HPP bahwa Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki tujuan dan kedudukan yang sama dengan penyelidikan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Oleh karena itu, pada tahap inilah dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menentukan suatu peristiwa sebagai peristiwa pidana atau bukan.
Jadi, dapat dipahami bahwa pemeriksaan bukti permulaan menjadi sangat sensitif dan krusial. Sensitif karena pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan dilakukan sepenuhnya oleh internal penyidik PPNS di lingkungan DJP. Krusial karena berdasarkan pemeriksaan bukti permulaan inilah akan menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa pidana atau bukan.
Setelah melakukan pemeriksaan bukti permulaan, apabila teridentifikasi sebagai peristiwa pidana, maka dilanjutkan pada tahap penyidikan yaitu: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka yang dikenakan penetapan tersebut sudah diduga kuat telah melakukan tindak pidana atau sebagai Pelaku tindak Pidana pajak. Oleh karena itu, pada titik ini pula merupakan titik yang sangat “abu-abu” dan karena itu berpotensi terjadi transaksional dalam operasionalisasinya.
Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dalam Menegakkan Ketentuan Pidana Pajak Dan Hak-Hak Tersangka
Penegasan kembali bahwa yang bertindak sebagai penyidik dalam konteks ini adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagaimana Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No. 27 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) berbunyi:
“Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.”
Kemudian, kewenangan tersebut dirinci di dalam Pasal 44 ayat (2). Menurut Pasal 44 ayat (3) bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan disampaikan kepada penuntut umum melalui kepolisian.
Sedangkan Pasal 42 ayat (3) mengatakan bahwa Penyidik DJP dapat melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berkaitan dengan di antaranya adalah upaya paksa yaitu misalnya membawa tersangka kepada penyidik PPNS untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.
Memperhatikan Pasal 42 a quo, diketahui bahwa peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan yang cukup besar kepada penyidik PPNS (DJP) dalam rangka penyidikan perkara tindak pidana pajak. Ironisnya, DJP pada umumnya berlatar belakang Pendidikan tinggi ekonomi, lalu berangkat dengan semangat dan paradigma pendapatan negara dikhawatirkan melanggar hak-hak-asasi warga negara.
Tentu saja isu demikian harus dipertanyakan, karena pada dasarnya penegakan hukum terutama ketentuan-ketentuan pidana bersentuhan langsung dengan hak asasi seorang yaitu hak ekonomi, sosial dan budaya (EKOSOB) maupun hak sipil dan politik (SIPOL) sebagai insan yang bermartabat sebagaimana dijamin di dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar 1945 yaitu di antaranya Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa:
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
Kemudian hak-hak tersangka dan terdakwa diatur lebih lanjut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu di antaranya:
Pasal 52 bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Pasal 54 bahwa guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
Pasal 55 bahwa untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Pasal 57 ayat (1) bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
Pasal 58 bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
Pasal 59 bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya. Pasal 50 ayat (1) bahwa tersangka berhak mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke penuntut umum.
Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) Pasal 18 ayat (4) secara tegas menyatakan bahwa "setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."
Sebagai kesimpulan, pertama, bahwa wajib pajak selaku tersangka dan/atau terdakwa tindak pidana pajak berhak mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Tentu hal ini menimbulkan larangan pula bagi aparat penegak hukum untuk tidak memproses pidana terperiksa, tersangka dan terdakwa tanpa pemenuhan hak-haknya tersebut.
Kedua, bahwa rumusan Pasal Pasal 38, UU CIPTAKER dan Pasal 39 serta Pasal 39A UU 28 Tahun 2007 tidak jelas, terang dan pasti isinya. Akibatnya, dalam konteks operasionalisasi berpotensi terjadi transaksional.
Ketiga, kewenangan penyidik PPNS (DJP) yang begitu besar dalam rangka penyidikan perkara pidana pajak berpotensi melanggar hak asasi wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak harus memahami hak-haknya sebagai warga negara yang telah dijamin dalam Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya agar dapat terhindar dari penegakan hukum pidana pajak yang tidak bertanggung jawab.