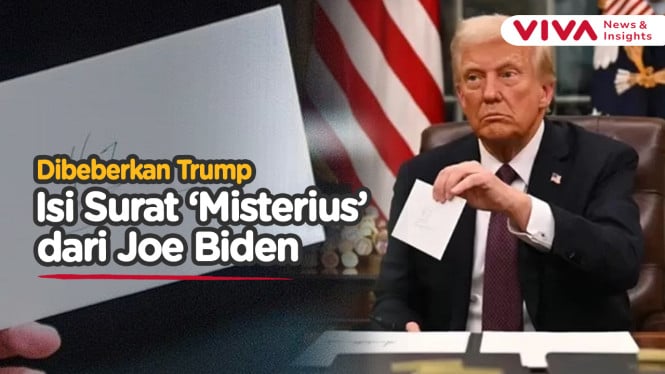Belajar Arti Kebinekaan dari Suku Tengger
VIVA – Pagi itu, sekitar pukul 09.00 WIB, terdengar suara musik gamelan yang mengalun merdu. Seakan benak dibawa ke arah bayangan zaman dahulu, saat masyarakat Indonesia memeluk ajaran agama Hindu. Suara itu makin lama semakin kencang. Bukan hanya suara gamelan saja, melainkan juga iringan terompet, saron, dan juga gendang menjadi satu, membelah dinginnya suhu lereng pegunungan Bromo pagi itu.
Perlahan, satu per satu warga mulai mendatangi pusat suara. Dengan memakai pakaian yang serba hitam, mereka langsung menduduki tempat yang telah disediakan oleh panitia yang menggelar ritual Nyadran di Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.
Mulai dari yang paling kecil, hingga yang sudah tua duduk bersebelahan sambil menunggu warga yang lain yang akan mengikuti upacara itu. Upacara ini masih dalam rangkaian upacara Hari Raya Karo yang digelar oleh warga suku Tengger yang beragama Hindu.
Setelah semuanya sudah berkumpul, acara penutupan Hari Raya Karo itupun digelar. Diawali dengan sambutan dari kepala desa dan camat, acara itu terlihat khusyuk dan khidmat. Tampak semua yang mengikuti ritual ini mendengarkan dengan serius apa yang disampaikan oleh kedua tokoh tersebut.
Selesai kedua tokoh itu memberikan sambutannya, tibalah waktunya ritual inti. Yakni pembacaan mantra sebagai pengantar roh para leluhur untuk kembali ke alamnya setelah selama kurun waktu satu minggu diundang dalam perayaan Hari Raya Karo atau yang juga dikenal dengan Pawedalan Jagat.
Aroma menyan dan dupa telah menyerbak memenuhi penjuru acara ritual di Balai Desa Sapikerep. Berbagai sesajen, mulai dari gedang ayu (pisang satu tandan), nasi, ayam, dan juga perangkat nginang yang sedari tadi dipersiapkan akan mulai dimantrai. Sang dukun memulai matra, dengan diiringi suara ting ting ting yang keluar dari alat yang dibawa oleh dukun dalam setiap ritual keagamaan Hindu.
Para umat Hindu nampak mulai lebih kekhusyukannya. Mereka tidak ada yang berbicara, hanya mendengarkan apa yang dibacakan oleh dukun di awal permulaan upacara ritual Nyadran itu. Setelah dipanjatkannya matra oleh dukun pandita desa setempat, barulah kemudian para warga yang sedari tadi khusyuk mulai berdiri dan mengikuti gelaran ritual dengan membawa sebuah gulungan yang berisi bunga untuk melakukan ritual Nyadran.
Nyadran sendiri adalah sebuah ritual untuk mengingat para leluhur yang telah meninggal mendahului mereka. Dengan ritual Nyadran ini, para warga suku Tengger Sapikerep melakukan ritual Pangeleng atau pengingat untuk leluhur. Bunga yang telah disiapkan dan juga toples berisi air bercampur dengan bunga tujuh rupa dibawa bersama ke makam. “Ini sudah tradisi turun-temurun. Saat saya masih kecil, ritual ini sudah ada,” terang Suwandi, Kepala Desa Sapikerep.
Nah, saat prosesi Nyadran inilah kerukunan umat beragama terlihat. Pasalnya, bukan hanya warga desa yang beragama Hindu saja yang mengikutinya. Melainkan warga yang beragama Islam pun juga mengikuti. Namun, bukan dalam ritual. Mereka mengikuti acara ini dengan keyakinannya masing masing, tanpa mengikuti ritual yang ada.
“Saya beragama Islam. Saya sebagai kepala desa juga mengikuti upacara ini, begitu pula yang lain. Tetapi tidak berbarengan. Untuk yang agamanya berbeda, kami suruh berangkat terlebih dahulu ke makam biar tidak berdesakan dengan yang menggelar ritual,” jelasnya.
Para umat Hindu yang menggelar ritual, beriringan berjalan bersama untuk terlebih dahulu menuju ke Punden. Setelah dari Punden kemudian mereka melanjutkan ke makam sanak famili mereka dengan membawa bunga dan juga sesajen. Dalam perjalanan menuju ke Punden dan juga makam, para umat Hindu ini diiringi dengan musik ktiplungan serta musik khas Bali yakni Bale Ganjur. Tujuannya, untuk menyenangkan roh para leluhur yang telah diundang dan akan diantar ke tempat bersemayamnya.
Makampun selesai dikunjungi. Namun, bukan membuat warga kemudian pulang ke rumah. Melainkan, masih ada ritual lain yakni prosesi membuat senang leluhur masih diteruskan dengan cara menanggap jaran kepang atau kuda lumping. “Sebelum diantar pulang, kami wajib untuk menyenangkan terlebih dahulu. Dan juga tanggapan ini sebagai hiburan bagi masyarakat,” ujarnya.
Ada yang unik dari perayaan Hari Raya Karo yang ada di desa ini. Meskipun kepala desa adalah seorang Muslim, namun untuk menjaga kerukunan umat beragama dan melestarikan budaya yang ada di desa, beliau selama sepuluh hari ikut tidak boleh tidur di rumahnya. Tujuannya untuk menjaga sesajen yang ada di Balai Desa yang digunakan untuk mengundang leluhur desa agar tidak terjadi apa-apa.
“Ini sudah tradisi. Siapapun kepala desa yang jadi, harus menjalankan tradisi ini. Bukan untuk mengikuti agamanya, tapi untuk menjaga kerukunan umat beragama dengan cara bertoleransi,” jelas Suwandi.
Ia berada selama sepuluh hari di Balai Desa bersama dengan anak dan istrinya. Ia ditugaskan untuk mengganti beberapa sesajen yang sifatnya tidak tahan lama, seperti wedang kopi yang dalam satu minggu harus diganti dengan yang baru. Sedangkan yang lainnya tidak perlu diganti.
Bukan itu saja, sebagai kepala desa yang mengayomi masyarakatnya, meskipun berbeda agama, Suwandi juga mendapatkan tugas untuk mengunjungi rumah warga yang merayakan Karo. Dari sekitar 800 kepala keluarga yang ada di desanya, Suwandi harus mengunjungi sedikitnya 500 kepala keluarga.
“Yang merayakan Karo sekitar 500 kepala keluarga. Itu harus saya kunjungi semua dalam waktu tiga hari. Jadi, satu harinya berkisar 165 kepala keluarga yang harus saya kunjungi,” tutup kepala desa yang menjabat sejak tahun 1999 itu. (Tulisan ini dikirim oleh Rosyidi)