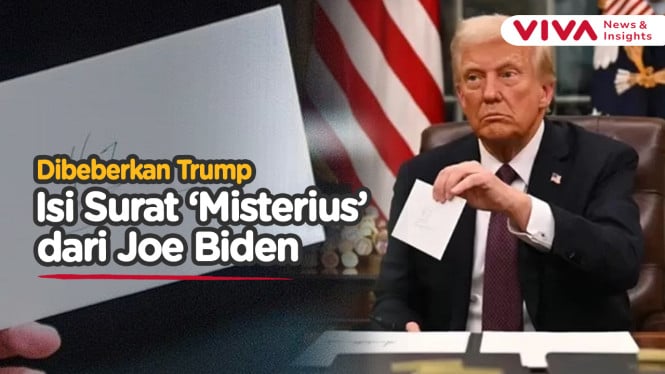Dari Anak Jalanan hingga Menjadi Pengusaha Kreatif
- U-Report
VIVA.co.id – Suara azan magrib bergemuruh. Gemericik air mengiringi pria itu mengambil wudu. Setelah salat di langgar, dia menyulut rokoknya sambil masuk ke galerinya. Beberapa kali dia mengatur ulang rambutnya yang mulai berantakan. Sambil senyum-senyum dia mulai bercerita tentang galeri kerajinan kulit miliknya.
Sekarang dia sudah mantap di rumah. Beberapa tahun yang lalu, Yogi pergi dari rumah. Dengan modal kepercayaan diri sebagai remaja laki-laki yang bebas, dia memutuskan hidup di jalanan. Dia menjelajah sampai Surabaya, Purwokerto, dan beberapa kota di Pulau Jawa. Yogi menjadi tukang cuci piring untuk menyambung hidup di jalanan.
“Dulu saya jarang pulang ke rumah, paling dua bulan sekali. Sisanya saya punk-punkan,” ungkap pria 28 tahun tersebut. Saat itu, Yogi merupakan penggebuk drum dari band Kapital Destroy dan Distorsi Liar. Selama tiga tahun, Yogi hidup di jalanan. Semua keputusan itu yang membuat kuliahnya di UGM keteteran.
Yogi memutuskan pulang ketika mendapat kabar bahwa ayahnya menderita stroke. Dia pulang sebagai anak yang hilang. Keputusannya untuk pulang mengiringi kepergian ayahnya menuju Sang Khalik. “Saya pulang karena bapak saya stroke. Mungkin beliau terlalu memikirkan nasib saya, anaknya,” ujar Yogi mengenang bapaknya.
Setelah kejadian itu, dia mulai berbenah dengan mengejar gelar sarjananya. Yogi sempat bekerja di Jakarta selama beberapa bulan, tapi ia memilih pulang ke rumah dan merintis usaha sendiri. Berbekal pengalaman mengikuti lokakarya sablonase, Yogi memulainya di rumah. Segala macam sablon, tie die, dan tas furing adalah rintisan pertamanya.
Namun, usaha pertamanya kandas karena tidak ada komitmen yang kuat di antara teman-temannya. “Lha ya biasa to anak muda itu suka tidak konsisten kalo mau usaha,” jelasnya. Lewat kegemarannya memelihara burung elang, Yogi mendapat ide untuk memulai bisnis baru. Aksesori kulit penutup paruh elang menjadi awal mula ide untuk membuat galeri kulit sendiri.
“Saya belajar dari teman tentang membuat aksesori kulit, tempat beli bahan, dan alat apa saja yang perlu digunakan,” ungkap Yogi yang berencana menikah tahun ini. Demi memulai bisnis ini Yogi merogoh koceknya sangat dalam. Hampir 60 juta rupiah dia gelontorkan untuk memulai galeri kulitnya.
“Uang itu hasil dari usaha yang lama, tabungan pribadi, dan sedikit dari kakak saya,” terang Yogi. “Banyak anak muda di sini kerjanya cuma mabuk-mabukan, tapi tidak ada penghasilan. Maka saya ajak mereka untuk belajar membuat kerajinan kulit ini,” cerita Yogi ketika pertama membuka galerinya. Yogi dengan sabar mengajari teman-temannya untuk membuat aksesori kulit layak jual. Bahkan, selama empat bulan pertama galeri kulitnya tidak menghasilkan uang sama sekali.
“Prinsip kerajinan saya adalah hand made. Jadi semua jahitannya dikerjakan tangan. Fungsi mesin hanya untuk membuat lubang saja,” jelas Yogi sambil menunjukkan jarum jahit dengan ukuran yang besar. Pemasaran yang dilakukan Yogi terbilang unik. Dia membagikan produknya kepada hampir semua anak muda di kampungnya. Kebanyakan berupa dompet dan gelang.
“Saya bagikan. Saya suruh mereka main yang jauh. Harapannya nanti ada yang tanya itu beli di mana,” ungkapnya sambil menirukan gaya calon pembelinya. Cara ini diakui belum efektif benar. Namun, cara ini diakuinya dapat menumbuhkan kegembiraan di tengah-tengah temannya. Sampai sekarang, galeri kulitnya hampir berjalan satu tahun.
Pesanan sudah mengalir deras. Biasanya, orang memesan strap jam tangan, gelang, dan dompet. Mereka mencari galeri saya karena harganya masih relatif murah. Beberapa pelanggan malah membeli grosiran untuk kemudian dijual lagi. “Urusan balik modal memang masih sangat jauh. Yang penting usaha ini jalan terus, karyawan ada penghasilan, dan galeri ini semakin maju,” harapan Yogi untuk galerinya.
Filosofi Kampung Jogonegaran terletak di balik hiruk pikuk jalan Malioboro yang tak kenal lelah. Jalan masuknya jarang terlihat karena lebih sering tertutup bus pariwisata yang parkir vertikal. Pada sore hari, remaja muda gemar duduk-duduk di muka gapura dan anak-anak bermain bola di jalan kampung yang sempit. “Ya, seperti itu kegiatan anak muda di sini. Nongkrong sambil melihat yang tua-tua jadi tukang parkir. Sebagai lahan basah parkir, di depan gang itu rawan gesekan. Anak-anak muda cuma melihat, tapi tidak ada kerjaan yang tetap,” kata Yogi menjelaskan keadaan kampungnya.
Dari keseharian tersebut, Yogi merasa perlu ada yang memikirkan kelanjutan kampungnya ini. Yogi menggambarkan bahwa setelah tamat SMA, anak muda di Jogonegaran mulai meninggalkan kampung dan jarang peduli pada keberlangsungannya. Oleh karena itu, dia memberi nama galerinya “House of Makaryo”. Sebuah nama dengan corak urban yang kental, seperti kampungnya.
Bahasa Inggris digunakan untuk menambah kesan keren dan bahasa Jawa dipilih sebagai sesuatu yang sangat intim dengan warga Yogyakarta. Makaryo sendiri dalam bahasa Indonesia berarti bekerja. Harapannya, pemuda dapat selalu bekerja dan bukan sekadar penonton dari perubahan zaman.
“Rencana saya setelah menikah, bersama istri saya, saya akan membuat local branding. Jadi nanti terserah anak muda di sini mau buat karya apa, biar saya yang memasarkan, tapi ya baru rencana,” kelakar Yogi sambil membakar rokoknya lagi. Usaha yang dilakukan Yogi adalah bentuk konkret dari pemberdayaan kaum muda.
Di dalam arus ekonomi yang meluas, kreativitas anak muda adalah energi yang besar. Upaya berdikari adalah jalan sunyi yang akan membuahkan hasil. Seperti kata Shakespeare, cara menjadi sukses hanya ada tiga. Pertama, tahu lebih banyak, bekerja lebih keras, dan berharap lebih sedikit dari orang lain, termasuk negara. (Tulisan ini dikirim oleh Agrangga)