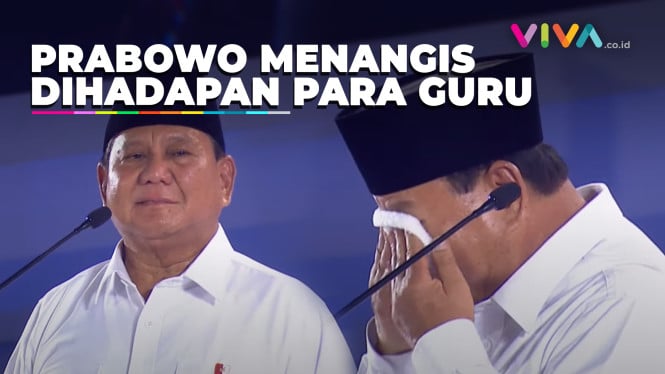Luka Bocah Kecil Sang Pengojek Payung
VIVA.co.id – Riuh angin kencang menggoyangkan dahan-dahan pohon. Riak hujan membanjiri tiap sisi jalan. Kala itu, jingga telah berpulang dan tergantikan awan hitam pekat. Hujan tak juga reda, padahal aku ingin segera pulang dan menikmati coklat panas di kamarku. Tapi apalah daya hujan ini tak kunjung juga berhenti.
Jam di tangan menunjukkan pukul 20.55. “Hujan seperti ini pasti lama berhentinya,” pikirku. Aku berjalan menuju pintu keluar dari pusat perbelanjaan kota Depok. Di lobi pintu keluar, aku berdecak kesal. Seharusnya hujan ini kalau mau turun nanti saja setelah aku sampai di rumah. Atau bisa saja tak usah ada hujan sekalian.
Beberapa menit berlalu aku memutuskan untuk beranjak dari sana dan berjalan dengan hujan yang masih lumayan deras. Setelah beberapa langkah meninggalkan pintu lobi, seorang anak kecil menghampiriku. “Payungnya, Ka.” Aku pun menoleh dan mengiyakan tawarannya.
Dia berjalan di belakang, mengikuti setiap langkahku. Tak sampai hati aku melihat dia bermandikan air hujan. Bajunya basah kuyup tak ada sehelai benang pun yang kering. Kedua tangannya ia lipat di dada, kepalanya menunduk. “Kamu sini dong!” kataku sambil menarik bahunya. “Rumahmu di mana?” Aku sengaja mengajaknya berbicara.
“Di Depok, Ka”. Jawabnya.
“Ayah ibumu tahu kamu di sini?” tanyaku lagi.
“Bapak sama ibu cerai. Bapak kawin lagi dan tidak pernah tahu aku di sini.” Jawabnya lagi.
Tuhan, rasanya aku ingin menangis saat itu juga. Perawakan anak itu kecil dan kurus. Sekolahnya baru kelas 3 SD. Bayangkan saja anak sepolos dan sekecil itu harus ikhlas dan tabah dengan apa yang ia harus jalani saat ini. Aku melirik kantong belanjaan yang aku beli saat tadi di pusat perbelanjaan tadi. Aku memang bukan terlahir dari keluarga kaya raya. Namun apa yang aku mau, aku bisa membelinya dengan uang jajanku.
Entah apa yang ia rasakan saat aku menanyakan tentang ayah ibunya. Tapi ia begitu polos dan jujur. “Terus kamu uangnya nanti buat apa?” Aku masih saja penasaran dengan hidupnya.
“Buat sekolah sama jajan Ka,” Lagi-lagi dia membuatku malu. Sekolah dan biaya hidupku tanpa malu meminta kepada orangtua. Jika kurang, aku merengek minta tambahan. Bahkan kadang berbohong untuk membeli sesuatu yang kurang manfaatnya.
Tapi lihatlah dia! Si bocah ojek payung itu. Dia rela berbasah-basahan menyingkirkan rasa takutnya terhadap bahaya kala hujan datang. Hanya dengan bermodalkan payung ukuran sedang, dia bisa mendapatkan rupiah untuknya bersekolah dan sekadar membeli jajanan rumahan.
Padahal tadi aku sempat berpikir tak usah ada hujan sekalian. Jika memang terjadi seperti itu, anak ini mungkin tak mendapatkan rizkinya. Terselip rasa kagumku padanya. Mungkin sebagian besar anak seumurannya sedang asyik bermain game online, bersenda gurau dengan keluarganya di rumah, menyantap makanan yang disediakan, atau bahkan sedang berselimut hangat di kamar yang cukup luas dengan berbagai macam mainan di sudut kamar. Sementara dia? Mungkin seribu dua ribu cukup membuatnya bahagia.
“Kamu nanti pulang naik apa?” tanyaku. “Naik apa saja Ka. Kadang naik angkot,” ucapnya. Aku ingin mengajaknya pulang bersama, tapi dia menolak dengan alasan masih ingin mengojek payung. Setelah sampai kukembalikan payungnya dan bertanya, “Berapa?” Dia pun menjawab, “Seikhlasnya saja, Ka.”
Untuk ke sekian kalinya dia kembali membuatku terdiam sesaat. Aku segera membuka tasku dan mengambil dompet. Beberapa lembar uang kertas aku keluarkan dan kuberikan padanya. “Terima kasih ya,” Dia hanya mengangguk dan kembali berjalan dengan wajah tertunduk.
Dari kejauhan aku perhatikan dia. Menerobos keramaian orang-orang yang lalu lalang sembari menawarkan payung yang ia sewakan. Jika bisa mengeluh, mungkin ia akan mengeluh, menangis, dan mengadu pada orangtuanya. Mengapa bapak dan ibu pisah? Mengapa aku harus hidup dengan ibu tiri yang tak menyayangiku? Ke mana bapak yang dulu? Ke mana ibu pergi meninggalkanku? Ke mana? Ke mana? Mengapa? Dan mengapa?
Hati dan jiwanya mungkin tak sebaik yang kita bayangkan. Tapi lihat, betapa banyak goresan luka dan kerinduan di sana. Andai dia boleh menangis dan berteriak kepada semesta kenapa ia harus terlahir berbeda dengan teman sebayanya, mungkin dia akan menangis tersedu-sedu.
Lihatlah, sekecil itu ia sudah mampu menyembunyikan semua luka dan kerinduan kepada keutuhan ibu bapaknya. Ia mampu menyimpan tangisnya di balik senyum kepada setiap penyewa payungnya. Ia mampu tersenyum mengalahkan matahari jika hujan datang. Tadi aku sempat bertanya apakah dia lebih suka hujan atau panas. Dengan wajah tertunduk dia menjawab, ‘’ Lebih suka hujan, Ka’’. (Tulisan ini dikirim oleh Eva Saiya dan Mentari Deti Lukita, mahasiswa Fikom, Universitas Pancasila, Jakarta)