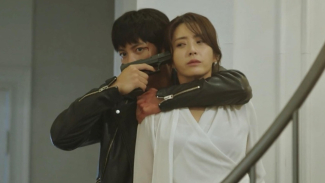Susahnya Terjebak Banjir
- U-Report
VIVA.co.id – Dulu, rumah saya adalah langganan banjir. Sebenarnya daerah di tempat saya itu bukan daerah banjir, tapi bentuk rumah saya yang dulu terlalu rendah. Jadi, setiap hujan besar sedikit saja pasti langsung banjir. Banjirnya memang tidak terlalu besar, hanya semata kaki. Tapi ternyata dengan banjir semata kaki itu sudah cukup membuat saya kewalahan.
Saya yang waktu itu masih berumur 5 tahun punya side job lain di samping mengerjakan PR dan nonton Si Unyil di TVRI. Side job saya adalah setiap terjadi banjir saya harus ngeluarin air yang menggenang di halaman rumah dengan menggunakan ember, gayung, ataupun baskom biar rumah saya enggak kemasukkan air.
Biasanya saya melakukan hal itu sambil menangis (ditambah ingusan) karena saya takut air hujan akan masuk ke kamar dan menghanyutkan koleksi Tamiya milik saya. Tiap air masuk ke halaman rumah, sambil mencidukkan air, saya pasti menangis sesengukkan sambil berdoa "Tuhan, tolong berhentikan hujan ini. Aku enggak mau hanyut ke kali, huhuhu". Tapi semua berubah sejak rumah saya yang lama dihancurkan dan dibangun baru.
Karena sekarang rumah saya tinggi, air pun tidak pernah bisa masuk ke halaman rumah lagi. Saya yang dulu setiap hujan selalu menciduk air sambil mewek, sekarang hanya ngelihatin tetangga saya yang kewalahan menciduk air dari balik jendela. Bahkan selama saya tinggal 3 bulan di Jakarta yang katanya selalu banjir itu, saya tidak pernah ketemu banjir. Semuanya lancar-lancar saja, saya tetap bisa membaca komik Gober sambil berselimut tebal tanpa harus takut kena banjir.
Tapi memang yang namanya musibah bisa datang kapan saja. Tanpa ada kode apa-apa, tanpa ada pertanda apa pun tiba-tiba saya terjebak banjir di Jakarta. Sebenarnya ini cukup memalukan sih, atau lebih tepatnya saya lagi sial.
Belum lama ini, saya dan teman-teman kebetulan ada acara workshop atau seminar di Sunter. Di hari itu berita banjir sedang heboh-hebohnya dan dengan polosnya saya tetap ikut teman ke hotel yang ada di daerah Sunter. Bodohnya, saya tidak pernah tahu kalau Sunter, Boulevard, dan sekitarnya adalah daerah langganan banjir. Setiap banjir, pasti saja jalanan di situ menggenang dan tidak bisa dilewati.
Pagi-pagi saya berangkat bersama teman saya. Semuanya baik-baik saja, dan saya pun masih bisa ketawa-ketiwi di jalan. Masalah mulai muncul ketika sudah hampir mencapai tujuan, kurang lebih 2 km lagi. Saya bertanya-tanya, kenapa banyak mobil berhenti di jalanan. Padahal hotel tempat seminar itu letaknya tidak terlalu jauh. Tinggal belok kiri, jalan sedikit, sampai deh.
Setelah tanya-tanya ke polisi dan tukang jual kerupuk, akhirnya saya dapati sebuah kenyataan kalau jalan utama penghubung Boulevard dan Sunter itu terendam banjir. Kalau mobil Pajero atau Jeep sih mungkin enggak masalah dan bisa menerobos, tapi sayangnya saya naik mobil Jazz yang pendek, jadi tidak ada keberanian dari sopir untuk menerobos.
Pilihan yang paling bijak adalah menunggu sebentar sampai jalan yang terendam bisa cepat surut. 2 sampai 3 jam menunggu, tapi kok airnya enggak surut-surut. Lebih fatalnya, sebenarnya saya sudah punya janji sama teman saya yang lain di Grand Indonesia. Oke, akhirnya saya ambil keputusan untuk memisahkan diri dan mencari transportasi umum buat ke arah kota. Brilliant kan ide saya? Walaupun terkesan licik karena meninggalkan teman-teman saya dalam posisi kebanjiran. Ide brilliant walau mungkin saya kayaknya disumpah serapahi oleh teman yang saya tinggal di mobil.
Setelah berjalan selama 10-15 menit, saya sampai di Mall of Indonesia. Ini kali pertama saya melihat mall ini, biasanya sih cuma lihat di tv doang. Saya tidak ada urusan di Mall of Indonesia, karena yang jadi urusan utama buat saya adalah mencari halte dan cus ke arah Jakarta Pusat. Halte sih memang ada, tapi kok busnya enggak ada ya?
Dari kejauhan saya melihat ada tempelan di kaca yang bertuliskan "Hari ini bus tidak beroperasi karena banjir" Aduh! Kalau ini busway tidak beroperasi, terus saya naik apa dong buat pulang? Saya anak cupu soal pengetahuan jalan dan sekarang tersesat di daerah yang sama sekali tidak saya kenal. Saya cuma dapat rekomendasi dari tukang parkir yang menyuruh saya naik bus warna hijau dengan nomor 146. Tapi yang luar biasanya, sudah saya tungguin 2 jam tapi bus ini enggak lewat-lewat juga.
Saya mencoba untuk tetap tenang, karena di saat genting seperti ini yang dibutuhkan adalah ketenangan. Raut muka memang menujukkan ketenangan walau mungkin hati saya sudah meraung-raung karena panik. Sepertinya kalau saya naik angkutan umum sudah pasti tidak ada harapan, karena tidak ada angkutan umum yang beroperasi.
Saya ingat kalau saya punya teman yang rumahnya di Kelapa Gading. Sebenarnya saya agak enggak enak juga minta tolong ke dia. Pertama, karena dia sudah berkeluarga dan kedua saya mau minta tolong dia untuk anter saya ke halte busway terdekat. Dibanding saya enggak bisa pulang, minta tolong adalah solusi paling bijak buat saya.
Akhirnya saya telepon dia dan dengan dengan senang hati dia mau mengantar. Tetapi masalahnya ada satu, yaitu saya harus ke Mall La Piazza karena rumah dia di daerah situ. Sedangkan akses menuju La Piazza itu cuma ada 1 jalur dan jalur itu terendam banjir selutut. Jarak dari tempat saya berdiri ke La Piazza ada sekitar 3 km.
Kata teman saya, saya disuruh menyewa delman buat menyeberang, tapi itu bukan pilihan bijak menurut saya karena sungguh sangat tidak berpri-kudaan. Kuda cuma satu harus dinaikkin rombongan. Apalagi pas banjir, pasti langkah kaki si kuda menjadi semakin berat. Pilihan naik delman pun saya coret. Solusi yang paling mungkin adalah saya naik mobil bak terbuka punya polisi buat melewati jalanan yang banjir ini.
Entah kenapa saya kok merasa jadi napi kalau harus naik mobil polisi. Tapi, daripada saya enggak bisa pulang, naik mobil polisi adalah opsi paling bagus buat saya. Sambil malu-malu, saya pun naik mobil polisi. Tapi bodohnya, ternyata cuma saya seorang yang berdiri di belakang mobil terbuka milik polisi ini. Entah orang-orang enggak mau dekat sama saya atau mereka tidak ada yang butuh menyeberang tapi yang pasti cuma saya seorang yang naik mobil polisi.
Setelah saya naik, beberapa polisi juga ikutan naik karena mau menyeberang. Dibanding orang yang mau nyeberang, saya lebih tampak sebagai pelaku kriminal yang ditangkap aparat berwajib. Yang menjadi masalah adalah, di sini banyak stasiun TV sedang meliput soal banjir. Sebagian besar adalah TV nasional. Parahnya, pas saya naik mobil polisi dan diapit oleh banyak polisi, kamera-kamera TV nasional itu menyorot saya.
Ada reporter yang ngomong (suaranya terdengar jelas), "Bisa dilihat genangan air yang begitu tinggi di Boulevard. Nampak seorang warga harus mengungsi sambil menaiki mobil kepolisian, bla...bla...." sambil menunjuk ke arah saya dan diikuti dengan kamera-kamera lain yang juga menyorot saya. Sumpah, saya jadi semakin mirip pelaku kriminal dibanding korban banjir!
Pertama, saya enggak bawa tas besar kayak warga mengungsi. Kedua, gaya saya saat itu dengan bercelana jeans dan sneakers sungguh tidak mencerminkan korban banjir yang biasanya pakai celana pendek, kaos kutang, dan sandal. Dan yang bodohnya lagi, saat si mbak reporter sedang melihat ke arah saya, kamera juga menyorot ke arah saya, tiba-tiba sang kameramen memberi kode ke saya untuk melambaikan tangan dan saya nurut saja dengan dadah-dadah kayak anak alay.
Tidak lama setelah itu, mobil pun berjalan. Saya baru berpikir, "Bagaimana kalau mama saya di Bandung nonton dan melihat saya diangkut mobil polisi kayak begini?" Mama saya pasti langsung mikir, “Anak gue jauh-jauh ke Jakarta disuruh cari duit malah diangkut mobil polisi."
Setelah berjuang melewati banjir, akhirnya saya ketemu juga sama teman saya yang sudah menunggu di La Piazza. Kondisi saya sangat mengenaskan. Badan basah kuyup, sepatu basah, daleman basah, ponsel pun basah. Di apartemennya, saya mandi dan mengganti baju. Dari lantai 15 ini, saya melihat keadaan jalanan yang benar-benar parah gara-gara terendam banjir.
Saya melamun sebentar sambil berpikir, “Bagaimana coba kalau saya enggak dijemput oleh teman saya, sudah jadi gembel kali di jalanan. Saya langsung menelepon kakak saya dan menceritakan kesialan saya hari itu. Kakak saya cuma bisa tertawa ngakak mendengar cerita saya dan sejak hari itu, saya baru tahu rasanya kebanjiran itu seperti apa. (Cerita ini dikirim oleh Stefanus Sani, Bandung)