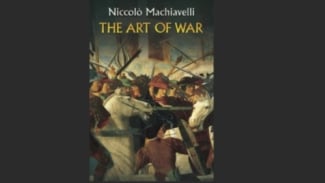Dilema Kolektivisme Nahdlatul Ulama
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id – Akhir bulan lalu, 31 Januari 2016, Nahdlatul Ulama (NU) memperingati hari jadinya yang ke-90 tahun. Ibarat usia seorang manusia, NU tak lagi muda. Dalam perjalanannya, NU telah mencatatkan diri sebagai organisasi yang aktif dalam pembangunan republik. Prestasi dan nama besar NU sebagai organisasi, disertai pula oleh perjuangan para tokoh besarnya, K.H Hasyim Asy’ari, K.H Ahmad Shiddiq, K.H Abdurrahman Wahid (Gusdur), dan K.H Mustofa Bisri (Gus Mus) merupakan sedikit dari sederet nama besar tokoh NU.
Mempelajari, meneladani, dan meneruskan perjuangan NU sudah selayaknya menjadi tugas kita bersama. Sebagai masyarakat yang beradab, mari kita tunaikan kewajiban tersebut melalui berpikir dan bersikap kritis terhadap organisasi NU itu sendiri.
NU merupakan organisasi kemasyarakatan Islam yang berpijak pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sebuah ajaran yang menghendaki adanya Sami’na wa Atho’na (kami dengar, maka kami taat). Singkatnya, NU kental akan nilai-nilai kepatuhan. Kepatuhan ini terjalin antara hubungan santri/penganut NU (masyarakat NU) dengan kiai.
Menurut hemat penulis, hubungan kepatuhan antara kiai dan masyarakat NU mengandung nilai ganda yang kontraproduktif. Dalam politik misalnya, masyarakat NU sami’na wa atho’na pada keputusan kiai. Entah, terlepas baik atau buruknya keputusan tersebut. Apapun yang menjadi keputusan kiai, keputusan itulah yang juga menjadi keputusan masyarakat NU. Sami’na wa atho’na: masyarakat dengar, maka masyarakat taat.
Hubungan masyarakat NU dengan kiai membentuk patronase yang teramat kuat. Pada ranah praksis, hampir di setiap momentum politik-pemilu, sowan para politisi kepada kiai acapkali diselenggarakan. Tak lain, tujuannya adalah untuk memperoleh “restu suara” kemenangan.
Dari paparan di atas, kita perlu meletakkan nilai kepatuhan sebagai nilai yang membawa konsekuensi logis tersendiri bagi masyarakat NU. Di satu sisi konstruktif sebagai pengejawantahan dari sikap/perilaku hormat, tetapi di sisi lain destruktif karena menjerat kebebasan individu (baca: kebebasan masyarakat NU). Signifikansi pengaruh hubungan patron-klien ini menyeret NU pada sebuah dilema kolektivistik; kepatuhan yang membelenggu kebebasan individu.
Dilema Kolektivisme
Jika ditelusuri lebih jauh, sami’na wa atho’na dianut sebagai nilai moral karena tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kiai. Kiai dipercaya sebagai orang ’suci’ yang mempunyai kecakapan religius dalam pengambilan keputusan atas dasar nilai-nilai agama. Setiap fatwa dan setiap keputusan kiai adalah kebenaran bagi masyarakat NU. Dalam kehidupan demokrasi bukan lagi Vox Populi Vox Dei atau suara rakyat adalah suara Tuhan. Melainkan Vox Sacerdotum Vox Dei, suara kiai suara Tuhan.
Mengenai agama dan politik, menurut Max Weber dalam buku “Masyarakat dan Negara” karya Ignas Kleden (2004), setiap kekuasaan politik berpotensi untuk memperluas wilayah kekuasaan dalam lingkungan agama (Caesaropapisme). Setiap kekuasaan agama tergoda untuk memperluas kekuasaannya dalam bidang politik (Hierokrasi). Perihal ini dapat kita saksikan pada kepercayaan masyarakat NU terhadap kiai yang berujung pada kekecewaan. Dalam kancah politik praktis, tidak sedikit kiai NU yang terjerumus dalam skandal korupsi.
Di Jawa Timur, sebagai daerah basis massa NU, kita disuguhkan oleh kasus korupsi yang menimpa kiai Fuad Amin yang notabene kiai NU. Belum lagi kemapanan dinasti politik yang juga berhasil dibangun. Fenomena berbagai kasus kiai NU tersebut telah mengingatkan kita bahwa kolektivisme (NU) ujungnya akan membawa petaka bagi kemanusiaan. Seperti petuah Lord Acton, “Semua kekuasaan itu korup, apalagi kekuasaan absolut” (Hayek, The Road to Serfdom: 2001)
Quo Vadis NU?
Sepak terjang NU sebagai organisasi besar kemasyarakatan Islam menuai beberapa catatan. Mulai dari relasi patronase kiai dan santri yang melahirkan kepatuhan semu, sampai pada skandal para kiai yang terlilit korupsi dan dinasti politik.
Quo Vadis NU? Di satu sisi kita disuguhkan pada torehan prestasi-prestasi NU beserta keteladanan para tokoh besarnya. Disisi lain kita pun perlu membangun kritisisme terhadap NU. Pemikiran-pemikiran kritis tentang NU telah muncul dalam berbagai manifestasinya. Terselenggaranya forum-forum dan dialog publik yang membahas tentang NU menjadi bukti betapa masyarakat begitu antusias untuk berjalan bersama NU dalam melanjutkan mimpi kemerdekaan.
Bahkan, diterbitkannya buku-buku dan karya-karya akademik, salah satu naskah terbaiknya adalah “Rowing in a typhoon: Nahdlatul Ulama and the decline of parliamentary Democracy” karya Greg Fealey pada tahun 1992, peneliti politik Islam Australia National University yang juga memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di Indonesia.
Seluruh perayaan perdebatan mengenai NU seperti paparan tulis di atas adalah pertanda bahwa NU merupakan organisasi besar yang amat dicintai masyarakat. Maka, tidak berlebihan rasanya jika kita menaruh kebanggan pada organisasi yang mewakili warga nahdiyin ini, sembari mengkritisinya. Selamat harlah ke-90 NU! (Tulisan ini dikirim oleh Sukma Hari Purwoko, mahasiswa Universitas Jember, Jawa Timur)