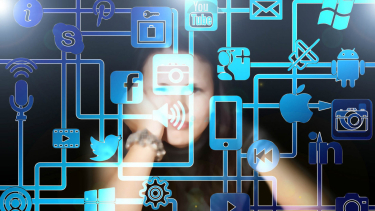Fatwa Haram Merambah Media Sosial
- www.pixabay.com/geralt
VIVA.co.id – Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa Muamalah di Media Sosial. Keputusan ini sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara pemerintah dan MUI pada Januari 2017 guna memberi pagar aturan kepada umat Islam dalam menggunakan jejaring sosial di internet.
Dalam fatwa yang diberi Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial ini, terdapat sejumlah hal yang diputuskan sebagai perbuatan haram bagi umat muslim.
Yakni, gibah atau membicarakan keburukan atau aib orang lain, fitnah, namimah atau mengadu domba, dan menyebarkan permusuhan.
Kemudian, praktik bullying atau merisak, ujaran kebencian serta informasi palsu atau hoax dan hal yang berkaitan dengan konten pornografi. Serta terakhir berkaitan dengan penyebaran konten yang tidak sesuai tempat dan atau waktunya.
"Ini sangat penting, karena berangkat dari keprihatinan MUI daripada maraknya konten media (sosial) yang tidak hanya positif tapi juga negatif," kata Ketua MUI Ma'ruf Amin, Selasa, 6 Juni 2017.
Hoax dan Persekusi
Sejak beberapa waktu ini di Indonesia memang tengah menggejala penyakit informasi palsu. Sebarannya menyentuh hampir seluruh lini dan beberapa telah menimbulkan korban.
Internet dan media sosial telah menjadi medium penyebaran informasi palsu atau hoax yang tak terbendung. Sekali saja sebuah kabar menjadi viral maka ia tidak akan terhenti. Internet pun menjadi bak bilah mata pisau, ia bisa melukai bisa juga bermanfaat.
Di Indonesia, ledakan hoax telah muncul sejak beberapa tahun terakhir. Ia mengacak segala informasi dengan medium utamanya adalah media sosial.
Merujuk laporan Reuters Institute dalam Digital News Report 2016 yang digelar di 30 negara, tak termasuk Indonesia. Menemukan bahwa memang ada kecenderungan publik mengasup informasi lewat media sosial.
Dalam riset itu juga menemukan bahwa antara perusahaan media dan media sosial secara prinsip tidak saling meniadakan. Kepercayaan publik terhadap media dan media sosial berjalan di alurnya masing-masing.
Namun demikian, memang ada beberapa negara yang kecenderungan publiknya memang lebih mempercayai media sosial sebagai sumber informasi mereka. Itu terjadi di Malaysia dan Singapura. Reuters Institute mencatat ada angka lebih dari 25 persen kepercayaan, lebih tinggi dari Amerika Serikat yang hanya 15 persen.
Di Indonesia, dari data yang dimiliki Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016, jumlah pengakses internet Indonesia sudah mencapai 132,7 juta dari total penduduk mencapai 256,2 juta orang. Jumlah itu jauh meningkat drastis dibanding tahun 2014 yang hanya 88,1 juta orang.
Dan kemudian, mayoritas penggunaan internet tercatat 97,4 persen adalah media sosial. Sebanyak 54 persen atau sekira 71,6 juta mengakses melalui facebook, instagram 15 persen atau 19,9 juta, youtube 11 persen atau 14,5 juta, google+ 6 persen atau sekira 7,9 juta, twitter 5,5 persen atau 7,2 juta dan linkedin sebanyak 0,6 persen atau 796 ribu. (Baca: Hoax, Tsunami Baru di Era Post-Truth)
Data ini menunjukkan bahwa memang ada 54 persen orang Indonesia yang menggunakan media sosial. Bentuknya bisa untuk berinteraksi dan mencari informasi. Di luar itu, muncul anggapan bahwa tingginya penggunaan media sosial ini lah yang diduga menjadi pemicu reaktifnya orang Indonesia terhadap sejumlah isu yang viral di media sosial.
Terlepas itu isu positif atau bukan, yang jelas opini publik pun dengan mudahnya mengkristal lewat media sosial. Untuk yang positif misalnya seperti penggalangan donasi bantuan kepada yang terkena musibah.
Sementara untuk yang negatif bisa dilihat dari maraknya hujatan hingga munculnya aksi persekusi, yakni pemburuan sewenang-wenang terhadap seseorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Meskipun aksi ini sebagai respons atas lambannya kepolisian dalam mengusut penghinaan dan hujatan kepada ulama di media sosial namun hal ini tidaklah dibenarkan secara undang-undang.
Hal inilah yang kemudian dikhawatirkan. Media sosial akhirnya menjadi senjata untuk perseteruan dan kericuhan. Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet) bahkan sudah mencatat sepanjang Januari-Mei 2017, telah ada 60 kasus persekusi terjadi.
"Meningkat secara drastis setiap bulan," kata Koordinator Regional Safenet Damar Julianto, Minggu, 4 Juni 2017.
Efektif atau Tidak
Sejauh ini, dengan terbitnya Fatwa MUI tentang ketentuan atau Muamalah di Media Sosial. Menjadi penambah tebal lapisan peraturan bagi publik saat menggunakan internet dalam medium apa pun.
Apa saja ketentuan itu? Sebut saja Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE No. 11/2008, dan kemudian ada juga Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 soal penanganan situs internet bermuatan negatif. (Baca: Jokowi Bentuk Satgas Anti Provokasi)
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengaku menyambut baik hasil Fatwa MUI soal perilaku media sosial tersebut. Ia meyakini dengan terbitnya fatwa tersebut akan makin memperkokoh kekuatan pemerintah melindungi publik dari paparan konten negatif dan informasi palsu.
"Di dalam UU ITE tugas pemerintah ada dua. Melakukan edukasi dan membatasi akses ke dunia maya. Sesuai dengan rekomendasi MUI, kami akan menjalankan dua tugas ini," kata Rudiantara.
Kedepan, dengan bermodal UU ITE serta fatwa dan persetujuan DPR, Rudiantara mengaku pihaknya kini memiliki kekuatan lebih untuk menutup akun atau konten negatif yang memicu perseteruan.
Dukungan serupa juga dilontarkan dari Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Ia pun berharap lewat fatwa itu juga bisa membendung segala hal yang bermuatan negatif.
"Pihak tertentu mengacaukan masyarakat, kita hentikan. Misalnya saja sekarang teroris sudah menggunakan teknologi cyber, apa kita biarkan? Perakit bom dengan cara-cara teknologi baru, teknologi informasi yang ada, apa kita biarkan?" kata Wiranto.
FOTO: Anggota FPI tersangka persekusi terhadap seorang anak berumur 15 tahun karena unggahan di Facebook
Di luar itu, saat ini di era digital, media sosial sejatinya hanyalah sebagai medium. Diakui ia memang menjadi penghantar tercepat informasi palsu ataupun kebencian.
Namun demikian, hal yang harus diperkuat juga adalah kebiasaan publik untuk mengecek setiap informasi. Sebab faktanya kemudahan yang disediakan internet membuat kita malas.
Dan fakta bahwa mesin pencari di internet telah mengkotakkan informasi sesuai dengan yang digemari sudah menjadi hal yang tak terbantahkan.
Atas itu, sadar atau tidak, publik yang terlanjur berkutat di seputar informasi hoax maka mereka akan tetap berada dalam gelembung hoax selama ia bergelut di mesin pencari.
Google, Facebook, Twitter dan lain sebagainya kini telah merekam segala aktivitas kita. Apa yang digemari seseorang kini akan dikelompokkan dengan mudah di jejaring sosial. Singkatnya publik tetap tak punya pilihan.
Algoritma mesin pencari menjadikan mereka tetap terkotak sesuai dengan minat, kesukaan dan hal yang mereka inginkan atau percayai. Atas itu, bisa jadi mau setumpuk peraturan selama internet telah merekam perilaku digital kita maka akan sulit keluar dari lingkungan itu.
Karena itu ada baiknya memang seharusnya kita harus lebih banyak bertatap muka dengan orang, bercengkarama, dan tak melulu disibukkan dengan internet di telepon seluler atau laptop.
"Hidup jauh lebih indah di luar gadget, handphone, atau komputer. Tapi, kadang kita lebih suka terjebak pada jaring-jaring yang kita tenun sendiri," kata pengamat sosial politik dan media Made Supriatma seperti dikutip dari Remotivi. (adi)