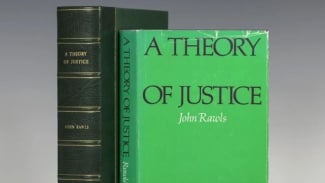- VIVA.co.id/Nurcholis Anhari Lubis
VIVA.co.id – Suasana di dalam gedung Pewayangan Kautaman Taman Mini Indonesia Indah mendadak senyap. Hari beranjak siang. Saat itu, Senin 24 April 2017.
Keriuhan pendukung pementasan kelompok wayang orang Sriwedari sebelum gladi resik dimulai perlahan hilang. Berganti dengan keheningan.
Lamat-lamat suara gamelan terdengar. Para pemain, pengrawit atau penabuh gamelan, dan kru wayang orang Sriwedari mulai menyatu. Memadu gerak gladi resik jelang pementasan.
Cerita tentang Arjuna dengan lakon “Mintaraga” perlahan mengalir. Pemain pun melakoni peran dengan khidmat.

Pada pagelaran wayang orang, para pemain akan selalu menari seiring dengan jalan cerita. (VIVA.co.id/Nurcholis Anhari Lubis)
Pemain dan penari meliukkan tubuhnya secara pelan namun indah, membawa imajinasi penonton pada kisah Ramayana dan Mahabharata. Adegan demi adegan dilakukan sepenuh hati, serasa terlempar jauh ke masa lalu dan berjarak dengan hiruk pikuk dunia kekinian. Meski baru gladi resik, semua pemain memberikan totalitas pada setiap peran yang mereka jalani.
Mintaraga atau Ciptoning, mengisahkan Arjuna yang sedang bertapa mencari jati diri. Dalam pertapaannya itu, ia mendapatkan berbagai ujian atau cobaan dari para dewa melalui aneka macam perwujudan. Tujuannya untuk menguji seberapa teguh niat Arjuna untuk mencapai tujuannya. Arjuna berhasil melalui semua godaan, sehingga ia dipilih oleh dewa-dewa untuk menjadi “Jagonya Dewa”.
Arjuna diberi tugas melawan raksasa yang bernama Niwoto Kawojo. Saat itu, Niwoto Kawojo telah mengobrak-abrik Kahyangan karena ingin mempersunting bidadari bernama Subpraba. Padahal, bukan ranahnya raksasa memperistri seorang bidadari.
Lakon Mintaraga memiliki pesan bahwa seseorang yang sudah mencapai tingkatan tertinggi, seperti raksasa Niwoto Kawojo dan Begawan Ciptoning, yang sama-sama memiliki kesaktian luar biasa, sesungguhnya masih bisa dipertanyakan.
Apakah mereka yang sudah mencapai tingkatan seperti itu sudah menjalani perannya sesuai dengan kodratnya? Sesuai dengan titahnya dengan sesama manusia, titahnya dengan alam semesta, juga titahnya dengan Tuhan?
Umumnya, cerita wayang memang selalu penuh dengan filosofi. Pesan-pesan moral yang pas untuk menjalani kehidupan kerap muncul melalui dialog, adegan, juga dari tema utuh.
Meski kisah yang diangkat berasal dari cerita yang sudah turun temurun selama berabad-abad, namun filosofi dalam wayang tak pernah basi, dan tetap menarik disimak.
Karena mementaskan wayang adalah mementaskan kehidupan seorang manusia. Kisah yang disampaikan adalah kisah yang sama, hanya berganti tahun, berganti masa dan berganti kondisi sosialnya.
Kelompok wayang orang Sriwedari misalnya. Melakukan pementasan dengan dua alasan, menyambut Kongres IX Serikat Nasional Pewayangan Indonesia atau Senawangi dan menyambut perayaan wayang orang itu yang tahun ini mencapai 107 tahun. Sebuah usia yang luar biasa untuk perjuangan mempertahankan kesenian dan tradisi budaya. (Baca juga: Seabad Wayang Orang Sriwedari Berjuang)
Lebih dari satu abad wayang orang Sriwedari melakoni perjalanan budayanya. Di tengah gempuran masa yang menuntut serba mudah dan cepat, wayang orang Sriwedari tetap setia menjalankan pentas dengan persiapan matang yang melibatkan puluhan orang, ratusan alat musik, seni berpakaian dan berdandan yang mungkin saat ini dilihat lamban serta ribet. (Baca juga: Pernik-pernik Wayang Orang)
Salah satu kelompok yang ikut berperan aktif menjaga kesenian wayang orang adalah Triardhika Production, yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surakarta membawa wayang orang Sriwedari berpentas di Jakarta.
Produser Triardhika, Enny Sulistyowati, berkisah, Sriwedari adalah kelompok wayang orang yang awalnya dibentuk di dalam keraton yang akhirnya dibawa keluar. Setelah dipentaskan di luar keraton, wayang orang menjadi semakin dikenal.
Apalagi menjelang kemerdekaan, wayang orang disiarkan di sebuah siaran radio. Maka makin luaslah penggemarnya. Semakin banyak penggemar wayang orang, membuat seorang pengusaha asal Tionghoa tertarik menjadikannya sebagai hiburan yang memiliki nilai jual.
“Jadi pada zaman dulu itu kemudian dikemas oleh pengusaha Tionghoa supaya bisa dijadikan hiburan yang memiliki nilai jual. Dijadikanlah wayang orang sebagai tontonan panggung, dan tontonan panggung itulah yang ada sampai sekarang,” ujar Enny.
Enny mengaku sangat mengagumi Sriwedari, yang kini sudah mencapai empat generasi. Kelompok ini pernah mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1970-an. Di masa itu, ada tiga nama yang begitu populer dan kini mulai melegenda. Ketiganya adalah Surono, Rusman, dan Darsih.
Ketiga orang ini disebut sebagai aktor luar biasa yang membuat popularitas Sriwedari mencapai puncak emasnya. Bahkan Presiden Soekarno kerap meminta kelompok ini tampil di hadapan tamu negara.
Selanjutnya, Wayang Orang vs Budaya Pop
Wayang Orang vs Budaya Pop
Perjalanan Sriwedari tak selamanya mulus. Masa keemasan pada 1970-an mulai memudar. Penonton wayang orang Sriwedari mulai berkurang dan terus berkurang. Masuk tahun 1990-an, perjalanan kelompok ini semakin redup dan nyaris bangkrut.
Budaya pop terus menggerus budaya tradisional hingga kelompok ini makin tersisih. Nasib Sriwedari mulai mengenaskan. Pentas mereka semakin sepi pengunjung.
Tiket penjualan yang berharga sangat murah tak cukup membuat publik mendatangi gedung pertunjukan. Nasib pemain semakin susah. Namun mereka bertahan.
Teknologi yang semakin memudahkan ditengarai menjadi penyebab sepinya penonton. Untuk mencari hiburan, tak perlu lagi susah-susah membuang waktu mendatangi tempat pertunjukan.
Ketika televisi mulai menjadi hiburan alternatif, maka manusia tak perlu lagi bersusah payah hanya untuk mencari hiburan. Perubahan budaya akhirnya berpengaruh pada kebutuhan dan selera.
Eddy Karsito, dari bagian humas Senawangi memahami itu. “Dasar hidup manusia itu kan ada dua ya, dasar material dan spiritual," kata dia.
Nah, secara spirit bisa saja manusia ingin menonton wayang, tetapi secara material mereka tidak terdukung. Misalnya, menonton wayang tidak semudah menonton televisi yang cukup di rumah duduk dan tidak mengeluarkan uang.
"Nah, kalau dia nonton wayang kan harus punya waktu, tenaga, uang, pikiran juga kan,” ujarnya.
Meski demikian, Eddy yakin, tidak ada budaya yang akan terus bertahan, karena sejatinya kebudayaan nanti hanya akan menjadi simbol. Bagi Eddy, bukan kebudayaannya yang harus dipertahankan, namun nilai-nilai kearifan yang terkandung dalam budaya itu yang harus bisa dipertahankan.
“Zaman pasti berkembang. Kita hanya perlu menyesuaikan seni budaya tradisional agar tetap bisa diterima di tengah-tengah perubahan atau perkembangan zaman saat ini,” tuturnya.

Budaya wayang orang masih akan tetap bertahan ditengah gempuran hiburan modern. (VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar)
Meski mengakui perubahan zaman yang tak bisa ditolak, Eddy yakin, wayang akan bisa bertahan. Dunia pewayangan yang multikarakter, menurut Eddy, adalah representasi dari karakter manusia.
Dunia pewayangan tak hanya bicara soal orang baik, namun juga ada tokoh jahat, tokoh yang menghasut, iri dengki, dan lain sebagainya. “Wayang adalah makro, alam jagat raya. Jutaan, bahkan miliaran karakter ada semua dalam tokoh wayang,” ujarnya.
Seorang pemain Sriwedari, Dhestian Wahyu Setiaji juga mengaminkan itu. Budaya pop yang serba cepat sangat kontras dengan budaya wayang yang sudah berusia berabad-abad.
Kultur dan kondisi sosial di mana budaya itu tumbuh sudah sangat jauh berbeda. Namun, itu bukan berarti wayang akan tersingkir habis oleh budaya pop.
“Saingan kita itu kan saat ini memang hiburan-hiburan yang memiliki genre pop dan lain sebagainya," kata dia.
"Ketika ingin menggelar pertunjukan wayang orang itu kan setidaknya kami juga membutuhkan supporting tata artistik panggung yang juga harus bagus, khususnya untuk kami yang di Sriwedari. Kami tidak punya fasilitas yang mendukung itu semua,” ujar pria yang berusia 27 tahun tersebut.
Wahyu tak ingin melihat merebaknya budaya pop sebagai hambatan. Bagi pekerja seni tradisional, sepertinya ia memilih memecut diri untuk bisa terus mempertahankan eksistensi wayang orang. Ia memilih melakukan sesuatu agar wayang orang tak tergerus.
“Kami ingin wayang ini tetap berkembang, jadi kami akan terus berupaya agar kesenian ini bisa lestari,” ujarnya.
Selanjutnya, Tak Hilang Tergerus Zaman
Tak Hilang Tergerus Zaman
Meski terus mendapat gempuran, masih banyak yang memilih bertahan. Rasa cinta pada budaya tradisional ini menjadi alasan utama.
Enny Sulistiowati salah satunya. Ia mengaku setia menjaga wayang orang karena sudah mencintainya. “Wayang itu secara pendalaman, secara filosofi sebenarnya sudah sampai pada tingkatan yang tidak ada bandingnya," tuturnya.
Wayang itu tidak ada bandingnya dibandingkan film, sinetron. "Secara filosofis, wayang memiliki nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia,” Enny menjelaskan alasannya.
Enny juga menjelaskan, wayang berasal dari kata “wewayangan,” atau bayang-bayang. “Jadi, apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya sudah ada di wayang zaman dahulu, sudah dikisahkan dalam cerita pewayangan. Dan itulah keunggulan wayang,” ujar perempuan yang juga ikut bermain sebagai Dewi Badari Supraba dalam lakon “Mintaraga.”
Dewi Badari Supraba membantu Arjuna mengalahkan Niwoto Kawojo dengan cara membantu para dewa mencari kelemahan raksasa ankara itu.
Suparmin Senjoyo, ketua umum Senawangi juga masih optimistis. Ia yakin, wayang orang akan bertahan. Sebab, pendukungnya masih banyak, khususnya komunitas-komunitas di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali.
Selain itu, dari segi sumber daya manusia, proses regenerasinya terus berjalan. “Jumlah sanggar di Pulau Jawa itu sangat banyak, 200an lebih mungkin. Sekolah kejuruan tingkat menengah, jurusan pedalangan juga sudah cukup banyak, malahan di level universitas itu sekarang kan sudah ada ISI, ISI Surakarta, ISI Bandung, dan lain sebagainya,” dia menjelaskan.
Kendala bagi Suparmin adalah bagaimana menarik minat agar orang mau menonton wayang. Ia menyadari semakin banyaknya jenis hiburan yang semakin modern, mengikuti gaya hidup masyarakat yang terus berubah.
Banyak cara untuk bertahan, menurut Suparmin, salah satunya adalah bersedia adaptif dengan perubahan. Ia bahkan bersedia melakoni wayang dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, agar peminat wayang dari generasi muda terus terjaring.
Optimisme pada kelestarian wayang orang juga diaminkan oleh Kondang Sutrisno, ketua umum Persatuan Pedalangan Indonesia (Pepadi). Ia memiliki barometer sendiri untuk rasa optimismenya.
Menurut Kondang, tiap tahun selalu ada pertemuan ‘Dalang Bocah’, dengan tingkat partisipasi yang terus bertambah. Ia juga merujuk pada berbagai pementasan wayang orang yang masih terus ada, bahkan nyaris setiap hari.
“Wayang orang Sriwedari masih berpentas setiap hari, dan penontonnya tetap banyak,” ujarnya.
Meski minim perhatian pemerintah pusat, wayang orang Sriwedari memang masih terus menjalankan aktivitasnya. Mereka tampil nyaris setiap hari, tanpa libur.

Diperlukan perhatian khusus dari pemerintah kepada para pemain wayang orang untuk menjamin kesejahteraan mereka. (VIVA.co.id/Fajar Sodiq)
Bahkan jumlah penonton masih bisa mencapai 700 hingga 800 orang. Dukungan penuh diberikan oleh Pemerintah Kota Solo dalam bentuk perhatian pada infrastruktur dan kesejahteraan pemain.
Sebagian pemain diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan sebagian lainnya menjadi tenaga kontrak dengan gaji setara PNS.
Meski demikian, para pemain wayang orang Sriwedari tetap menjalani perannya dengan profesional. Mereka menyadari, ada sesuatu yang lebih dari sekadar nilai finansial yang membuat mereka terikat.
Bagi Suparmin, Eddy, Enny, Kondang, dan Dhestian, melakoni peran mereka dalam pewayangan bukan sekadar peran kosmetik. “Wewayangane ngaurip,” begitulah mereka menjalaninya, melakoni peran itu adalah menjalani kehidupan mereka sendiri.
Mereka ingin mengingatkan, wayang adalah refleksi kehidupan manusia, sejak dari dalam kandungan, lahir, tumbuh besar, hingga kematian, termasuk pertikaian, permusuhan, cinta kasih, perdamaian, tokoh jahat dan tokoh baik, itu semua adalah kehidupan, dan itu semua tergambar dalam pewayangan.
Para pelakon sepakat, wayang orang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pemain, kondisi sosial, dan bahasa yang digunakan mungkin bisa berubah, namun nilai-nilai kebaikan, budi pekerti, dan filosofi menjalani hidup yang tersimpan dalam cerita tak boleh luntur. Dan sejatinya, nilai-nilai itulah yang perlu terus diwariskan. (art)