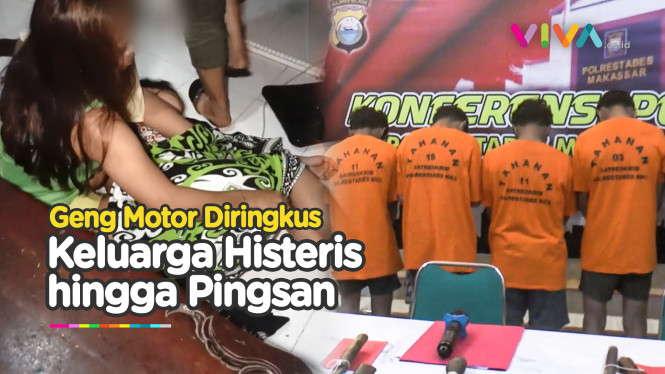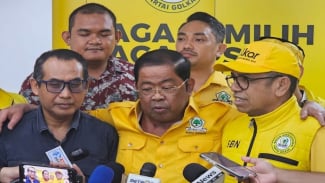- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Tragedi Reza Ikhsan Fadillah, yang meninggal dunia akibat di-smackdown kakak kelasnya pada 2006 silam, terulang lagi pada 2015. Kali ini korbannya berinisial NA.
Dia baru bocah 8 tahun, siswa SD Negeri 07 Pagi, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Jakarta. NA meregang nyawa setelah dihajar teman sekolahnya pada 18 September 2015.
Dia langsung tak bergerak setelah kepalanya dipukul, ditendang, dan diinjak oleh temannya, yang berinisial R, juga berumur 8 tahun. Kejadiannya berlangsung di dalam ruang kelas.
Belum diketahui pasti sebab musabab peristiwa itu. Namun, menurut para saksi, korban dan pelaku terlihat sering saling ejek, lalu berkelahi.
Sembilan tahun lalu, Reza Ikhsan Fadillah mengalami peristiwa serupa dengan NA. Dia dibanting, kepalanya dihujamkan ke lantai, dan kemudian tangannya ditekuk.
Murid kelas tiga SD di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, itu diperlakukan begitu karena teman-temannya meniru tayangan berkelahi bebas bohong-bohongan SmackDown pada sebuah stasiun televisi.
Kekerasan berujung maut yang dialami NA ditengarai masih ada hubungan dengan tayangan televisi. Acaranya bukan lagi gulat "SmackDown," karena siaran itu sudah ditiadakan tak lama setelah musibah yang menimpa Reza Ikhsan.
Namun, di televisi, banyak tampil tayangan-tayangan perkelahian atau semacamnya, yang bisa mengilhami anak-anak. Mereka mengingatnya dengan detail adegan-adegan itu, lalu menirunya ketika di sekolah atau tempat bermain.
Prasangka itu bukan tanpa dasar. Publik mafhum, banyak tayangan televisi yang menampilkan adegan kekerasan, tak hanya yang vulgar seperti SmackDown tetapi juga yang samar-samar seperti suatu tayangan sinetron yang menampilkan adegan perkelahian.
Tayangan itu berdampak fatal. Hasrandra, bocah SD, meninggal dunia pada 30 April 2015. Dia ditendang dan dipukul teman-temannya, seperti yang mereka lihat dalam sinetron lokal tersebut.
Siaran bermuatan kekerasan tak lagi didominasi film atau serial impor, tetapi juga sinetron maupun reality show produksi lokal. Waktu penayangannya pun dianggap berpotensi besar ditonton anak-anak. Ditambah kepedulian orang tua yang masih minim sehingga abai mengontrol tontonan bagi anak-anak mereka.
Televisi berperan besar
Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Maria Advianti, membenarkan prasangka bahwa televisi berpengaruh besar pada perilaku anak-anak. Apalagi anak-anak dapat menonton televisi kapan pun, di rumah atau di tempat lain di lingkungannya.
Anak-anak, kata Maria, pada dasarnya hanya meniru. Perilaku itu bisa mereka dapatkan dari kedua orang tua di rumah. Anak yang hidup dalam keluarga yang taat beribadah, sedikit atau banyak akan turut rajin beribadah. Begitu juga sebaliknya.
Anak-anak yang meniru-niru adegan kekerasan, boleh jadi terilhami perilaku serupa yang dilihatnya dari orang tuanya. Misalnya, orang tua yang bertengkar.
Namun, tetap saja, potensi besar ada pada televisi. Orang tua yang, umpamanya, sibuk bekerja di luar rumah akan berkurang waktunya untuk anak-anak mereka.
Selama tidak bersama orang tua, anak-anak biasanya menonton televisi. Pada saat-saat seperti itu tak ada orang dewasa yang mengawasi mereka menyaksikan tontonan yang baik atau sebaliknya.
“Bisa dibilang bahwa televisi lebih berdampak ketimbang perilaku kekerasan yang dilakukan orang tuanya sendiri. Televisi ada dimana-mana, tiap rumah ada, mungkin setiap rumah di Indonesia punya televisi, atau bahkan tidak hanya satu tapi di tiap kamar ada,” kata Maria ditemui di kantornya di Jakarta pada Rabu, 23 September 2015.
Maria tak memungkiri asumsi bahwa lingkungan sekolah --selain keluarga-- turut membentuk perilaku anak. Perkelahian atau tawuran di sekolah bisa menginspirasi anak-anak melakukan hal serupa di luar. Tetapi potensi terbesar tetaplah televisi, karena anak-anak bisa tanpa batas waktu untuk menontonnya. Apalagi kalau orang tua mereka tak peduli.
Solusinya, kata Maria, bukan melarang anak menonton televisi, tetapi membatasinya dan mengarahkan pada aktivitas lain yang lebih bermanfaat. Misalnya, arahkan anak-anak berkegiatan yang lebih mendorong psikomotorik atau aktivitas fisik seperti bermain lari atau kejar-kejaran.
“Kalau anak hanya dilarang nonton TV tapi tidak diberikan alternatif hiburan yang lain, anak-anak bisa stres, bisa berontak pula. Sekarang anak-anak kritis: kenapa tak boleh nonton, lalu apa kegiatan untuk kami,” ujar Maria.
Pendapat serupa diungkapkan Ketua Komisi Nasional Perlindungan, Arist Merdeka Sirait. Dia bahkan mengaku sangat yakin bahwa televisi berperan amat besar bagi perkembangan psikologi anak. “Ya, tentu, karena saat ini tayangan televisi sebagian besar mempertontonkan nilai-nilai yang mengandung kekerasan,” katanya ditemui di kantornya di Jakarta, Kamis, 25 September 2015.
Selain itu, Arist menambahkan, ada juga faktor lain yang ikut memengaruhi perilaku anak, yakni media sosial dan perangkat telepon seluler (ponsel) pintar atau komputer tablet. Media sosial adalah sarana yang cukup efektif untuk penyebaran informasi, bahkan nyaris tak bisa dikontrol. Tayangan yang tak lulus sensor untuk televisi, umpamanya, bisa menyebar dan dapat ditonton dengan bebas di media sosial berbagi video.
Di jagat maya berlimpahan pula aplikasi permainan yang dapat diunduh secara gratis dan dimainkan lewat ponsel pintar maupun komputer tablet. Tak sedikit orang tua yang tak memerhatikan ponsel pintar anak mereka telah terpasang aplikasi permainan kekerasan, seperti perkelahian atau pertarungan bebas.
Guru dan orang tua
Pengaruh buruk televisi dan permainan kekerasan pada gadget sebetulnya dapat dikurangi atau bahkan dicegah dengan peran orang tua dalam keluarga dan guru di sekolah. Orang tua bisa mengontrol anak-anak mereka menonton televisi: melarang menyaksikan tayangan kekerasan, memberikan bimbingan manakala memirsa program yang mengandung muatan berbahaya, atau memeriksa permainan digital pada ponsel pintar atau atau komputer tablet, dan lain-lain.
Para guru di sekolah pun dapat membantu memberikan bimbingan tentang tontonan-tontonan berbahaya bagi anak-anak.
Namun dalam banyak kasus, tidak sedikit orang tua yang masa bodoh dengan tontonan anak. Kadang mereka waspada terhadap tayangan yang secara vulgar menampilkan adegan kekerasan, tetapi menganggap tak masalah untuk siaran yang samar-samar bermuatan kekerasan, misalnya, sinetron yang mempertontonkan adegan bullying atau kekerasan nonfisik.
“Diperburuk dengan kesibukan orang tua sehingga anak dengan bebas menonton berbagai tayangan kekerasan dan cerita-cerita alay (remaja belia), sinetron yang mempertontonkan kesinisan, balas dendam hingga bullying. Itu semua terekam di kepala anak,” kata Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati, di kompleks Parlemen di Jakarta, Rabu, 23 September 20015.
“Ditambah berbagai game (permainan) kekerasan yang juga dimainkan anak. Secara tidak sadar mereka menjadi belajar memukul, menebang, dan melakukan kekerasan lainnya,” kata Reni.
Persoalan lain ialah kapasitas guru. Diakui atau tidak, masih banyak guru di Indonesia yang hanya memiliki kemampuan mengajar tetapi tidak cakap mendidik. Kemampuan guru untuk mendidik menjadi tidak berkembang karena kurikulum pendidikan nasional yang cenderung berat atau tak sesuai dengan tingkat perkembangan anak-anak.
“Masa anak TK (taman kanak-kanak) dipaksa bisa baca dan berhitung sebelum masuk SD. Mereka itu harus belajar dengan cara bermain jangan dipaksa,” ujarnya.
Reni berpendapat, tak dapat disalahkan ketika adegan-adegan kekerasan terekam dalam otak anak-anak lalu mereka mempraktikkannya di sekolah maupun di rumah. Mereka bahkan kadang merasa tak bersalah telah mengasari temannya, termasuk ketika sampai meninggal dunia. Soalnya orang tua terlalu sibuk atau abai, sementara guru lebih fokus pada mengajar sesuai standar kurikulum.
Pada pokoknya, menurut Arist Merdeka Sirait, anak tak dapat disalahkan. “Orang dewasa berkontribusi. Dunia pendidikan pun secara tidak langsung, mengajarkan kekerasan, karena anak hanya dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual.”
Tak Melulu Televisi
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sependapat dengan pandangan bahwa televisi berpengaruh besar dalam membentuk perilaku kekerasan pada anak. Namun televisi bukan satu-satunya sebab. “Pengawasan orang tua, faktor media lain selain televisi, seperti internet, gadget atau PS (permainan PlayStation),” kata Wakil Ketua KPI, Idy Muzayyad.
KPI telah membuat regulasi, di antaranya, menetapkan klasifikasi tayangan yang aman untuk anak-anak, hanya untuk orang dewasa, atau baik buat semua umur. Misalnya, tayangan yang baik untuk anak-anak diberi kode A/SU (Anak/Semua Umur), tayangan yang boleh ditonton anak-anak tapi dengan bimbingan orang tua diberi kode BO/A (Bimbingan Orangtua/Anak), tayangan yang hanya untuk orang dewasa dengan kode D (dewasa).
Tetapi, kata Idy, klasifikasi itu pun tak menjamin tayangan benar-benar aman untuk anak-anak. Tayangan berita yang dalam klasifikasi SU, misalnya, bisa memuat informasi tentang kekerasan dan tetap memerlukan bimbingan orang tua.
“Sering kali yang menganggu psikologi itu program berita tentang tawuran dan kerusuhan. Berita kayak begitu, kan buruk, dan packaging-nya (penyajiannya) enggak boleh ditunjukan yang sadis-sadis,” ujarnya.
KPI, Idy menambahkan, pun bukan satu-satunya lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas media penyiaran televisi. Soalnya wewenang KPI hanya pada urusan setelah tayang, bukan sebelum tayang. Artinya, KPI mengawasi ada pelanggaran atau tidak setelah program siaran ditayangkan, bukan sebelum itu.
Kalau ditemukan pelanggaran, KPI pasti menindak televisi yang bertanggung jawab. Sanksi berupa teguran sampai pemberhentian izin siaran.
Ada bagian yang bukan wewenang KPI tetapi vital bagi televisi, yakni otoritas sensor. Perkara itu adalah urusan Lembaga Sensor Film (LSF), terutama tayangan yang bukan berita, seperti film, sinetron, reality show, dan sejenisnya. Tak jarang ditemui tayangan yang telah dinyatakan lolos sensor LSF tapi masih bermuatan kekerasan.
“Kalau ada kecenderungan masih ada program siaran (bermuatan kekerasan) di TV maka yang patut dipersoalkan adalah sejauhmana proses dan parameter sensor itu dilakukan. Karena KPI itu, kan, menghakimi, mengkaji sesudah tayang,” ujar Idy.
Penilaian itu dibenarkan Pribudiarta Nur, Deputi Perlindungan Anak pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Menurutnya, tidak sedikit tayangan, misalnya, film animasi yang tampak aman bagi anak-anak dan lolos sensor LSF, tetapi sesungguhnya masih mengandung muatan berbahaya.
Pribudiarta mencontohkan film-film kartun atau animasi yang menampilkan adegan memukul orang lalu orang itu tak terluka sedikit pun dan tampak baik-baik saja. Anak-anak yang menonton tayangan itu lantas meniru atau mempraktikkannya karena mereka menganggap tak berbahaya seperti pada film.