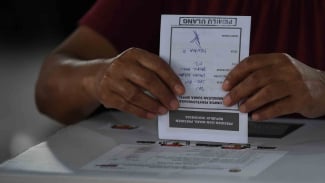- ANTARA FOTO/Rachman
VIVAnews – Ketukan palu Priyo Budi Santoso mengakhiri perdebatan panjang terkait mekanisme pemilihan kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan revisi Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah yang salah satu isinya mengembalikan pemilihan kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
"Dengan demikian rapat paripurna DPR memutuskan, untuk substansi ini adalah pilihan lewat DPRD," ujar Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, saat memimpin sidang paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat dini hari, 26 September 2014.
Keputusan ini tak jadi dilaksanakan. Pasalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah. Perppu ini membatalkan sekaligus mencabut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Kini, setelah lima tahun berlalu, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD kembali mengemuka. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melontarkan gagasan agar Pilkada langsung dikaji dan dievaluasi kembali. Pasalnya, pilkada langsung dinilai boros, rawan kerusuhan dan praktik korupsi. Mantan Kapolri ini mengusulkan pilkada dengan sistem Asimetris.
Ide Tito ini memang tak sepenuhnya mengembalikan pilkada ke tangan DPRD. Namun, sebagian kalangan menilai ini merupakan langkah mundur. Karena, akan mencabut kedaulatan rakyat dalam memilih dan menentukan kepala daerahnya. Seperti zaman Orde Baru (Orba), dimana kedaulatan rakyat dikangkangi karena kepala daerah diputuskan oleh pemerintah pusat dan segelintir elite.
Pilkada ala Orba
Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI, Dini Suryani, mengatakan, pilkada di masa Orde Baru adalah wujud sistem sentralisasi dan wujud nyata dominasi pemerintahan yang otoriter. Menurut dia, pada masa itu, sesuai dengan Pasal 15 UU No 5 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih oleh pusat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya bersifat mengajukan rekomendasi kepala daerah, tetapi keputusan akhir tetap ada di tangan pemerintah pusat.
“Biasanya kepala daerah kabupaten kota di-acc oleh Kemendagri, dan gubernur di-acc oleh presiden,” ujarnya kepada VIVAnews, Jumat 29 November 2019.
Hal ini memperlihatkan cengkeraman yang sangat kuat dari pemerintah pusat dalam mengontrol daerah. Apalagi, di masa Orba, kepala daerah mayoritas berasal dari kalangan militer, di mana orang yang berpangkat jenderal diberikan jabatan gubernur dan orang yang berpangkat perwira menengah bisa menjadi bupati atau wali kota.
“Presiden Soeharto yang berasal dari militer akan lebih mudah mengontrol jika kepala daerahnya juga berasal dari kalangan yang sama,” ujar pengamat politik jebolan The Australian National University ini.
Menurut Dini, pemilihan via DPRD baru benar-benar dilaksanakan ketika UU No 22/1999 dijalankan, ketika DPRD diberi wewenang lebih dan diposisikan berada di luar pemerintahan. Kelebihannya, proses pilkada relatif lebih cepat dan cenderung lebih murah. Sementara kekurangannya, orang-orang yang duduk di DPRD tidak bisa dijamin memiliki integritas untuk memilih calon kepala daerah secara objektif berdasarkan kapabilitas dan kapasitas yang dibutuhkan seorang kepala daerah.
“Dalam banyak kasus, di era pilkada via DPRD, anggota DPRD banyak disuap oleh calon kepala daerah agar mereka terpilih. Kekurangannya yang lain adalah tidak terciptanya akuntabilitas vertikal antara kepala daerah yang bertanggung jawab kepada masyarakat.”
Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, sependapat. Dugaan terjadinya suap menyuap begitu kental dalam pilkada melalui DPRD. Namun, menurut dia, kritik terbesar terkait pilkada tak langsung karena publik atau rakyat hanya menjadi penonton. Selain itu ada gap antara aspirasi masyarakat terhadap figur kepemimpinan daerah dengan pilihan yang dibuat oleh DPRD.
“Ada disparitas antara aspirasi dan pandangan politik warga dengan keputusan politik yang dibuat oleh DPRD,” ujarnya.
Banyak Mudaratnya
Menurut Titi, salah satu alasan pilkada digelar secara langsung adalah agar prosesnya transparan dan publik bisa mengawasi dengan baik. “Dulu mengapa kita beralih dari tidak langsung ke langsung salah satunya karena ingin mengatasi politik transaksional dalam ruang gelap pemilihan oleh DPRD,” ujarnya kepada VIVANews, Rabu 27 November 2019.
Pendapat senada disampaikan Jansen Sitindaon. Ketua DPP Partai Demokrat ini mengatakan, salah satu yang menjadi tuntutan reformasi adalah mengembalikan kedaulatan kembali ke tangan rakyat. Salah satunya dengan melakukan pilkada langsung.
“Kalau di zaman Orba tidak ada pilkada langsung. Tidak ada kedaulatan rakyat waktu itu. Padahal yang tertinggi dalam demokrasi adalah kedaulatan rakyat,” ujarnya kepada VIVAnews, Jumat 29 November 2019.
Menurut dia, salah satu dampak negatif dari pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah rakyat tidak bisa menyalurkan suaranya. “Rakyat tidak bisa memilih siapa yang akan jadi pemimpinnya,” ujarnya menambahkan.
“Belum lagi anggota DPRD tidak mungkin melawan ketua umum partainya kan. Jadi di situ rakyat telah kehilangan haknya.”
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, pilkada melalui DPRD lebih banyak mudaratnya dibanding pilkada langsung. “Kita semangat menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke rakyat tidak lagi mekanisme via DPRD karena pada masa itu (orba) sangat kental dengan KKN dan tidak fair. Karena kepala daerah hanya ditentukan atau dipilih DPRD,” ujarnya, Rabu, 28 November 2019.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini menjelaskan, ada sejumlah mudarat atau dampak negatif jika kembali menggelar pilkada ala Orba. Pertama, tidak ada jaminan bisa menekan biaya pemilu. Menurut dia, pemilu paket hemat itu bisa dilakukan dengan memperbaiki sistem pemilu.
Selain itu, jika dipilih DPRD, tidak ada lagi kepala daerah yang mau blusukan menemui rakyatnya. Karena mereka tak butuh lagi suara rakyat di TPS. Mereka hanya berkepentingan dengan anggota DPRD.
Selain itu partai kecil juga akan sulit bisa terpilih menjadi kepala daerah. “Maka kalau nanti Pileg 2024 dimenangkan Gerindra misalnya. Maka ada kemungkinan besar semua kepala daerah berasal dari kader Gerindra, karena berbasiskan jumlah kursi paling banyak di DPRD. Nanti kalau divoting sangat kecil kans bagi partai kecil bisa terpilih kadernya menjadi kepala daerah di suatu daerah,” ujarnya menjelaskan.
Mengembalikan pilkada kepada DPRD juga menghilangkan partisipasi politik masyarakat dalam menentukan dan memilih kepala daerahnya. Selain itu juga perhatian dan kepedulian kepala daerah terhadap aspirasi masyarakat daerah akan berkurang. “Selain itu juga terbuka peluang politik dagang sapi maupun bentuk bentuk model transaksi politik lainnya.”
Sementara itu, menurut Dini, pilkada via DPRD akan mencabut hak konstitusional warga negara untuk terlibat aktif dalam politik dengan memilih langsung pemimpinnya dan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 18 ayat (4) tentang kedaulatan rakyat. Selain itu juga akan menghilangkan aspek akuntabilitas vertikal yang memungkinkan kepala daerah memiliki rasa tanggung jawab kepada masyarakat.
“Jika pemimpin tidak memiliki aspek ini, dia tidak akan berupaya untuk berkomitmen menyelesaikan permasalahan masyarakat dan melayani publik.”
Menggeser Demokrasi ke Oligarki
Pilkada lewat DPRD juga dikhawatirkan akan membuat oligarki semakin menguat. Menurut Titi, oligarki akan makin menguat karena keputusan makin eksklusif, elitis, serta jauh dari partisipasi dan akuntabilitas publik. Selain itu, ruang korupsi politik juga bisa makin leluasa karena kekuasaan dikendalikan segelintir orang dan sulit untuk dievaluasi oleh publik akibat mekanisme yang ada tidak tersedia untuk itu.
“Sangat mungkin tradisi politik yang elitis ini juga malah terus terbawa dalam relasi kepemimpinan kepala daerah setelah terpilih. Alih-alih berorientasi pada pelayanan publik, malah terjebak pada hubungan timbal balik dengan aktor-aktor politik di DPRD,” ujarnya.
Sementara itu, menurut Pangi, jika pilkada diserahkan kepada DPRD tetap membuka lebar peluang permainan politik uang dan transaksi politik. Hal ini terbukti ketika rezim Orba berkuasa, politik uang berlangsung di tataran DPRD.
“Itulah asbabul nuzul mengapa pada masa itu kita rindu dan bersemangat pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara langsung tidak lagi via DPRD.”
Presiden PKS, Sohibul Iman, mengatakan, hari ini oligarki di dalam politik sangat luar biasa. Jika pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD maka kemungkinan oligarki semakin berkuasa akan sangat luar biasa. Karena, ruang eksploitasinya itu semakin menyempit, semakin memudahkan mengelola oligarki.
“Karena itu kami masih berpendapat bahwa pemilihan langsung itu masih lebih baik, karena para oligarki tidak memiliki keleluasaan yang lebih besar dibandingkan ketika itu dilaksanakan oleh DPRD,” ujarnya kepada VIVAnews, Jumat 29 November 2019.
Ia mengatakan, kalau sebuah daerah anggota DPRD cuma 50 orang, berarti oligarki cukup mengendalikan 50 orang itu. Sementara kalau itu dibuka sebagai pemilihan langsung mereka tentu tidak akan semudah itu melakukan penguasaan politik. “Jadi kami masih menilai pilkada langsung masih lebih baik. Kedua, kalau pemilihan itu lewat DPRD kemungkinan orang- orang yang punya kapasitas, kapabilitas integritas mereka tidak akan bisa mendapatkan kesempatan masuk dalam sirkulasi kekuasaan. Tetapi kalau dipilih oleh rakyat, orang-orang yang berintegritas masih punya peluang untuk masuk sirkulasi kekuasaan.”