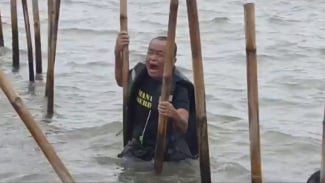- ANTARA FOTO/Indrayadi TH
VIVA – Hampir kurang lebih 5 menit Adnan menatap ponselnya, sesekali ia terlihat senyum-senyum sendiri. Tak lama ia beralih ke layar laptop sambil menggerak-gerakan mouse, lalu mulai mengetik dan melanjutkan pekerjaannya. Tak sampai 20 menit, Adnan kembali menengok ponselnya dan menatapnya lagi. Begitu seterusnya.
Adnan (27) adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Sehari-hari ia tak pernah lepas dari gadget. Tak hanya handphone (Hp), Adnan juga kerap berselancar di dunia maya lewat laptop.
"Setiap hari pastilah internetan. Dari melek mata sudah scrolling medsos (media sosial), cek e-mail, cek whatsapp, browsing info-info baru," ujar Adnan kepada VIVA Rabu 16 Januari 2019.
Tak hanya itu, Adnan mengatakan, sepanjang perjalanan ke kantor saat naik kendaraan umum ia juga tak absen menatap ponselnya. Belum lagi di kantor saat bekerja, hingga pulang kantor dan sebelum ia terlelap tidur, ponsel tak jauh darinya.
"Ya mau gimana ya, memang semua pekerjaannya di situ. Belum lagi kalau mau pesan ojek online, komunikasi sama teman semua serba digital. Jadi mau enggak mau ya harus cek Hp," ujarnya beralasan.

Banyak orang kecanduan gadget
Tak hanya Adnan, ternyata jutaan manusia di dunia telah kecanduan digital. Dua peneliti dari University of Hong Kong, Cecelia Cheng dan Angel Yee-lam melakukan sebuah studi yang dirilis tahun 2014 silam dalam jurnal Cyberpsychology, Behavior and Social Networking. Mereka menemukan bahwa kecanduan digital memengaruhi enam persen atau 182 juta orang dari seluruh populasi di dunia.
"Ada 182 juta orang yang menghabiskan waktunya di dunia maya. Mereka bisa melakukan banyak hal dengan internet dan gadget di tangannya," ujar Chang dilansir The Sun.
Keduanya lalu memilih 80 studi global meliputi laporan kecanduan internet di 31 negara di tujuh kawasan termasuk Amerika Serikat, Australia, Austria, Estonia, Perancis, Jerman, Irlandia, Norwegia, Swedia, Inggris, Bulgaria, Siprus, Republik Ceko, Yunani, Hungaria, Italia, Polandia, Rumania, Serbia, Slovenia, Spanyol, Iran, Isarel , Lebanon, Turki, Cina, Hong Kong, India, Korea Selatan, Taiwan dan Columbia.
Dari banyaknya negara tersebut ternyata Timur Tengah adalah wilayah yang paling banyak mengalami kecanduan internet di dunia (10,9 persen, termasuk Iran, Israel, Lebanon dan Turki).
Sementara itu di luar dugaan, prevalensi terendah dilaporkan di Amerika Utara dan Eropa Barat yang memiliki tingkat kecanduan internet 2,6 persen. Sedangkan Eropa Selatan dan Timur berada di angka 6,1 persen.
Dilansir laman Daily Mail, Dr Richard Graham yang menjalankan program kecanduan digital di Rumah Sakit Capio Nightingale, London mengatakan bahwa internet menyediakan hal paling mendasar dalam kehidupan yang diinginkan setiap manusia yakni kebebasan untuk mengekspresikan diri dengan cara yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Ekspresi tersebut diutarakan lewat media sosial seperti Twitter, Facebook, YouTube atau menuliskan komentar menanggapi sebuah artikel berita.
"Orang-orang menggunakan internet untuk menghilangkan stres dan dengan internet mereka menemukan cara untuk mengekspresikan diri sehingga mereka merasa lebih nyaman menjadi diri sendiri," ujarnya.
Namun, Graham juga mengatakan bahwa hal tersebut kemudian menciptakan risiko yakni orang tidak menghadapi isu-isu penting secara langsung.
"Saat ini orang bahkan tak hanya kecanduan internet, tapi juga mengalami kecanduan teknologi di mana gadget atau ponsel pintar harus selalu ada di genggaman karena kebutuhan konstan mereka untuk menggunakan internet," tambahnya.

Para pemilih gadget rentan mengalami kecemasan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)
Hal tersebut dibuktikan dengan studi dari Front Range yang belum lama ini dilakukan. Studi tersebut menunjukkan bahwa lebih dari setengah pemilik gadget atau sebanyak 53 persen orang di seluruh dunia mengaku menderita kecemasan ketika mereka tidak dapat menggunakan ponsel mereka.
Keadaan tanpa teknologi dalam hal ini gadget digambarkan sebagai keadaan yang mampu menyebabkan stres seperti ketika mereka pergi ke dokter gigi atau menghadapi hari pernikahan.
Lalu bagaimana dengan adiksi digital bagi pengguna internet di Indonesia? Soal ini Tenaga Ahli Menteri Bidang Literasi Digital, Doni BU menanggapinya dengan berkaca pada data yang disajikan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)
"Kalau baca riset APJII tentang Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet tahun 2017, di sana ada soal durasi penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia. Ternyata rata-rata masyarakat Indonesia gunakan internet 1-3 jam sehari," ujar Doni kepada VIVA Kamis 17 Januari 2019.
Mirisnya ia menekankan bahwa ternyata durasi masyarakat menggunakan internet ada yang lebih dari itu.
"Ada pula pengguna yang mengakses internet selama 4-7 jam dalam sehari.
Kenyataan itu tentu berdampak serius. Tak hanya masalah kesehatan fisik seperti kualitas penglihatan yang menurun atau memicu back pain, namun juga pada masalah mental disorder hingga adiksi. Bahkan, kini sudah banyak orang yang kecanduan game hingga mengalami disfungsi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
"Jadi tidak mau kuliah, sekolah, dan pertengkaran keluarga. Dia jadi mudah marah, ayah ibunya jadi berantem, dan itu semua disfungsi. Orang yang kecanduan memang sulit menghentikannya. Dari penelitian Neuroimaging pada otak memang ada gangguan pada otaknya. Jadi dia memang tidak bisa menghentikan sendiri hingga butuh terapi."
Mengenal Kecanduan Digital, Tak Sekadar Ketagihan
Mungkin ancaman kecanduan yang ditimbulkan dari penggunaan internet dan perangkat digital belum terlalu berdampak pada kehidupan Anda, namun ancaman tersebut nyata. Sebelum lebih jauh bicara soal kecanduan digital, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu kecanduan digital.
Secara harfiah kecanduan digital diartikan sebagai perilaku adiksi terhadap konten digital. Pakar psikologi Dr. Neila Ramdhani, M.Si., M.ED dari Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada (UGM) mengatakan, kecanduan dikenal dengan Internet Addiction Disorder, atau kecanduan internet lewat teknologi digital.
"Kalau kecanduan digital, bukan digitalnya. Tapi isinya. Misalnya game online hingga sosial media. Game yang sifatnya digital dengan tampilan yang bagus karena teknologi digital," ujarnya kepada VIVA di Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, Rabu 16 Januari 2019.
Sementara itu, menurut laman Psycom, Internet addiction disorder adalah kondisi seseorang yang adiksi dan kompulsif menggunakan internet. Kondisi ini biasa disebut iDisorder.
Awalnya kondisi ini diperdebatkan dan diragukan para ahli sebagai hal yang nyata. Namun pada 1995 iDisorder digambarkan sebagai hal satir. Dalam sebuah literatur yang ditulis oleh pakar kesehatan jiwa, Dr. Ivan Goldberg, MD membandingkan kondisi ini dengan kondisi mental dalam kegiatan perjudian.
Namun seiring berjalannya waktu, ternyata kondisi kecanduan internet meningkat pesat. Selain itu yang mengejutkan angka prevalensinya di Amerika dan Eropa memengaruhi 8,2 persen dari populasi. Bahkan ada juga yang menyebutnya mencapai 38 persen. Perbedaan persentase ini akibat tidak adanya standar yang sahih mengenai iDisorder.
Kemudian 10 tahun kemudian, iDisorder melahirkan istilah No Mobile Phone Phobia (Nomophobia). Kondisi ini merupakan sindrom ketakutan jika tidak mengakses konten telepon genggam (smartphone). Istilah ini muncul di Inggris lewat riset yang dilakukan oleh lembaga survei, YouGov. Mereka meneliti tentang kegelisahan yang kerap dialami oleh 2.163 responden karena tidak memegang ponsel dalam satu waktu.

Mereka mengalami kegelisana pada suatu waktu karena tidak bisa mengakses gadget. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Dalam Ilmu Psikologi, Neila menjelaskan, istilah kecanduan harus melewati beberapa kriteria diagnosis. Kriteria diagnosis ini ada yang digunakan para psikiater atau dokter, itu yang dinamakan pedoman dan penggolongan diagnosis gangguan jiwa (PPDGM).
"Di sana (PPDGM) memang ada yang namanya kecanduan atau adiksi. Dulu kecanduan itu kecanduan rokok, minuman keras, obat-obatan atau sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh," ujarnya.
Namun akhir-akhir ini menurutnya istilah itu berkembang. "Ternyata ada yang kecanduan judi, kecanduan yang sifatnya kecanduan perilaku (pengin melakukan hal itu lagi dan lagi). Kalau dulu judi, sekarang berkembang sejak ada teknologi. Teknologinya itu tidak nyandu sebenarnya, tapi sesuatu yang dilakukan dengan teknologi itu yang membuat orang nyandu."
Lalu kini apakah kondisi kecanduan tersebut masuk dalam kategori gangguan mental?
Sekelompok psikolog di Amerika Serikat percaya bahwa, orang yang kecanduan digital bisa dibilang mengalami gangguan jiwa jenis baru. Namun hingga kini penetapan gangguan jiwa karena ketergantungan internet memang masih menjadi perdebatan.
Penetapan diagnosis seputar gangguan mental mengacu pada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Buku ini digunakan, atau diandalkan, oleh dokter, peneliti, lembaga regulasi obat kejiwaan, perusahaan asuransi kesehatan, perusahaan farmasi, sistem hukum, dan pembuat kebijakan yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association (APA) dan diproduksi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
DSM sekarang dalam edisi kelima, DSM-5, yang diterbitkan pada 18 Mei 2013 lalu. Di dalamnya mengevaluasi pasien di lima sumbu atau dimensi, bukan hanya satu aspek yang luas dari 'gangguan jiwa'. Dimensi ini berhubungan dengan aspek biologis, psikologis, sosial dan aspek lainnya.
Dalam kasus kecanduan internet yang tercantum dalam DSM-5 baru gambling (judi online) sedangkan untuk gane dimasukkan ke bab yang harus dipelajari lebih lanjut sehingga belum dimasukkan ke dalam diagnosa.
Sementara itu, Psikiatri, dr. Eva Suryani, SpKJ mengatakan bahwa fenomena kecanduan terhadap konten gadget adalah nyata, dalam klasifikasi gangguan jiwa karena gejalanya menyerupai kecanduan narkoba. Dampaknya pun bisa nampak secara fisik, psikologis, maupun sosial. "Namun secara formal gangguan ini belum dimasukkan dalam klasifikasi diagnosis baik ICD 10 maupun DSM 5," ujarnya.
Penyebab Kecanduan Digital
Seperti pada banyak kasus soal adiksi, kecanduan digital memiliki banyak faktor pemicu. dr Eva menyebut ada 4 faktor yang melatarbelakangi terjadinya kecanduan digital, yaitu faktor internal, eksternal, situasional, dan faktor sosial.
"Faktor internal seperti aspek kontrol diri yang rendah, namun sifat sensation seeking-nya tinggi. Lalu self esteem-nya rendah, tapi di sisi lain ia juga memiliki kepribadian ekstraversion yang tinggi, habit menggunakan gawai yang tinggi, expectacy effect yang tinggi dan kesenangan pribadi yang tinggi," ujarnya.
Lalu faktor situasional, dipengaruhi oleh tingkat stres yang tinggi, kesedihan, kesepian, kecemasan, jenuh belajar, hingga tidak ada kegiatan saat waktu luang.
"Faktor eksternal, terkait dengan besarnya paparan media dalam memasarkan gawai dan fasilitas yang disediakan. Sementara itu faktor sosial mengarah pada perilaku yang harus dilakukan untuk memuaskan kebutuhan berinteraksi yang distimulasi atau didorong orang lain."
Di sisi lain, laman Psycom menulis bahwa ada bukti fisik bahwa adiksi digital mampu memengaruhi perubahan struktur otak.
Beberapa bukti menunjukkan bahwa pecandu internet memiliki susunan otak yang mirip dengan pecandu bahan kimia seperti misalnya obat-obatan dan alkohol. Selain itu terjadi perubahan struktur otak di area prefrontal, area ini terkait dengan ingatan detail, perhatian, perencanaan dan memprioritaskan tugas. Artinya, pecandu internet tidak bisa membedakan mana yang jadi prioritas dalam hidupnya.
Pakar Neurosience Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), dr.Rizki Edmi Edison juga menyebutkan hal serupa. Menurutnya kecanduan digital juga dipengaruhi efek hormon dopamin yang diproduksi otak saat mengakses konten digital.
Ia menyebut bahwa proses kecanduan terjadi ketika Ventro tagmental atau bagian otak tengah memproduksi hormon pemicu rasa senang (dopamin) yang ditembakkan ke Neucleos acumben (otak bagian depan). Aktivitas 'senang' itu terjadi ketika seseorang mengakses konten-konten internet misalnya medsos, hingga game online.
"Karena memunculkan perasaan senang, manusia tidak pernah merasa puas, selalu ingin dilakukan lagi dan lagi. Sehingga dalam otak akan banjir hormon dopamin yang terus menerus ditembak ke otak depan," ujar Rizki kepada VIVA ditemui di Jakarta.
Maka, lanjut Rizki yang terjadi kondisi itu akan memicu kerusakan pada otak depan. Sayangnya, otak depan memiliki berbagai fungsi kognitif seperti berpikir rasional, memorizing, berpikir analitik juga sistem bertahan untuk tidak berbuat kesalahan (breaking sistem).
"Nah, orang-orang yang sudah mengalami adiksi breaking sistem-nya sudah rusak. Akibatnya dia tidak bisa lagi menentukan prioritasnya apa. Kita tahu kita sedang rapat, sedang makan malam bersama, atau sedang rapat penting, tapi dia tetap saja 'phobi' lihat smartphone untuk sekadar cek sosmed."
Mirisnya, korban adiksi digital bisa siapa saja. Dr Rizki menyebut bahwa korban adiksi digital juga tak terbatas usia.
"Semua yang menggunakan gadget punya peluang terpapar. Yang tidak terpapar adiksi gadget adalah dia yang tidak memakai. Termasuk anak-anak," ujarnya.

Adiksi gadget sering dialami oleh anak-anak. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)
Ia juga menyebut bahwa anak-anak lebih rentan terpapar karena kemampuan otak depannya untuk berfikir rasional tidak sama seperti orang dewasa.
"Kalau orang dewasa minimal masih tahu mana yang rasional mana yang tidak, tapi kalau anak-anak yang dia tahu adalah mana kesenangan dia. Jadi anak-anak itu lah yang sebetulnya paling rentan untuk terpapar adiksi gadget."
Lalu bagaimana mengetahui bahwa seseorang sudah mengalami adiksi? dr Eva menjabarkan 6 ciri-cirinya.
"Ia akan mengalami perilaku kompulsif, lalu adanya konflik interpersonal, konflik dengan aktivitas lain, merasa hilang kendali, withdrawal atau menarik diri dan relapse, atau terjadi secara berulang-ulang."
Jika dibiarkan tentunya akan memicu dampak yang lebih buruk bukan hanya pada fisik tapi juga berdampak ke segala aspek mulai dari aspek psikologis hingga sosial.
"Misalnya efek fisik digital eye strain (penglihatan kabur, lelah, rasa terbakar dan gatal pada mata), text neck (sakit pada leher karena menunduk terlalu lama), cepat lelah, pusing, mual, sakit di tangan atau lengan, hingga penurunan konsentrasi."
Lalu pada efek psikologis, ditandai dengan terjadinya penurunan kualitas tidur, timbul ringxiety (phantom phone rings), cemas, depresi, hingga gangguan tidur.
"Sedangkan dampak sosialnya, tentunya pecandu digital akan mengalami problem komunikasi atau relasi dengan orang lain termasuk keluarga."
Terapi untuk Atasi Kecanduan
Di Indonesia salah satu layanan psikiatri yang mampu menangani pasien dengan ketergantungan (adiksi) adalah Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang bekerja sama dengan Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
Psikiater adiksi sekaligus Kepala Departemen Medik Kesehatan Jiwa RSCM-FKUI dr. Kristiana Siste Kurniasanti, SpKJ (K) menjelaskan bahwa tenaga di klinik adiksi ini terdiri dari para psikiater adiksi, psikiater anak dan remaja, ada juga psikiater marital therapy, dan neuropsikiatri.
"Klinik adiksi di poli dewasa memang sudah berdiri dari bulan juni 2018. Dan klinik itu memang masih untuk umur 18 tahun ke atas. Untuk anak dan remaja juga ada klinik adiksi. Rencananya akan jadi poli madya (rencana diresmikan 1-2 bulan ke depan). Nantinya remaja dan dewasa akan bergabung," ujarnya kepada VIVA Jumat 18 Januari 2019.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa klinik adiksi itu juga menangani pasien yang kecanduan internet, game, hingga pornografi.
"Dokternya lengkap, ada psikiater anak dan remaja, ada psikiater dewasa, ada tim dari gizi, karena mereka yang kecanduan bisa kegemukan karena pola makan tidak sehat. Dan bisa juga malnutrisi karena menolak makan. Selain itu ada dokter akupunktur hingga rehabilitasi medik untuk membantu pasien agar memiliki pola hidup yang sehat."
Pasien yang mengunjungi klinik untuk berobat berkisar di usia 18-21 tahun, namun ada juga yang usia remaja. Menurutnya, untuk pasien yang kecanduan game seringkali dari kalangan dewasa dan remaja muda.
Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, 10 persen remaja mengalami adiksi internet. Namun selama ini yang ia tangani di RSCM lebih banyak pasien dewasa muda. Hingga kini Siste mengaku ada sekitar 1 pasien dewasa muda yang ditanganinya secara rutin.
"Kebanyakan (pasien) pecandu game dan laki-laki. Kalau perempuan kebanyakan kecanduan media sosial, seperti instagram, facebook, line, dan saat ini yang banyak juga kecanduan judi bola."

Pasien adiksi didominasi oleh laki-laki dewasa muda. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Untuk menangani seseorang yang mengalami ketergantungan atau kecanduan memerlukan psikoterapi bahkan farmakoterapi untuk mengurangi tingkat adiksi dan dampak yang dialami. Siste juga mengatakan bahwa jika seseorang mengalami kecanduan internet, game, atau judi, maka harus cari tahu apa yang mendasarinya.
"Pertama kita mesti telusuri dulu, kenapa dia kecanduan. Apakah memang ada masalah psikologi yang mendasarinya. Misal mudah cemas dan depresi, atau orangnya merasa self esteem buruk. Nah, itu mesti kita perbaiki dulu."
Untuk obat-obatan, ada obat tertentu yang bisa mengalihkan pikirannya dari ketergantungan. Dan yang ketiga terapi perilaku.
"Jadi kita membantu pasien untuk membuat jadwal dan modifikasi lingkungan. Wifi itu tidak boleh ada di rumah, internet itu hanya boleh digunakan di area umum seperti di ruang makan yang mudah terlihat. Pasien tidak boleh menggunakan internet selama 4 jam dan selalu dalam pengawasan orangtua."
Rasanya memang mustahil untuk hidup tanpa gadget dan internet. Karena teknologi telah terlanjur menyentuh segala aspek kehidupan kita. Tak jarang, kita pun dibuat terlena atas segala kemudahan, hiburan hingga pencerahan yang mampu diberikannya.
Wajar pula bila kita merasa insecure tanpa gadget di tangan. Tapi sebaiknya Anda telaah lagi habit berteknologi. Jangan sampai, tanpa disadari Anda sudah terjerumus dalam adiksi digital. Kecanduan digital akan memberi efek yang merusak fisik, psikologis hingga sosial. Ingat, gadget seharusnya membantu hidup Anda, bukan menghancurkannya.
Baca Juga
Kecanduan Digital, Definisi, Indikasi dan Cara Mengatasi