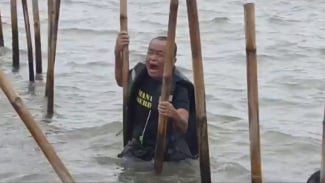- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Para peserta forum pembagian sertifikat tanah pada Selasa siang pekan terakhir Oktober itu mulanya khidmat menyimak pidato Presiden Joko Widodo. Namun, seketika hening saat Presiden mengubah topik pidato dan mengeluhkan reaksi sebagian elite politik yang menyoal kebijakan pemerintah memberikan dana untuk kelurahan pada 2019.
Siang itu, usai membagikan lima ribu sertifikat tanah di Lapangan Sepakbola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta, Jokowi mencurahkan isi hatinya. Dia merasa setiap kebijakan pemerintah selalu dicurigai untuk kepentingan politik pemilu presiden; semacam muslihat menarik simpati rakyat dengan memanfaatkan dana pemerintah. Padahal, katanya, kebijakan semacam itu jelas-jelas untuk rakyat, bukan demi urusan politik apa pun.
Dia mengingatkan, bahwa itu semua ulah sebagian elite yang memengaruhi pola pikir masyarakat. Irama bicara Presiden mulai meninggi, seraya mewanti-wanti dan mengarahkan telunjuk tangan kanannya ke angkasa, "Hati-hati—saya titip ini—hati-hati, hati-hati, hati-hati!" Memang, katanya, tak sedikit politikus yang bijaksana memahami itu sebagai komitmen pemerintah kepada rakyat. "Tapi juga banyak politikus sontoloyo. Saya ngomong apa adanya aja."
Tutur kata Presiden itu dengan cepat menuai polemik, lebih-lebih di kalangan elite politik kubu lawan. Sebagian menganggap tak patut seorang presiden mengucapkan kata semacam itu. Sebab, pengertiannya serupa dengan konyol, tidak beres, bodoh. Bahkan, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah itu dipakai sebagai kata makian.
 )
)
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat Penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Lapangan Ahmad Yani, Jakarta, Selasa, 23 September 2018. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Jokowi awalnya tak lugas menjelaskan ujaran sontoloyo itu. Namun, esok harinya dalam kesempatan lain di Tangerang Selatan, Jokowi memerinci maksud pernyataannya. Belakangan, katanya, banyak politikus gemar menggunakan cara-cara tak beradab, tak beretika, dan tak bertata krama dalam berpolitik. Dampaknya jelas, masyarakat diadu-domba dan publik dipecah-belah dan karenanya saling membenci.
"Kalau masih menggunakan cara-cara seperti itu, masih politik kebencian, politik SARA, politik pecah-belah, itu yang namanya tadi: politik sontoloyo," katanya.
Rupanya Jokowi belum selesai dengan kata-kata ejekannya. Dua pekan berikutnya, dalam kesempatan pembagian sertifikat tanah pula di Tegal, Kepala Negara memperkenalkan istilah baru: politik genderuwo.
Frasa baru itu sesungguhnya hanyalah gabungan kata politik dengan genderuwo, sesosok makhluk gaib serupa manusia yang tinggi besar dan berbulu tebal. Namun gabungan keduanya diartikan sebagai pernyataan-pernyataan elite politik yang seolah menutup mata dengan capaian-capaian pemerintah, malahan menebar pesimisme dan ketakutan pada masyarakat. "Itu sering saya sampaikan, itu namanya politik genderuwo; nakut-nakuti."
Ungkapan tak lazim Jokowi sebagai Kepala Negara itu pun segera menjadi tema baru polemik kubu lawan. Fadli Zon, wakil ketua umum Partai Gerindra, misal, bahkan menulis puisi yang ia beri judul Ada Genderuwo di Istana. "Ada genderuwo di istana, seram berewokan mukanya; kini sudah pandai berpolitik, lincah manuver strategi dan taktik," tulisnya.
Calon wakil presiden penantang, Sandiaga Uno, membalas ejekan Jokowi dengan ungkapan satire bahwa mungkin yang dimaksud Presiden aneka macam masalah dalam perekonomian nasional. "Yang berkaitan dengan ekonomi rente, mafia ekonomi, mafia pangan atau mafia lainnya, sebagai genderuwonya ekonomi," katanya.
Kubu Jokowi merasa ungkapan-ungkapan sang calon presiden sebetulnya reaksi atas pihak lawan yang kerap mengumbar kemuraman masa depan. Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, mencatat beberapa ungkapan kubu lawan, misal, Prabowo Subianto yang menyebut bahwa 99 persen rakyat Indonesia hidup pas-pasan.
Begitu pula dengan Sandiaga Uno yang mencoba menggambarkan perekonomian nasional lesu dengan metafora tempe kini setipis kartu ATM, atau betapa hampir tak berharganya uang pecahan Rp100.000 karena sekarang hanya cukup bisa beli cabai dan bawang. Menyusul lagi ungkapan Sandiaga bahwa nasi ayam lebih murah di Singapura dibandingkan di Jakarta.

Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (tengah) bersama Ketua DPP PAN Yandri Susanto (kanan) memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta, Jumat, 7 September 2018. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
Pernyataan-pernyataan seperti itu, kata Ace, tentu saja tak sesuai kenyataan; faktanya perekonomian tumbuh dan bahkan uang seratus ribu dapat dibelanjakan aneka kebutuhan pokok. Tetapi kalau gambaran-gambaran kemuraman itu dibiarkan, katanya, masyarakat bisa menganggapnya benar.
"Karena di era post-truth (politik pasca-kebenaran yang mengutamakan emosi dan keluar dari inti kebijakan) sekarang ini, lontaran seperti itu jika tidak ditanggapi, itu bisa benar. Yang rugi siapa, rakyat. Karena akan dimanfaatkan spekulan ekonomi, pedagang-pedagang untuk membiarkan itu," ujarnya kepada VIVA di Jakarta, Kamis, 15 November.
Sebaliknya, kubu Prabowo menuding lawan merekalah yang memulai memunculkan istilah-istilah aneh itu. "Yang mengeluarkan celotehan-celotehan yang enggak substansi, ya, kubu sebelah," kata juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade.
Andre mengklaim, Prabowo maupun Sandiaga tetap fokus pada substansi seputar ekonomi. Prabowo maupun Sandiaga, tiap berkunjung ke daerah menemui masyarakat, yang disampaikan selalu menyangkut perekonomian secara makro, penciptaan lapangan pekerjaan, dan harga kebutuhan bahan pokok atau pangan terjangkau.
Perang Kata-kata
Sejumlah kalangan menengarai, gejala perilaku elite politik saling sindir itu bukan cuma ekspresi upaya memerosotkan pamor antarcalon di mata masyarakat, melainkan justru bagian dari strategi kampanye. Guru besar ilmu psikologi politik pada Universitas Indonesia, Hamdi Muluk menilai, gejala itu sesungguhnya salah satu siasat mengelola perhatian masyarakat di tengah masa kampanye yang terlalu panjang—tujuh bulan, sejak 23 September 2018 sampai 13 April 2019.
Pada dasarnya, kata Hamdi, tak ada yang benar-benar baru dalam rangkaian pemilu kali ini. Dua calon presiden pun orang lama yang bersaing dalam pemilu tahun 2014; hanya masing-masing calon wakilnya yang orang baru. Begitu pula dengan partai politik yang terlibat dalam kontestasi lima tahunan itu.
Masing-masing kontestan, Hamdi berpendapat, merasa perlu semacam selingan atau intermeso mengingat masa kampanye yang begitu panjang itu. Belum lagi kalau dihitung dengan kampanye tak resmi jauh sebelum masing-masing ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Maka dilontarkanlah kata-kata tak lazim, tidak hanya ungkapan "politikus sontoloyo" atau "politik genderuwo" oleh Jokowi, melainkan juga celotehan Prabowo tentang "tampang Boyolali".

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno berdiskusi sambil ngopi bareng dengan kalangan milenial dan emak-emak, di Cafe Kabeuki, Sirnagalih, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin, 15 Oktober 2018. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)
Sandiaga memulainya dengan ragam istilah—baru atau lama yang diperbarui—seperti "kaum emak-emak", "politik cabai", "baper", "julid", dan lain-lain. Ma'ruf Amin, calon wakil presiden Jokowi, menyusul belakangan dengan ungkapan "buta dan budek" untuk mereka yang menutup mata dengan prestasi yang dicapai Jokowi.
Tetapi, menurut Hamdi, siasat itu sebetulnya dapat dibaca juga bahwa masing-masing calon menyadari masyarakat mulai jenuh dengan politik elektoral yang berjalan sekarang, sementara coblosan masih jauh. Pada aspek lain, masing-masing kandidat lama itu tak menawarkan sesuatu yang baru, entah berbentuk program atau gagasan atau terobosan, dalam politik maupun pembangunan secara umum.
Kubu oposisi atau penantang mestinya, dia menyarankan, mengajukan seperangkat program tandingan yang kuat sekalian mampu menarik simpati publik. Tetapi yang terjadi malahan jargon atau slogan belaka. "... atau justru cuma melempar seolah-olah kritik, tapi kosong, tanpa data dan argumen yang kuat." Akibatnya, kritik-kritik kosong maupun jargon dan slogan tak cukup efektif memerosotkan popularitas calon petahana.
Bahkan kelompok oposisi justru terjebak pada politik identitas dan melakukan pembunuhan karakter lewat isu-isu lawas seperti sentimen anti-PKI, anti-Islam, antek aseng atau asing, dan seterusnya.
"Informasi tentang kedua calon nyaris sudah sepenuhnya diketahui publik; tidak ada informasi baru lagi, sudah jenuh. Nah, harusnya oposisi datang menggebrak kejenuhan ini, karena dia penantang, dia yang harus ambil inisiatif, supaya masyarakat dapat perspektif baru," katanya menjelaskan.
Gejala semacam itu sebetulnya tak hanya di Indonesia melainkan global. Perilaku politik di era post-truth, sebagaimana diungkapkan pakar ilmu komunikasi politik Effendi Gazali, memang cenderung mengarah pada jargon-jargon kosong dan lebih banyak bersifat saling serang secara personal.

Pakar ilmu komunikasi politik Effendi Gazali, (VIVA/Tri Saputro)
Effendi mengutip rumusan pakar komunikasi politik American University of Paris, Jayson Harsin, tentang gejala situasi politik penuh rumor atau berita-berita hoax dan saling serang antarpolitikus. "Penggunaan medsos (media sosial) dan smartphone yang tinggi, terang-terangan menunjukkan sikap politik dan identitas, lebih menggunakan strategi berkonflik dan menyerang personality (pribadi), sambil semua mengaku memperjuangkan rakyat," ujarnya.
Penyebab situasi itu, selain fenomena global, menurut Hamdi, tak dapat dilepaskan dari betapa cairnya ideologi partai-partai politik di Indonesia, atau kalau pun ada sesungguhnya tak ada yang kuat. Ideologi pada dasarnya tetap penting sebagai landasan merumuskan visi-misi dan program kerja. Masalahnya sekarang hampir tak ada partai politik yang memiliki ideologi kuat.
Karena itulah, Hamdi mencontohkan, tak ada yang membedakan antara koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf dengan koalisi Prabowo-Sandiaga. "Dengan kata lain, platform program Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi, kalau saya bedah hampir sama, nyaris enggak ada beda, di 2014 juga gitu. Jadi apanya yang mau didebatkan," ujarnya. "Yang tersisa dari kedua calon ini, atau yang membedakan kedua calon ini, tinggal sosok."
Spontan atau Rekayasa
Andre Rosiade meyakinkan publik, kalau pun memang ada ungkapan-ungkapan yang dianggap aneh justru pada akhirnya menyebabkan polemik, itu spontan saja dan bukan dirancang dari awal. Sebab pada intinya Prabowo maupun Sandiaga mencoba menawarkan alternatif atas kegagalan pemerintah sekarang.
Jika ungkapan tertentu lalu menuai pro dan kontra, Andre berdalih, itu tak lebih hasil rekayasa pihak-pihak tertentu yang membesar-besarkan satu masalah. Dia mencontohkan polemik ucapan Prabowo tentang "tampang Boyolali". Ungkapan itu, katanya, sesungguhnya tak diniatkan untuk menghina atau melecehkan siapa pun, tetapi beberapa pihak lain mengelola isunya menjadi komoditas politik.
Dia malah menengarai itu karena kubu lawan mulai panik setelah elektabilitas Jokowi, berdasarkan beberapa hasil survei, di bawah 50 persen. Persentase itu, katanya, angka yang tak aman bagi calon petahana seperti Jokowi, padahal pemilu tinggal lima bulan.
"Mereka," Andre menengarai situasi di tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf, "Enggak nyangka survei Pak Jokowi itu enggak naik-naik, sehingga mulailah muncul kepanikan dari Pak Jokowi sendiri juga; keluarlah itu pernyataan sontoloyo, genderuwo."

Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto (kanan) saat kegiatan kampanye di Boyolali, Jawa Tengah. (Twitter.com/@Gerindra)
Dia pun menepis penilaian sebagian kalangan bahwa perang kata-kata aneh dan tak penting itu meniru kesuksesan Donald Trump mengalahkan Hillary Clinton dalam pemilu Amerika Serikat tahun 2016. Sekali lagi, katanya, Prabowo maupun Sandiaga hanya berfokus pada masalah perekonomian. "Jadi kita enggak mau ikut-ikutanlah seperti itu, enggak mau lempar pernyataan kontroversial."
Kubu Jokowi mengakui kebalikan dari kubu Prabowo. Ungkapan-ungkapan ejekan yang cenderung kasar itu sebenarnya bagian dari siasat saja, meski bukan diniatkan untuk memicu kontroversi atau kegaduhan, melainkan sekadar trik penyampaian agar lebih mudah dipahami kalangan awam.
Ace Hasan Syadzily mengulangi penjelasannya bahwa istilah "politikus sontoloyo" atau "politik genderuwo" dimaksudkan untuk menyangkal pandangan yang dibangun kubu lawan tentang kemuraman situasi perekonomian. Kunjungan Jokowi ke sejumlah pasar tradisional, misal, dimaksudkan untuk membuktikan harga-harga kebutuhan pokok relatif stabil dan cukup terjangkau.
Begitu pula program-program jaring pengaman sosial seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan lain-lain, dijalankan untuk memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Semua itu, katanya, "sebetulnya ingin mengatakan kepada rakyat: jangan takut! Justru jangan membuat kita menjadi pesimistis."
Dia malah menuding kubu lawan yang cenderung menerapkan strategi perang kata-kata atau kontroversial ala Trump dalam pemilu di Indonesia. Alasannya, dia mengklaim, pada dasarnya hampir tak ada kritik substantif kubu Prabowo-Sandiaga atas kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, kecuali menciptakan cerita-cerita yang tidak sesuai fakta.
"Mereka heboh, mencuri perhatian, menyampaikan gagasan yang tidak sesuai dengan fakta; menyebut rakyat Indonesia 99 persen hidup pas-pasan, yang enggak tahu sumbernya dari mana. Itu, kan, cenderung menjadi kebohongan," katanya.
Apa pun alasan atau dalih kedua pasang calon, strategi perang kata-kata itu dianggap jelas tak berfaedah, bahkan tak menambah nilai elektoral masing-masing. Malahan, menurut Direktur Lingkaran Survei Indonesia Denny JA, Adjie Alfaraby, perang kata-kata akan memperlihatkan kepada publik bahwa kedua pasang calon sama-sama buruk.
"Jadi," kata Alfaraby, "bukan pilihan mana yang lebih baik, tapi mana yang lebih buruk."
Kalau pola semacam itu diteruskan, alih-alih kembali berfokus pada tawaran program kerja, Alfaraby berpendapat, hanya bersumbangsih menguatkan pemilih loyal masing-masing calon. Sebab Jokowi maupun Prabowo sama-sama memiliki pemilih loyal hasil pemilu 2014. Artinya pula, model kampanye tak mendidik dan justru memicu kegaduhan itu tak akan menambah atau sanggup menjaring pemilih baru.
Alfaraby mengingatkan, berdasarkan hasil riset sebagian lembaga survei, calon pemilih yang belum menentukan pilihan karena masih bimbang atau ragu hingga kini masih cukup besar, kira-kira 20 persen. Jika jumlah pemilih sebanyak itu tak dijangkau, katanya, "dua-duanya (Jokowi dan Prabowo) gagal untuk memperluas basis pemilih mereka, dan menarik simpati pemilih yang mengambang."

Sejumlah warga Boyolali yang tergabung dalam Forum Boyolali Bermartabat melakukan aksi damai Save Tampang Boyolali di Boyolali, Jawa Tengah, Minggu, 4 November 2018. (ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho)
Pemilih yang awalnya ragu untuk memilih bisa jadi pada akhirnya memutuskan tidak memilih sama sekali, karena para kandidat hanya membuat kegaduhan, tanpa menawarkan alternatif perubahan.
Dia menepis kemungkinan perang kata-kata itu sesungguhnya bagian dari strategi kampenye saja, terutama untuk menaikkan popularitas masing-masing kandidat. Dugaan itu, katanya, bisa diterapkan kalau dua pasang calon sama-sama tokoh baru yang belum dikenal luas publik.
Jokowi dan Prabowo, katanya, tentu saja bukan tokoh baru, bahkan keduanya sama-sama bertarung dalam pemilu 2014. Karena itulah keduanya memiliki basis pemilih loyal. Maka strateginya mestinya bukan lagi berupaya menaikkan popularitas, melainkan merebut simpati calon pemilih baru yang sekarang masih bimbang.
Alfaraby malah mencurigai perang kata-kata sejatinya untuk menutupi kekurangan karena masing-masing calon tak memiliki program dan tawaran terobosan yang jelas. "Sehingga lebih banyak yang dikontestasikan adalah kata-kata yang lebih sensasional atau lebih sentimen." (umi)
Baca Juga
Dari Sontoloyo hingga Tampang Boyolali