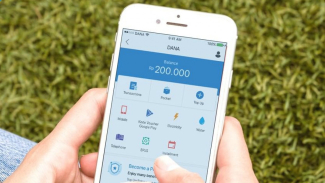Ambiguitas Hukum Perpajakan RI Masih Hambat Bisnis di Tanah Air
VIVA – Sengketa pajak PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dinilai sebagai salah satu dampak ambiguitas hukum perpajakan Tanah Air. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute, Prianto Budi Saptono.
Menurut dia, perbedaan penafsiran hukum perpajakan selama ini telah banyak terjadi di Tanah Air. Bahkan, hal ini telah menjadi salah satu hambatan bagi investasi bisa masuk cepat ke Indonesia.
Prianto bahkan mencatat pada survei World Economic Forum (WEF) 2017 menempatkan peraturan pajak di Indonesia sebagai faktor kesembilan yang menghambat kemudahan berbisnis di Indonesia.
"Ambiguitas hukum perpajakan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa ada solusi yang tuntas,” kata Prianto dalam webinar Analisis Kasus PGN vs DJP: Pemeriksaan & Metode Penafsiran Hukum Pajak, Rabu 13 Januari 2021.
Bahkan, Prianto juga menilai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja kluster perpajakan hanya mengatur beberapa hal terkait kemudahan investasi. Tanpa menyelesaikan persoalan ambiguitas hukum perpajakan yang sebetulnya juga menjadi penghambat investasi di Indonesia.
Untuk itu, kasus yang saat ini tengah membelit PGN terkait tahun pajak 2012 dan 2013 dapat menjadi salah satu buktinya. Dalam upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan tersebut sehingga PGN mesti membayar Rp3,06 triliun.
Prianto menyebut, sengketa ini muncul lantaran PGN dan Ditjen Pajak berbeda penafsiran soal status gas bumi sebagai objek pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PGN dan Ditjen Pajak dinilai sama-sama mengacu pada bukti yang kuat dan berdasar pada peraturan pajak.
“Tapi kedua pihak memiliki penafsiran yang berbeda atas peraturan perpajakan tersebut,” ujarnya.
Alhasil, majelis hakim Pengadilan Pajak mengabulkan permohonan PGN. Sementara majelis hakim MA mengabulkan permohonan PK yang diajukan Ditjen Pajak.
Baik PGN, Ditjen Pajak, dan MA sama-sama merujuk pada Pasal 4a ayat (2) UU PPN beserta penjelasannya. Ketentuan tersebut menyatakan jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu termasuk barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Nah, kata “yang diambil langsung dari sumbernya” ini menimbulkan multitafsir.
Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a UU PPN di atas di antaranya menyatakan “Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi: b. gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat”.
Berdasarkan uraian penjelasan pasal tersebut, ada dua titik multitafsir, yaitu: frasa “termasuk gas bumi seperti elpiji" dan frasa “yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat”.
Sebetulnya penjelasan yang lebih rinci ada di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252 tahun 2012. Pada pasal 1 ayat 1, gas bumi disebut merupakan barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Di pasal 2 PMK 252/2012 disebutkan Liquified Petroleum Gas (LPG) dalam tabung yang siap dikonsumsi masyarakat atau yang dikenal sebagai elpiji tidak termasuk dalam cakupan gas bumi yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
Artinya, elpiji merupakan barang kena pajak dan dikenai PPN. Sementara gas bumi yang dialirkan melalui pipa, LNG dan CNG tidak dikenai PPN.
PGN lanjut Prianto, juga berpegang pada surat konfirmasi dari Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP BUMN) pada 19 Agustus 2009.
Dalam surat tersebut, seperti termuat dalam laporan keuangan PGAS tahun 2017, KPP BUMN mengkonfirmasi kepada PGN bahwa gas bumi merupakan salah satu jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yang masuk dalam kelompok yang tidak dikenakan PPN.
"Sementara teman-teman di Ditjen Pajak bilang yang tidak kena PPN itu, misalnya Ketika PGN beli dari PHE (Pertamina Hulu Energi). Tapi barang yang sudah ada di PGN dan di trader itu barang yang kena pajak," ujar Prianto.
Terkait permohonan PK yang diajukan Ditjen Pajak ke MA terdapat risiko yang muncul selama proses peradilan. Hakim memutus perkara berdasarkan alat bukti, pengetahuan hakim dan berdasar keyakinan hakim sesuai kebenaran materil. Nah, di pengadilan khusus seperti pengadilan pajak, hakim yang mengadili perkara memiliki pengetahuan soal perpajakan.
"Sementara di level MA, bisa jadi hakimnya tidak punya pengetahuan yang cukup soal pajak. Tapi saya tidak tahu persis kondisinya bagaimana karena persidangannya juga berlangsung tertutup," ujar Prianto.