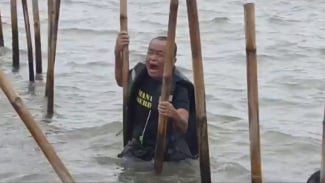Pendapat Tujuh Pakar Soal Pemindahan Ibukota
- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews - Tujuh pakar dari berbagai bidang telah berkomentar mengenai wacana pemindahan Ibukota. Dari tujuh itu, hanya satu yang secara tegas menolak usul pemindahan.
Marco Kusumawijaya
Pakar yang menolak usul pemindahan itu adalah Marco Kusumawijaya, Direktur Rujak Center for Urban Studies. Arsitek yang sering dimintai komentar soal tata kota ini berpendapat, pemindahan Ibukota dari Jakarta tidak perlu.
"Masalah-masalah Jakarta dapat diperbaiki dengan biaya lebih kecil daripada ongkos memindahkan Ibukota jika tujuannya adalah untuk membikin pemerintahan nasional berfungsi lebih baik," kata Marco di akun Twitternya, Selasa 3 Agustus 2010 lalu.
Fungsi yang dimaksud Marco adalah fungsi mengelola kepadatan Jakarta. Jakarta tidak lebih padat dari Tokyo, namun terbukti Ibukota Jepang ini berhasil mengelola lalu lintasnya sehingga tidak seruwet Jakarta. Marco juga menyebut, Jepang yang merupakan salah negara terpadat di dunia itu justru juga negara dengan tutupan hutan paling besar persentasenya.
Andrinof Chaniago
Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia ini adalah pendukung kuat pemindahan Ibukota. Andrinof yang mendalami kebijakan publik ini menyatakan, daya dukung Pulau Jawa khususnya Jakarta dan sekitarnya tak memadai lagi untuk Ibukota.
Andrinof menyatakan, satu bom sosial siap meledak di Jakarta 20 tahun lagi. Kesenjangan sosial kian tajam, kriminalitas tinggi, taraf kesehatan menurun. Gangguan jiwa meningkat.
"Kalau tak ada keputusan politik untuk pindah Ibukota, kita mungkin menghadapi ledakan sosial seperti Mei 1998," kata Andrinof pada Kamis 29 Juli 2010. Solusinya bagi Andrinof, Ibukota harus dipindahkan ke sebuah kota baru di Kalimantan.
Yayat Supriyatna
Planolog dari Universitas Trisakti, Jakarta, ini mendukung upaya pemindahan Ibukota dari Jakarta. Menurut Yayat, Jakarta tidak pernah disiapkan secara matang untuk menjadi Ibukota dengan skala sebesar sekarang. Dari sekadar kota perdagangan, kemudian harus menampung aktivitas pemerintahan dalam skala besar. "Akhirnya apa yang terjadi?" kata Yayat. "Fungsi dan perannya tidak jelas."
Sebagai pusat pemerintahan, beban itu bertambah dengan paradigma pemerintahan Orde Baru yang sentralistis. Pembangunan dirancang di Jakarta sehingga menjadi bias. "Kota ini lalu menjadi daya tarik yang besar bagi penduduk di luarnya," kata Yayat. "Ujung-ujungnya, apa-apa Jakarta, tidak terpikir mengembangkan daerah-daerah di sekitarnya."
Dan beban berlebihan itu baru terasa dekade belakangan. Jakarta mengalami kemacetan. Jakarta kekurangan air bersih namun di lain pihak kebanjiran di saat hujan sebentar. Lingkungan hijau juga tergerus oleh pemukiman.
"Idealnya, penduduknya hanya 4 sampai 5 juta jiwa, setengah dari sekarang," kata Yayat. Namun statistik terakhir, kata Yayat, diperkirakan penduduk resmi Jakarta mencapai lebih dari 9,5 juta jiwa.
Solusinya, Ibukota Pemerintahan dipindahkan namun bukan dengan membangun kota baru. Membangun kota baru, kata Yayat, membutuhkan dana yang sangat besar. Jakarta tetap menjadi Ibukota Negara, namun pemerintahan mulai diredistribusikan ke daerah-daerah. "Misalnya ke Jonggol, Karawang, Kalimantan," katanya.
Haryo Winarso
Planolog Institut Teknologi Bandung ini bersikap, pemindahan Ibukota jangan berdasarkan faktor Jakarta yang macet dan semrawut saja. Memindahkan Ibukota tidak serta merta menghilangkan segala masalah yang ada di Jakarta saat ini seperti kemacetan.
“Karena kalau alasannya untuk mengurangi kemacetan itu emosional, jangka pendek dan itu tidak benar,” kata Haryo Winarso kepada VIVAnews, Rabu 4 Agustus 2010.
Menurutnya Ibukota tidak dapat pindah ke dalam lokasi berdekatan seperti Jonggol dan Karawang karena hal tersebut hanya akan memperpanjang kemacetan. “Karena orang-orang yang terlibat pemerintahan tetap tinggal di Jakarta sehingga akan tetap macet,” katanya.
Jika Ibukota tetap berada di Jakarta maka solusinya adalah pemerintah harus menerapkan manajemen transportasi massal yang baik dan mengeluarkan kebijakan yang tidak populis seperti pembatasan kendaraan pribadi dan menaikkan tarif parkir. “Jika transportasi massal telah baik dan adanya pembatasan kendaraan pribadi maka kemacetan dapat berkurang, hal ini telah diterapkan di negara-negara lain seperti Singapura,” ujarnya.
Sonny Harry B. Harmadi
Pakar demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini mendukung pemindahan Ibukota ke luar Jakarta dan bahkan ke luar Jawa. Sonny menilai, kepadatan penduduk dan pemusatan aktivitas yang terus meningkat di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi menjadikan daerah ini tidak lagi ideal sebagai kandidat Ibukota baru Republik Indonesia.
"Jabodetabek, bahkan seluruh Jawa, sudah terlalu penuh karena 55 persen penduduk Indonesia ini berdomisili di Jawa," kata Sonny dalam dialog bertajuk 'Urgensi Pemindahan Pusat Pemerintahan' di gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu 4 Agustus 2010.
Jika pusat pemerintahan dipaksakan dipindah ke sekitar Jakarta, seperti Jonggol, Kabupaten Bogor, maka Sonny yakin hal itu hanya akan bertahan dalam waktu pendek, bukan untuk jangka panjang. "Itu seperti zero sum game, memindahkan masalah ke tempat lain tanpa menyelesaikan masalahnya," kata Sonny. Oleh karena itu, ia menilai kota di luar Jawa lebih ideal sebagai Ibukota baru RI.
Tata Mutasya
Peraih master di bidang manajemen pembangunan dari Universitas Turin, Italia, ini mendukung pemindahan Ibukota sebagai cara meratakan pembangunan. Tata menyatakan, perlu ada dobrakan atas sentralisasi pembangunan di Jawa khususnya Jakarta yang sudah terjadi sejak era kolonial.
"Selama ini tidak ada rekayasa ulang atas peninggalan kolonial itu," kata Tata dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis 29 Juli 2010.
M Jehansyah Siregar
Arsitek jebolan Institut Teknologi Bandung yang mendapat doktor di bidang perencanaan kota dari Universitas Tokyo ini mendukung pemindahan Ibukota. Namun, peneliti di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan ITB ini menyatakan, memindahkan Ibukota diperlukan visi yang kuat yang disertai regulasi yang kuat setingkat Undang-Undang.
Indonesia perlu meniru model regulasi yang diterapkan oleh Malaysia untuk membangun Putrajaya. Jika regulasi setingkat Undang-undang di Indonesia telah siap maka secara simultan langsung dibuat badan yang berkompeten untuk membangun Ibukota baru guna menghindari berbagai konflik dan spekulan.
Menurut Jehan, tidak perlu membuka lahan baru untuk membangun Ibukota baru, melainkan cukup dengan melanjutkan pembangunan kota yang telah ada. Berdasarkan berbagai kajian yang telah ada, Kalimantan pulau yang telah siap secara infrastruktur dan secara geografis Kalimantan jauh dari pusat gempa dan gunung berapi.
Kebijakan pemindahan Ibukota harus segera dilaksanakan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain. Menurut Jehansyah saat ini Indonesia telah tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan Ia memprediksi, Myanmar akan segera menyalip posisi Indonesia karena negeri itu telah lebih dahulu memindahkan Ibukota negara pada 2005 lalu.
"Mungkin nanti saat kita memulai pemindahan Ibukota, Myanmar telah maju. Semoga saja kita tidak tersalip Timor Leste," ujarnya lalu tertawa.
Bagaimana dengan Anda?