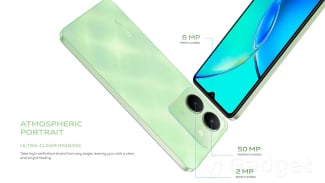Bagaimana Anak-anak Kandung Tertuduh Separatis Memandang RI

- bbc
"Saya sempat berpikir untuk melawan secara fisik di hutan. Tapi bapak bilang `kamu sekolah saja sampai nanti akhirnya kamu tahu sendiri`," kata Yosua.
"Untung waktu itu saya tidak punya jaringan ke hutan. Kalau ada, saya tidak tahu sekarang ada di mana. Saya bersyukur bisa berpendidikan jadi bisa mengerti perjuangan bisa lewat apa saja, tidak perlu berkontak senjata," ucapnya.
Saat kami berbincang dengan Yosua, dia tengah menunggu jadwal wisuda dari fakultas ilmu sosial dan politik di sebuah kampus swasta di Jakarta Timur. Setelah itu ia berencana menempuh strata dua.
Di keluarga Hiluka, dua kakak Yosua juga menempuh pendidikan tinggi. Tiga adiknya pun saat ini masih bersekolah. 
Namun mengapa sebuah keluarga petani di pegunungan tengah Papua berkeras menyekolahkan anak-anak mereka saat sang kepala keluarga dihukum penjara puluhan tahun?
"Saya berjuang untuk ideologi Papua, tapi kalau anak-anak saya tidak sekolah, saya rugi. Jadi walaupun saya diikat, diborgol, dipenjara sekian tahun, tapi pendidikan anak-anak harus tetap jalan," kata Linus.
"Saya di penjara tapi mama (istri) mereka masih di luar, dia jual noken, kayu dan ubi bakar di pasar."
"Anak-anak harus sekolah. Ada pikiran busuk agar saya dipenjara dan anak-anak saya menjadi korban. Itu tidak akan bisa terjadi. Itu sikap saya," tuturnya.
Berdamai dengan dendam
Merantau ke luar Papua menumbuhkan ragam perspektif Yosua tentang identitas dan politik. Di kampus, kata Yosua, dosen dan rektor mengetahui latar belakangnya sebagai anak tahanan politik.
Kerap dalam diskuksi di kelas, Yosua berdebat soal Papua dan keindonesiaan. Ia mengaku mulai belajar memahami orang-orang yang menganggap `Papua terlalu banyak menuntut`.
Diskursus itu hampir tak pernah dialaminya sebelum merantau karena di Papua, menurut Yosua, semua kawannya memberi rasa hormat sangat tinggi untuk anak-anak tapol.
"Dulu emosi saya naik cepat kalau bertemu orang seperti itu. Tapi sekarang saya sadar, hidup itu pilihan masing-masing," ujarnya.
"Saya tidak bisa memaksa mereka. Kalau menurut mereka itu pilihan tepat, tidak apa-apa. Tapi saya melihat realita di Papua, itu saja yang saya pikirkan."
Lantas apa emosi apa yang muncul dalam diri Yosua saat melihat dan mendengar simbol keindonesiaan, tujuh belas tahun setelah ia melihat ayahnya ditangkap dan kakeknya tewas?
"Saya sebenarnya tidak benci. Saat itu mendengar itu, yang muncul di pikiran saya adalah kasus-kasus di Papua," ujarnya.
"Jujur, emosi saya naik. Saya biasanya mengabaikan simbol-simbol itu. Tapi saya sadar, bukan bendera dan lagu kebangsaan yang salah, tapi sistem di Papua yang salah."
"Pemerintah sering memaksa kami untuk memiliki nasionalisme terhadap NKRI. Tapi nasionalisme tidak perlu dipaksa, itu akan keluar dari hati nurani kami sendiri. Muncul dari apa yang kami lihat dan rasakan," kata Yosua.
Tantangan generasi muda lebih berat
Linus berharap Yosua segera pulang ke Papua begitu meraih gelar strata dua. Titel itu, kata dia, diraih bukan untuk `menjadi pegawai` atau demi `makan dan minum enak`.
Linus berkata, Yosua harus berjuang untuk kepentingan warga Papua yang masih terpinggirkan.
"Gelar saya hanya diploma tiga. Dengan gelar itu saya bisa mewakili masyarakat Jayawijaya. Yosua sudah di perguruan tinggi, saya berharap dia lebih dari saya," ujar Linus.
Tapi perjuangan seperti apa yang diharapkan Linus kepada Yosua?
"Yosua harus berjuang secara damai, berunding di meja, tidak boleh angkat senjata. Dia bersekolah, artinya dia bisa kelola konflik. Berjuang secara demokratis, lewat jalur HAM dan hukum," kata Linus.
Bagaimanapun, Linus yakin pejuangan Yosua untuk Papua bakal lebih getir ketimbang generasinya. Sebelum ditangkap tahun 2003, Linus mengaku menikmati kebebasan berbicara yang diberikan Presiden Indonesia keempat, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Saat menjadi orang nomor satu Indonesia Gus Dur mengizinkan masyarakat Papua mengibarkan bendera bintang kejora, setingkat lebih rendah di sebelah Merah Putih.
Bintang kejora disebut sebagai simbol kultural orang Papua. Namun simbol ini pula yang belakangan menjadi dasar polisi mempidanakan seseorang.
"Dulu orang tua kami bilang `Papua` saja bisa diculik, itu waktu Orde Baru. Generasi saya beruntung karena reformasi. Gus Dur memberi hak setiap daerah untuk bicara. Saat itulah saja jadi anggota panel PDP," kata Linus.
"Tapi sekarang, walau negara demokrasi, unjuk rasa saja tidak bisa. Bicara sedikit bisa dikejar, masuk daftar pencarian orang, dan ditangkap. Situasi ini lebih berat dibanding awal tahun 2000-an."
`Saya tidak bisa berdamai`
Namanya adalah Johanis Relton Teterissa. Pemuda berusia 24 tahun ini adalah anak almarhum Johan Teterissa, terpidana kasus makar yang divonis seumur hidup penjara pada 2008.