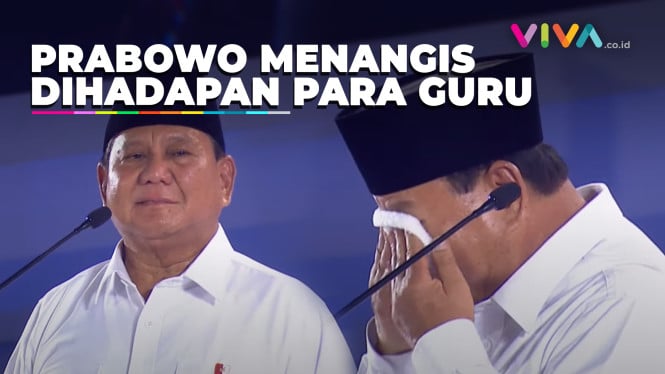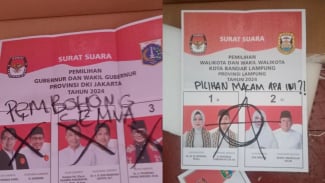Cerita Keturunan Papua yang Kehilangan Tanah Air

- bbc
Setidaknya 1.000 orang keturunan Papua dari tiga generasi berbeda saat ini tinggal di Belanda. Sebagian dari mereka sama sekali tidak bisa menginjakkan kaki di kampung halaman leluhur karena mendambakan kemerdekaan Papua.
Orang-orang itu adalah pelarian asal Nugini Belanda. Mereka mengungsi saat konfrontasi militer Indonesia-Belanda pecah di wilayah yang kini bernama Papua pada periode 1960-1962.
Sebagian lainnya adalah orang-orang Papua yang hijrah ke Belanda untuk menghindari apa yang disebut kelompok HAM sebagai militerisme Orde Baru pada awal dekade 1980-an.
Di antara mereka adalah anak-cucu pembuat bendera Bintang Kejora—simbol yang kini dianggap bagian dari kultur orang asli Papua, tapi kerap dijadikan alasan pemidanaan.
Ada pula generasi kedua seniman ternama Papua yang diyakini dibunuh pasukan elite Indonesia pada tahun 1984.
Baca juga:
- Lahir dan besar dalam konflik, bagaimana anak-anak kandung tertuduh separatis memandang keIndonesiaan?
- `Ih kalian bau` dan tudingan tukang minum: Mahasiswa Papua bicara soal rasialisme
- Investigasi BBC: Ini cara kerja jaringan bot penyebar informasi palsu tentang Papua
Orang-orang keturunan Papua di Belanda menganggap diri mereka adalah eksil, walau sebagian dari mereka lebih memilih disebut diaspora.
Membangun kehidupan di negeri orang adalah perjuangan tanpa henti. Memulai babak baru kehidupan dari nol hingga perundungan rasial harus mereka lalui.
Meski begitu mereka akhirnya meraih privilese yang tak dimiliki banyak orang asli Papua.
Lantas bagaimana mereka memandang identitas kepapuaan mereka? Dan mengapa mereka kerap meyuarakan persoalan Papua padahal hidup ribuan kilometer dari wilayah ini?
BBC News Indonesia bertemu dengan empat anak-cucu pelarian Papua di Utrecht, Belanda, beberapa waktu lalu. Berikut ini adalah kisah mereka.
`Ayah saya mendesain bendera Bintang Kejora`
Nicholaas Jouwe adalah satu dari dua orang asli Papua pertama yang duduk di pucuk kepemimpinan Dewan Nugini, saat wilayah itu masih menjadi koloni Belanda.
Selama hampir setengah abad dia hidup sebagai eksil di Delft ”kota kecil di Belanda yang luasnya separuh wilayah Jakarta Pusat.
Pada usia 85 tahun, dia kembali ke kampung halamannya.
Sejak momen itu hingga saat dia wafat di usia 93 tahun pada 2017, banyak kalangan menyebut Nicholaas akhirnya menanggalkan cita-citanya soal Papua yang merdeka.
Namun Nancy Leilani Jouwe yakin ayahnya masih menyimpan asa yang dipendam sejak memimpin komisi persiapan kemerdekaan Papua dari Belanda.
"Saya tidak mempercayai itu. Setelah berjuang lebih dari 40 tahun di pengasingan, di penghujung kehidupannya dia mencoba cara lain untuk memperbaiki kehidupan orang-orang Papua," kata Nancy.
"Bukan dengan berkonfrontasi, dia berusaha menjajaki dialog yang inklusif, sebagaimana dia melihat upaya generasi Papua setelahnya.
"Begitu tiba di Indonesia, sulit baginya melihat peluang yang tersedia. Dia kala itu sudah uzur, jadi secara personal saya tidak akan berkata bahwa ayah meninggalkan impiannya," ujar Nancy.
Nancy jelas paham betul nuansa kebatinan ayahnya. Dia menemani Nicholaas untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Indonesia tahun 2009. Nancy juga menyaksikan dan merasakan sendiri bagaimana ayahnya membangun ulang kehidupan keluarga mereka di Belanda, sembari berdiplomasi memerdekakan Papua.
Nancy belum lahir saat ayah, ibu, dan dua saudara laki-lakinya mengungsi ke Belanda tahun 1962. Dia lahir lima tahun setelah itu.
Pada masa kecilnya, Nancy merasakan `sesuatu yang hilang` dalam keluarganya. Ayahnya jarang berada di rumah. Urusan rumah tangga, termasuk membesarkan anak-anak, dikerjakan oleh ibunya, Louise Leonara.
Dari Belanda, Nicholaas berkeliling ke sejumlah negara untuk menggalang dukungan untuk kemerdekaan Papua. Dia bertamu ke kantor pusat Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Dia juga terbang ke Afrika untuk meraih solidaritas dari sesama berkulit gelap.
"Masa kanak-kanak berlalu dalam nuansa orang-orang yang melarikan diri dari tanah airnya, meski kami tidak pernah membahas masalah itu.
"Rasa bahwa kami tidak memiliki tanah air itu begitu kuat," kata Nancy.
Nicholaas bukan orang Papua biasa. Dia turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1949. Saat itu dia merupakan bagian dari delegasi Nugini Belanda.
Nicholaas juga menempuh pendidikan tinggi di Belanda sebelum akhirnya menikah dengan Louise Leonara, perempuan Belanda berdarah Solo yang melahirkan Nancy.
Pasangan transnasional itu lantas membangun rumah tangga di tanah kelahiran Nicholaas: Papua.
Semuanya kemudian berjalan mulus untuk keduanya. Nicholaas diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Nugini pada 1961. Nancy berkata, orang-orang Papua yang diberi jabatan pada institusi itu merupakan anak-anak kepala suku.
Lembaga ini, menurut banyak literatur, dibentuk Belanda sebagai bagian dari persiapan kemerdekaan Papua yang didasarkan pada hak menentukan nasib sendiri.
Salah satu yang dilakukan Dewan Nugini adalah merancang bendera yang nantinya digunakan Papua setelah lepas dari Belanda.
Nancy—akademisi sekaligus penulis isu dekolonialisasi—menyebut Papua saat itu membutuhkan simbol bersama untuk menyatukan penduduk yang terbagi dalam sejumlah kelompok suku.
"Nasionalisme Papua saat itu harus digairahkan dan sebuah bendera dapat mempersatukan semua kalangan," tuturnya.
Dewan Nugini lalu menggelar sayembara. Nicholaas, kata Nancy, adalah salah satu orang yang mengajukan desain bendera Papua. Bendera itu terdiri dari sebuah bintang berlatar merah menyala di sebelah kiri. Di sisi kanan terdapat tujuh garis biru dan enam garis putih.
Garis biru menyimbolkan tujuh suku besar, sedangkan garis putih merujuk gagasan enam provinsi yang bakal dibentuk setelah kemerdekaan.
Desain Bendera Bintang Kejora dimaknai berbeda oleh berbagai kalangan. Seorang anggota Dewan Nugini, Markus Kaisepo, misalnya, menilai bahwa warna merah, putih, biru merujuk pada Koreri—kepercayaan dalam mitologi Biak. Ketiganya, kata Markus, menyimbolkan keyakinan, kedamaian, dan keberanian.
Markus mengatakan ini dalam buku yang disusunnya bersama antropolog Australia, Nonie Sharp, The Morning Star in Papua Barat.
Pada akhirnya desain Nicholaas memenangkan sayembara. Bendera Bintang Kejora berkibar pertama kali pada 1 Desember 1961. Pada momen itu pemerintah kolonial Belanda juga meresmikan pergantian nama Nugini Belanda menjadi Papua Barat.
Namun konfrontasi yang dilakukan pemerintah Indonesia mengubah segalanya. Pertempuran bersenjata pun pecah antara Belanda dan Indonesia.
Pada Januari 1962 pertempuran di Laut Arafuru berlangsung. Tujuh bulan setelahnya Nicholaas, Louise, dan dua putra mereka tiba di Amsterdam. Mereka melarikan diri dari ancaman di Papua dan memilih menghadapi ketidakpastian baru di Belanda.
"Para politikus muda Papua berseberangan dengan keinginan Indonesia. Mereka yang berperan dalam proses memerdekakan Papua menghadapi kondisi yang tidak menentu.
"Ayah saya diberitahu bahwa dia bisa saja dibunuh atau setidaknya disiksa jika bertahan di Papua. Jadi dia memang harus pergi dari sana," kata Nancy.
Tumbuh dalam keluarga eksil di Belanda bukan perkara mudah bagi Nancy. Apalagi kulitnya berwarna.
Perlakuan rasial dia rasakan pada usia yang sangat belia: delapan tahun. Ketika itu teman sebayanya mengucapkan hinaan yang kerap dilemparkan kepada orang-orang berkulit hitam.
"Saya ingat betul pertama kali saya dicaci seperti itu. Waktu itu saya sedang bermain di halaman sekolah dan mereka mengatakan kata kasar itu," kata Nancy.
"Saya juga ingat waktu berusia 10 tahun, orang-orang memanggil saya sebagai orang Maluku. Ketika itu, Maluku adalah sebuah umpatan," ucapnya.
Pada tahun 1977, sembilan eksil asal Maluku Selatan membajak kereta di Groningen, Belanda. Mereka menuntut janji pemerintah Belanda terkait kemerdekaan Republik Maluku Selatan.
Dua dari sekitar 50 sandera tewas dalam pembajakan itu. Enam penyandera tewas di tangan Marinir Belanda.
"Saya terus belajar agar kuat menghadapi perundungan itu," kata Nancy.
Tumbuh dewasa, Nancy menenggelamkan diri dalam pergaulan komunitas eksil Papua. Tidak seperti dua saudara laki-lakinya, dia nyaris tidak pernah absen mengikuti Pesta Papua.
Di sisi lain, berbagai cerita dan legenda Papua yang dipaparkan Nicholaas memunculkan imajinasi tentang kampung halaman dalam benak Nancy.
Nancy berkata, identitas kepapuaannya menguat saat dia membaca sejumlah tulisan ayahnya tentang kejadian di balik Penentuan Pendapat Rakyat atau Perpera.
Rasa memiliki tanah air itu akhirnya menyeruak saat Nancy untuk pertama kalinya tiba di Bandara Sentani, Jayapura. Kala itu tujuan akhirnya adalah pulang ke Kayu Pulau, tempat kelahiran ayahnya.
"Ketika kaki saya menyentuh tanah di Sentani, saya merasa energi bumi menjalar ke kaki dan tubuh saya. Bumi seolah berkata kepada saya, `selamat datang kembali`," ucapnya.
Nancy menyebut Nicholaas tidak pernah memaksanya meneruskan asa kemerdekaan Papua. Tapi pada akhirnya jalan hidup Nancy tetap tidak bisa lepas dari asal usulnya.
Nancy sempat memimpin Papua Cultural Heritage Foundation (PACE), sebuah lembaga nirlaba di Utrecht mengarsipkan berbagai catatan terkait Papua.
Nancy juga menulis sejumlah buku bertema Papua dalam bahasa Belanda. Salah satu bukunya mengungkap eksistensi dan pergulatan perempuan keturunan Papua di Belanda: Papua`s? Oja, die bestaan echt, he? Een inventarisatie van de Positie van Papuavrouwen in Nederland, 1958-1992.
Namun apakah Nancy bisa benar-benar berempati pada orang-orang Papua yang hidup dalam berbagai keterbatasan?
Merujuk data Badan Pusat Statistik, indeks pembangunan manusia di Papua dan Papua Barat selalu menjadi yang terendah di Indonesia selama tahun-tahun terakhir.
Sebagian warga Papua kini tinggal di pengungsian karena terjebak dalam konflik bersenjata antara aparat dan milisi pro-kemerdekaan. Sebagian lainnya hidup dengan layanan dasar yang sangat minim.
Nancy tentu tidak mengalami itu. Dia bersekolah hingga perguruan tinggi. Berstatus warga negara Belanda, dia juga mendapat fasilitas dasar lainnya.
"Kami, keturunan Papua di Belanda, memiliki privilese. Tapi kemewahan itu menuntut tanggung jawab. Bagi saya, cara membayar privilese itu adalah dengan terus menyuarakan yang terjadi di Papua, " kata Nancy.
"Banyak orang di Belanda tidak tahu sejarah kolonial negara mereka di Papua. Fakta bahwa sejarah itu dilupakan sungguh menyakitkan. Tugas saya adalah menjaga kisah itu tetap hidup.
"Tapi banyak juga orang Indonesia yang tidak tahu apa-apa tentang Papua. Suatu kali dalam perjalanan udara, seseorang bertanya mengapa saya pergi ke Papua.
"Orang itu bilang, saya lebih baik pergi ke Bali atau kota lain di Jawa. Jelas ada sesuatu yang harus diubah dalam pola pikir itu," ujar Nancy.
Jalan hidup yang dipilih Nancy terus bergulir, termasuk ketika ayahnya memutuskan menerima undangan pemerintah Indonesia untuk pulang ke Jayapura pada tahun 2009. Ketika itu Nicholaas bertemu berbagai pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Keputusan Nicholaas menjadi kabar sensasional, tapi juga membuat banyak kalangan bertanya-tanya.
Hari ini, sikap Nicholaas itu masih terus dibingkai oleh banyak figur publik dan media massa, bahwa pendiri Gerakan Operasi Papua Merdeka—cikal bakal OPM—pada akhirnya mendukung NKRI.
Dalam buku berjudul Kembali ke Indonesia: Langkah, Pemikiran, dan Keinginan, Nicholaas menyebut perjuangannya dari pengasingan adalah pilihan keliru. Dia juga menulis bahwa dia memilih tidak kembali ke Belanda untuk "membantu pembangunan Papua".
Nicholaas memang tak lagi menjadi eksil hingga menghembuskan nafas terakhir di Jakarta pada 2017. Dia wafat dengan status penerima Bintang Jasa Naraya dari Presiden Indonesia.
Terlepas dari sikap ayahnya, Nancy yakin Papua belum bebas dari persoalan. Menurutnya, hak-hak orang Papua sebagai warga negara belum dihargai oleh pemerintah Indonesia—anggapan yang dibantah Presiden Joko Widodo dalam wawancara dengan BBC.
Dan Nancy percaya ayahnya tidak benar-benar berhenti memimpikan Papua yang `bebas` sesaat sebelum menutup mata untuk yang terakhir kalinya.
"Dia tidak mengungkapkan apa yang dia pikirkan saat itu dan saya rasa semuanya tetap sama baginya, bahwa orang-orang Papua harus mendapat hak untuk menentukan nasib mereka sendiri," kata Nancy.
Presiden Joko Widodo: `Papua adalah bagian dari Indonesia`
Dalam wawancara eksklusif dengan BBC baru-baru ini, Presiden Joko Widodo berkata telah menggencarkan pembangunan infrastruktur dan hendak mengejar sisi pembangunan sumber daya manusia di Papua.
Presiden Jokowi juga menyatakan ingin tanah Papua damai seraya menegaskan bahwa Papua dan orang Papua adalah bagian dari Indonesia.
"Saya kira semua yang berada di teritorial Indonesia adalah rakyat Indonesia. Dan ini adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus kita bangun bersama-sama.."
Presiden Jokowi menggarisbawahi bahwa dia sudah mengajak kubu prokemerdekaan untuk berdialog.
"Saya sudah mengajak mereka [kubu prokemerdekaan] untuk berbicara bagaimana membangun Papua bersama-sama, bagaimana bersama-sama bisa mensejahterakan masyarakat, bagaimana mengejar ketertinggalan agar bisa sama sejajar dengan saudara-saudara yang lainnya. Saya kira nanti kalau ini direspons, akan lebih baik."
`Ayah saya dibunuh tentara, saya sangat marah`
Raki masih berada dalam kandungan ibunya ketika ayahnya yang bernama Arnold Clement Ap, ditahan di penjara Jayapura, pada awal 1984.
Arnold ditahan sejak November 1983. Itu bukanlah kali pertama dia dijebloskan ke penjara.
Sore itu, setelah kunjungan ke penjara, ibunya, Corrie Bukorpioper, bersama tiga saudara laki-lakinya, menempuh perjalanan di atas perahu melintasi perbatasan. Tujuan mereka adalah Vanimo, sebuah kota di Papua Nugini yang berjarak sekitar 100 kilometer dari Jayapura. Mereka mengungsi.
Dalam pengasingan di Black Wara Camp, Mansorak alias Raki Ap akhirnya dilahirkan. Namun dia ditakdirkan untuk tidak pernah melihat wajah ayahnya secara langsung. Arnold meninggal pada April 1984. Saat itu Raki adalah bayi yang masih merah.
Jenazah Arnold ditemukan di Pantai Pasir Enam, di bagian timur Jayapura. Menurut sejumlah catatan kelompok HAM, Arnold ditembak dalam sebuah skenario operasi.
Dalam catatan sejarawan Robin Osborn dan George Aditjondro, aparat secara sengaja melepas Arnold dan mendorongnya melarikan diri dari Jayapura lewat jalur laut. Pada momen pelarian itulah, menurut keduanya, Arnold ditembak.
Tidak pernah ada investigasi yang dibuka kepada publik terkait kematian Arnold. Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Mochtar Kusumaatmadja, menuding Arnold adalah bagian dari Organisasi Papua Merdeka.
"Marah. Itu mungkin adalah kata yang tepat. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaan saat tahu cerita kematian ayah saya," kata Raki.
Corrie mengisahkan cerita itu kepada Raki saat putranya itu berumur 16 tahun. Saat itu mereka sudah menetap di Den Haag, Belanda.
Itulah untuk pertama kalinya, Corrie menyampaikan alasan di balik kepergian Arnold. Dia bercerita sembari memperlihatkan foto Arnold yang terbaring di dalam peti jenazah.
"Itu adalah peristiwa hidup yang tidak akan pernah saya lupakan. Tapi saat itu, sebagai anak berumur 16 tahun, saya tidak tahu harus berbuat apa," kata Raki.
Arnold Ap dikenang lewat beragam karya yang pernah diciptakannya. Pada masa itu dia adalah musikus paling ternama di Papua. Bersama grup musiknya, Mambesak, Arnold merekam lagu-lagu dalam 30 bahasa lokal.
Lewat Mambesak, Arnold menggugah nasionalisme orang-orang Papua, kata antropolog asal Australia, Diana Glazebrook.
Pada dekade 1970-an, misalnya, Arnold pernah melontarkan kritik soal liturgi ibadah banyak gereja Protestan yang berorientasi ke negara Barat. Dia lalu mengaransemen lagu-lagu ibadah berbasis tifa, ukulele, gitar, dan berlirik bahasa lokal.
Kesaksian itu ditulis George Aditjondro, yang bergaul dengan Arnold semasa bekerja di lembaga nirlaba The Irian Jaya Development and Information Service.
Namun jelas, Raki tidak pernah mendengar ayahnya menjelaskan sendiri sikap dan pemikirannya soal Papua. Lahir di pengungsian dan tumbuh di Belanda, Raki tak mengerti apapun yang terjadi di Papua.
"Mengetahui alasan di balik pembunuhan ayah dan cerita di balik keputusan ibu untuk mengungsi adalah peristiwa paling penting dalam kehidupan saya," ujar Raki.
"Saya tidak pernah membaca tentang Papua yang dikoloni Belanda. Saya tidak menemukan itu saat membaca buku sejarah di sekolah.
"Berbagai cerita itu mendorong saya untuk mencari tahu lebih banyak tentang ketidakadilan yang terjadi di Papua," ucapnya.
Dari situlah Raki kemudian mulai menggelorakan tuntutan kemerdekaan Papua. Dia bertemu Benny Wenda saat berumur 20 tahun. Ketika itu Benny sudah dua tahun melarikan diri dari pemidanaan kasus penyerangan kantor polisi dan pembakaran toko di Jayapura pada 2002.
Benny, yang menolak seluruh tuduhan aparat, divonis penjara 25 tahun. Setelah kabur dari LP Abepura, Benny menyeberang ke Papua Nugini, lalu menetap di Inggris sebagai penerima suaka politik.
Raki bergabung dalam gerakan yang digagas oleh Benny, United Liberation Movement for West Papua. Kakak pertama Raki, Oridek, lebih dulu berkolaborasi dengan Benny, sosok yang disebut banyak pejabat Indonesia sebagai perusuh dan pelaku makar.
"Setelah apa yang terjadi pada ayah saya, bagaimana mungkin saya tidak tergugah dengan apa yang terjadi di Papua," kata Raki.
"Hati saya menangis setiap hari. Hanya dengan mengungkapkannya secara terbuka dan memberi tahu banyak orang tentang Papua, perasaan saya itu bisa pulih," ucapnya.
Dengan pilihan yang diambil, Raki kemungkinan besar tidak akan pernah pulang ke tanah leluhurnya. Mustahil pula baginya untuk melihat pusara Arnold di Pemakaman Umum Kristen Tanah Hitam Abepura.
"Saya sungguh ingin pergi ke Papua, tapi karena aktivisme yang saya jalankan, saya tidak mungkin melakukannya," kata Raki.
Bersama Corrie, Raki, Oridek, dan dua saudara mereka yang lain, yaitu Mambri dan Erisam, menetap di Den Haag sejak 1985. Mereka mendapat peluang membuka lembaran kehidupan baru saat mengungsi di East Awin, Papua Nugini.
Di Belanda, empat bersaudara ini berkesempatan untuk bersekolah. Itu adalah impian Arnold saat ia meminta Corrie membawa anak-anak mereka lari dari Jayapura.
Keluarga ini menyatu dengan eksil lain yang sudah lebih dulu tinggal di Belanda. Raki belakangan bekerja di Kementerian Dalam Negeri Belanda. Mambri, anak kedua dalam keluarga ini, meninggal pada tahun 2020.
"Di Belanda, saya memiliki banyak privilese. Saya bebas mengutarakan apapun tanpa perlu takut dipenjara. Jika saya membawa Bendera Bintang Kejora, polisi tidak akan menangkap saya," ujarnya.
"Saya bisa bersekolah, mendapat pekerjaan. Tapi itu semua menghadirkan tanggung jawab yang harus saya bayar kepada orang-orang Papua.
"Itulah alasan mengapa saya berusaha menjadi suara bagi mereka," tuturnya.
Tidak seperti Arnold yang bertalenta seni, Raki tidak bermain gitar, menciptakan lagu, atau menceritakan mop. Tapi di hadapan kami dia berusaha menyanyikan salah satu lagu terakhir yang dibuat ayahnya sebelum April 1984.
"Hidup ini suatu misteri. Tak terbayang, juga tak terduga. Beginilah kenyataan ini, aku terkurung di dalam duniaku.
"Yang kudamba, yang kunanti. Tiada lain hanya kebebasan."
Lini masa status Nugini Belanda hingga masuk Indonesia
Akhir abad ke-19
Pulau Nugini dikuasai tiga otoritas berbeda. Belanda menguasai Nugini sebelah barat, sedangkan sisi timurnya terbagi menjadi dua teritorial, sebelah utara dipegang Jerman sementara bagian selatan diduduki Inggris.
1949
Pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada Konferensi Meja Bundar tidak mencakup wilayah Papua Barat.
Belanda menjanjikan kemerdekaan tersendiri bagi masyarakat di koloni ini karena menganggap mereka berbeda dengan masyarakat Indonesia.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia mendesak Papua Barat masuk dalam wilayah kedaulatan mereka. Alasannya, Papua Barat adalah bagian dari Hindia Belanda.
Dekade 1950-an
Perselisihan status Papua Barat terus berlanjut. Sengketa ini rutin dibahas dalam Sidang Umum PBB.
1961
Belanda membentuk Dewan Nugini dengan klaim mewujudkan janji kemerdekaan Papua Barat. Lembaga itu meresmikan Bendera Bintang Kejora dan `lagu kebangsaan` Hai Tanahku Papua.
1962
Sengketa terus memanas. Indonesia mulai mengirim pasukan tempur ke Papua Barat dalam Operasi Trikora. Pertempuran di Laut Arafuru pecah pada awal tahun ini.
Belanda mengadukan ini ke PBB, tapi Presiden Sukarno membuat klaim bahwa pasukan Indonesia memasuki wilayah yang merupakan bagian dari negara mereka.
Pada periode ini, gelombang pengungsian keluar dari Papua Barat terjadi.
Agustus 1962
Perjanjian antara Indonesia dan Belanda ditandatangani di New York dalam forum yang ditengahi oleh PBB. Merujuk kesepakatan itu, administrasi Papua Barat diserahkan kepada badan khusus PBB, yaitu UNTEA.
Dan enam tahun setelah perjanjian itu, Belanda diwajibkan keluar dari Papua Barat. Pada saat yang sama, referendum tentang merdeka atau bergabung ke Indonesia harus digelar.
1969
Merujuk Perjanjian New York, setiap penduduk Papua memiliki hak untuk mengikuti referendum. Namun akhirnya hanya 1.025 orang yang memberikan suaranya pada jajak pendapat ini. Seluruhnya memilih bergabung ke Indonesia.
Meski begitu, sejumlah dokumen, salah satunya laporan jurnalistik yang mendokumentasikan ajang itu, menyebut terjadi proses yang tidak adil dan intimidasi dalam referendum Papua Barat.
Merujuk hasil Perpera, Papua Barat akhirnya menjadi bagian dari NKRI.
"Saya tidak dianggap orang Papua, tidak juga diakui sebagai orang Belanda"
Ayah saya, bersama saudara kandung dan ibunya, datang ke Belanda tahun 1962. Mereka harus melarikan diri dari Papua karena mereka takut menghadapi invasi Indonesia. Kakek dan saudara tertua ayah saya menyusul ke Belanda satu tahun berikutnya.
Saat itu situasi mulai berbahaya bagi orang-orang di Papua. Kakek saya bekerja untuk pemerintah kolonial Belanda. Itulah alasan kenapa dia dan keluarganya pindah ke sini. Kakek cemas dia akan dibunuh atau setidaknya disiksa jika ditangkap.
Mereka datang ke Belanda lewat jalur udara. Ayah selalu bercerita tentang peristiwa itu, bahwa dia naik pesawat Dakota.
Hari-hari setelah tiba di Belanda sangat berat bagi ayah saya. Waktu itu cuaca sangat dingin—salah satu musim dingin terburuk pada masa itu. Anda bisa bayangkan, seseorang yang terbiasa hidup di kawasan tropis tiba-tiba hidup di tengah musim dingin.
Kakek datang tanpa membawa apapun. Dia kehilangan semua kepemilikannya. Keluarganya tidak mempunyai apapun, kecuali komunitas Papua yang sudah mengungsi lebih dulu.
Tapi kehidupan mereka saat itu juga tidak mudah karena diskriminasi. Bagi saya, ayah adalah laki-laki kulit putih karena kakek saya keturunan Belanda, sedangkan nenek asli Manado.
Kakek lahir di sini, lalu datang ke Hindia Belanda pada dekade 1920-an. Namun ayah tetap menghadapi perundungan. Sangat sulit baginya beradaptasi dengan kehidupan baru.
Keluarga ayah dulu tinggal di Kaimana. Mereka berbicara dalam bahasa Melayu Papua dan Melayu Maluku. Saaat ayah pindah ke Belanda, dia terganjal bahasa.
Ayah juga sulit beradaptasi dengan lingkungan. Di Papua, dia tinggal dalam masyarakat yang terbuka.
Ketika dewasa, ayah bergaul erat dengan komunitas Papua. Dia turut serta dalam unjuk rasa terkait Papua di Den Haag.
Pada 1995, ayah dan ibu menikah di Papua. Ibu saya keturunan Biak. Ibu ikut pindah ke Belanda setahun setelahnya.
Dan saya pun lahir di Belanda. Di rumah, ibu selalu mengajari kami untuk berbicara dalam Bahasa Melayu. Dari situ saya mulai mengerti identitas saya dan alasan mengapa saya berbeda dengan anak-anak lain di sekolah.
Saya satu-satunya anak dengan kulit berwarna di kawasan tempat tinggal kami. Sulit untuk beradaptasi dengan situasi itu. Saya bisa berbahasa Belanda, tapi saat ingin mengungkapkan perasaan, saya memakai bahasa Melayu. Tidak ada yang memahami apa yang saya katakan.
Nama saya juga terdengar sangat `putih`. Ketika saya menghadiri wawancara kerja, wajah orang-orang di kantor itu berubah begitu melihat saya datang. Mereka mungkin mengira saya orang berkulit putih.
Pelan-pelan saya mempelajari sejarah keluarga bahwa kami memiliki darah Biak. Saya berusaha mengerti adat-istiadat, lagu, dan juga bahasa Biak.
Tanggal 1 Desember adalah momen di mana saya selalu belajar lebih dan akhirnya mengetahui beragam peristiwa yang terjadi di Papua, termasuk kenapa banyak orang tidak tahu-menahu tentangnya.
Sulit bagi saya melihat identitas diri. Bagi orang-orang di sini, saya bukan laki-laki Belanda. Tapi saat saya datang ke Papua, saya tidak dilihat sebagai orang Papua.
Namun saya melihat diri saya sebagai orang Papua. Leluhur saya ada di Biak. Namun saya juga berakar pada keluarga di Belanda dan Manado.
Saya selalu menyebut diri sebagai orang Papua karena faktor ibu dan budaya yang diajarkan kepada saya—yang akhirnya saya hidupi.
Benar bahwa saya memiliki privilese. Saya tidur di bawah atap dan selalu ada makanan di meja makan. Banyak orang di Papua tidak merasakan itu.
Bersama Julia Jouwe, tiga tahun lalu saya membuat wadah bernama Young Papua Collective. Kami ingin menyatukan generasi ketiga Papua di Belanda.
Banyak perbedaan pemikiran antara generasi tua Papua di Belanda. Banyak dari mereka akhirnya keluar dari komunitas. Kami ingin anak-anak muda, apapun ideologi mereka, bisa bersatu.
Sedikit dari generasi saya yang mengerti tradisi, bahasa, lagu, dan cerita tentang Papua. Mereka tidak pernah bersentuhan dengan itu. Saya beruntung tumbuh di dalam komunitas sehingga tahu sedikit tentangnya.
Seperti kata tete (kakek) Markus Kaisepo, "kita tetap harus bersatu karena kita punya satu tujuan. Tujuan ini untuk Papua."
Orang Papua di Belanda semakin berkurang. Kalau kami hidup sembarangan, identitas dan adat akan hilang. Semua orang muda akan lupa.
Jadi walau ideologi berbeda, termasuk kalau ada yang mendukung Indonesia, masuk komunitas ini juga tidak masalah. Markus Kaisepo bilang, "biar kamu orang Papua asli, China, Jawa, orang apa saja, kalau kamu punya hati untuk Papua, kamu juga orang Papua".
`Kematian kakek membuka mata saya tentang Papua`
Julia Jouwe adalah generasi ketiga eksil Papua di Belanda. Kakek dari garis ayahnya adalah Nicholaas Jouwe, pendesain Bendera Bintang Kejora sekaligus pembentuk cikal bakal Organisasi Papua Merdeka.
Namun bukan hanya Papua yang mengalir dalam darah Julia. Neneknya, Louise Louinara, adalah perempuan keturunan Belanda-Jawa. Ibunya, Inggrid van Bilzen, merupakan perempuan asal Belanda.
Julia berpikir ulang ketika kami bertanya apakah dia merupakan seorang eksil Papua di Belanda. Menurutnya, istilah yang tepat untuk mendeskripsikan dirinya adalah diaspora.
Julia kini berumur 24 tahun. Dia lahir di Belanda ketika Orde Baru nyaris tumbang di Indonesia.
Peristiwa Biak Berdarah terjadi pada Juli 1998. Julia masih bayi saat kejadian yang diawali pengibaran Bendera Bintang Kejora dan orasi kemerdekaan Papua itu berakhir pada tewasnya sejumlah warga warga sipil dan penangkapan massal oleh aparat.
Julia juga belum masuk ke bangku sekolah saat Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay, dibunuh anggota Kopassus tahun 2002.
Berbagai peristiwa di Papua terasa begitu jauh dari Julia pada masa itu.
Di Belanda, pada masa kanak-kanaknya, Julia mulai mendengar ragam cerita tentang sebuah pulau yang tak bisa dibayangkan. Nicholaas menceritakannya kisah cenderawasih, "burung dari surga" yang hanya hidup di Papua.
"Aku hidup di Belanda dan begitu menyatu dengan kehidupan di negara ini, dulu aku tidak pernah menganggap Papua sebagai bagian dari diriku," kata Julia.
"Sulit untuk menerima identitas kepapuaan karena semua orang di sekitarku adalah orang berkulit putih dan aku sedang berusaha tumbuh dalam masyarakat ini.
"Apa yang diceritakan kakek terdengar seperti mitos, sesuatu yang disebut surga dan burung cenderawasih. Aku dulu tidak percaya pada kisah-kisah itu," ucapnya.
Dan hari-hari Julia pun berlalu. Papua tidak mendapat tempat dalam kehidupan masa kecil dan remajanya.
Sampai pada tahun 2009, ayahnya, Nico, bersama tantenya, Nancy, terbang ke Indonesia untuk menemani kakeknya untuk pertama kalinya pulang ke Papua.
Pada momen itu, segala hal yang berkaitan dengan Papua mulai masuk ke relung pikirannya.
Saat kakeknya memutuskan untuk menetap di Jakarta dan meninggalkan status sebagai eksil pada 2010, sejarah keluarga Jouwe dalam bingkai Papua semakin mengambil tempat dalam kehidupan Julia.
"Aku mulai menyadari bahwa keluargaku memiliki cerita yang luar biasa," ujarnya.
Namun mata Julia baru benar-benar terbuka melihat Papua pada tahun 2017. Ketika itu Nicholaas baru saja wafat di Jakarta. Situasi akhirnya membawa Julia melihat pulau yang belasan tahun lalu dikisahkan kakeknya.
Julia untuk pertama kalinya menginjakkan kakinya di Papua—tanah leluhurnya. Bersama keluarga besar Jouwe, Julia mengantar Nicholaas ke tempat peristirahatan terakhir.
Laki-laki yang dulu digadang-gadang akan memimpin kemerdekaan Papua dari Belanda itu dimakamkan di Pulau Kosong, diseberang Pelabuhan Jayapura. Nicholaas wafat dalam status ondoafi atau pemimpin tertinggi dalam klannya.
"Itu adalah momen saat aku terlibat secara personal dengan keluarga besarku. Saat itu aku mulai membaca catatan sejarah tentang apa yang terjadi dengan Papua, terutama keluargaku," kata Julia.
"Momen itu sungguh membuka mataku. Aku tidak pernah melihat kakek dihormati dan dirayakan oleh banyak orang di Belanda. Di negara ini tidak ada yang tahu siapa dia dan peran yang pernah dilakukan.
"Ketika aku hadir dalam pemakaman itu, melihat orang-orang begitu tersentuh dan menangis, aku menyadari sesuatu yang besar, yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya," ujar Julia.
Dari situ Julia pulang ke Belanda membawa hasrat mendalami diri dan latar belakangnya. Jarak ribuan kilometer kembali memisahkannya dari Papua, tapi dia berusaha tetap menyalakan kepapuaannya. Dia rutin berkomunikasi dengan saudara-saudarinya di Papua.
Kata-kata Nicholaas kepadanya terus teringang dalam benaknya. "Suatu hari nanti kamu akan membantu orang-orang Papua," ucapnya mengulangi perkataan kakeknya.
Bukan hanya keluarga, Julia juga mengembangkan jejaringnya dengan muda-mudi Papua lain. Dia menggagas Young Papuan Collective bersama Samuel van Voorn, kawannya yang juga berstatus generasi ketiga eksil Papua di Belanda.
Gerakan ini belum menghasilkan apapun, kata Julia. Meski begitu dia berupaya agar ruang kolektif itu bisa menjadi wadah kerja sama generasi muda Papua yang tersebar di berbagai negara.
"Saat ini apa yang kami lakukan tidak politis. Kami ingin bekerja sama dengan mereka yang tinggal di Papua. Mereka tentu tidak nyaman jika wadah ini menyatakan hal-hal yang terlalu politis," ujar Julia.
"Tapi jelas, segala sesuatu yang berkaitan dengan Papua bersifat politis dan sangat sulit untuk menghindari itu," ucapnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Julia aktif sebagai pemengaruh dalam isu hak asasi manusia di Papua. Akun media sosialnya diikuti sekelompok muda-mudi Papua.
Julia menyadari berbagai privilese yang dia miliki. Dia tinggal dan berstatus warga negara Belanda. Yang dia dapatkan, dari pendidikan, jaminan atas rasa aman dan beragam hak dasar lainnya, tidak dimiliki banyak muda-mudi Papua lainnya.
"Aku sungguh ingin menggunakan privilese ini. Ada tanggung jawab moral dan etis di baliknya," kata Julia.
"Namun di sisi lain aku tidak merasakan previlese yang besar. Aku sungguh rindu dengan Papua. Aku tidak bisa merasakannya di sini," ucapnya.
Tulisan ini merupakan bagian dari liputan khusus Otonomi Khusus Papua di situs BBC News Indonesia.
Callistasia Widjaja dan Samuel Robinson berkontribusi untuk liputan ini.